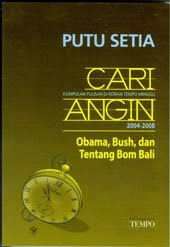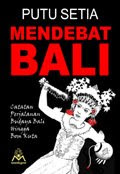Kamis, Agustus 27, 2009
Jumat, Juli 03, 2009
KPK
Di tengah riuh gemuruh kampanye calon presiden, di antara ribuan kata diumbar para tim sukses, banyak yang mencemaskan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih tepatnya, bukan keberadaan Komisi –disebut begitu saja supaya singkat— itu yang dipersoalkan, tetapi ada upaya yang membuat Komisi makin busuk. “Memangnya mangga yang bisa busuk?” kata hati saya.
Namun, saya ikut cemas kalau benar ada upaya yang sistematis untuk memperlemah kerja Komisi. Berbagai cobaan dihadapi Komisi. Ibarat pepatah, makin tinggi pohon makin keras mendapat terjangan angin. Dan “terjangan angin” itu saya rasakan ketika Wakil Ketua Komisi Chandra M. Hamzah diperiksa polisi selama tujuh jam dalam kasus penyadapan telepon seluler Rhani, cewek yang jadi saksi kunci pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Diperiksa tujuh jam? Ini yang mencemaskan, lebih-lebih bagi mereka yang tak tahu lika-liku pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Banyak muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana tekniknya polisi memeriksa seorang “terperiksa” begitu lama? Apakah pertanyaan diajukan dengan begitu pelannya dan “terperiksa” menjawab dengan terbata-bata? Atau mungkin diselingi nonton tayangan gossip di televisi? Apalagi dalam kasus Chandra M. Hamzah ini pertanyaannya –semestinya- amat sederhana.
Dari sini muncullah kekhawatiran di masyarakat, sepertinya Chandra mau “dibidik”, jika tidak kenapa mesti berlama-lama diperiksa. Kalau Chandra sampai “kena bidik” dan kemudian menjadi “tersangka”, maka berkurang lagi pimpinan Komisi setelah Ketua Komisi (Antasari Azhar) dinyatakan nonaktif. “Di sinilah pembusukan itu,” kata seseorang, entah siapa.
Apa pentingnya dan siapa yang berkepentingan dengan “busuknya” Komisi? Oh, banyak. Para koruptor, baik yang sudah merasa akan diseret maupun yang masih gentayangan di tim sukses masing-masing calon presiden, berharap Komisi bukan saja “busuk” tetapi “lumpuh”. Ketika seorang anggota dewan yang terhormat berkoar-koar di televisi dalam kapasitas sebagai tim sukses calon presiden, seorang teman menelepon saya: “Lihat orang itu, dia kan disebut-sebut menerima cek saat memenangkan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia, kapan ditangkap ya?”
Masih ada puluhan teman anggota dewan itu yang seharusnya sudah dipanggil Komisi – atau langsung diperiksa tujuh jam dan ditangkap – jika saja semua pihak mendorong Komisi untuk lebih semangat. Jadi, ini dugaan beberapa teman dan saya setuju, anggota Dewan banyak yang sebenarnya ingin agar Komisi lumpuh, bukan hanya busuk. Bukti lainnya, rancangan undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga dibahas, padahal sebentar lagi anggota Dewan berganti.
Tapi, apakah kepolisian ingin juga Komisi itu “busuk”? Saya tak mau berkomentar, takut kena masalah dan nanti “diperiksa tujuh jam”. Saya hanya ingin mengatakan, memang asal-usul adanya Komisi itu adalah para penyidik – kepolisian dan kejaksaan—dianggap “kurang semangat” dalam memberantas korupsi di negeri ini, meski pun kedua penegak hukum ini punya wewenang menangkap koruptor dan sudah dijalankan. Kalau saja polisi dan jaksa bersemangat “maju tak gentar” memberantas korupsi tanpa melihat “ada bulu atau tidak”, tak akan ada Komisi, apalagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teorinya begitu, para hakim di Pengadilan Negeri sudah cukup menghukum koruptor.
Sayangnya, ketiga calon presiden, tak jelas betul apa sikapnya. Mereka bisa bilang, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan lebih cepat lebih baik untuk tegaknya ekonomi kerakyatan, tapi mau diapakan KPK ini?
(Koran Tempo Minggu 28 Juni 2009)
Debat
Saya menyesal tidak mengikuti debat calon presiden, Kamis malam lalu. Ada acara yang tak memungkinkan menyetel televisi. Namun, teman saya mengaku lebih menyesal lagi karena menonton debat itu sampai selesai. “Tak ada perdebatannya, saya hampir mengantuk,” katanya.
“Anda jangan seperti pengamat politik. Begini salah, begitu salah. Kalau calon presiden saling melempar argumentasi, dikatakan saling serang dan saling sindir. Kalau rukun, dibilang adem ayem. Anda mau apa sih?”
Ucapan saya itu mengagetkan teman saya. “Tapi ini betul-betul bukan debat, ini hanya giliran pidato, bahkan saling dukung. Ganti dong acaranya menjadi ‘kampanye bareng’ atau apalah,” katanya.
Saya jelaskan, kultur Indonesia memang begitu, lebih-lebih para elitnya. Beraninya cuma di belakang, bukan berhadap-hadapan. Kalau Mega ada di Bekasi, ia berani menyerang SBY karena yang diserang tidak ada. Kalau Jusuf Kalla di Aceh, ia berani menyerang SBY yang ada di Malang. Sebaliknya, SBY pun ringan menyindir Mega atau JK, ketika berada di Malang. Jika ketiganya bertemu, semuanya akan rikuh. SBY kan pernah jadi bawahan Mega, JK masih menjadi wakilnya SBY. Kualat bertengkar dengan mantan bos. Adapun Mega, kalau sudah dipuji oleh keduanya, ya, tak bisa marah lagi, apalagi beliau seorang Ibu, simbol keramahan. Justru kalau terjadi perdebatan, ini melanggar petuah orangtua; “nak, jangan bertengkar di tempat ramai.” Ini budaya Nusantara, khususnya Jawa.
“Debat Barrack Obama dengan John Mc Cain kok bisa menarik? Padahal saya cuma baca teks terjemahannya,” kata teman saya.
“Itu karena tradisinya beda,” kata saya. Di Amerika Serikat, budaya debat adalah budaya keilmuan, pakai otak. Yang mendengar juga menggunakan otak. Selesai berdebat mereka salaman, penontonnya juga bisa pulang bareng. Di sini, perdebatan berarti ada ketidak-sepahaman dan itu bisa melahirkan dendam, bisa tak bicara dalam waktu lama, apalagi salaman. Perdebatan nyaris berarti pertengkaran. Penontonnya juga begitu, bisa saling menggebuk mobil saat pulang. Peserta kuis siaran langsung di televisi saja bisa berantem usai acara karena tak senang disindir.
Pengamat kita itu aneh kalau ingin menonton debat yang bermutu, ini belum zamannya. Misalnya, ada calon presiden yang mengumbar isu ekonomi kerakyatan. Lalu, calon presiden yang lain menanyakan, apakah mereka pernah membeli baju di Pasar Ciputat yang berlumpur kalau hujan itu? Jangankan beli baju, kacamata saja membelinya di mal. Kalau sakit bukannya ke Puskesmas, malah ke Singapura. Tim suksesnya juga begitu. Neolib diserang habis-habisan, tapi membeli dasi di Mal Ambasador, bukan di Pasar Cipete. Semua calon itu bermasalah soal “kerakyatan”, semuanya tak tahu isi hati “wong cilik”.
“Anda kenal Siti Musdah Mulia?” Teman saya bengong. Dia itu dosen, doktor, juga ibu rumah tangga. Suatu kali saat acara Indonesian Conference on Religion and Peace – beliau ketuanya– dia bilang ke saya: tak pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan. Padahal dia tak pernah ngomong ekonomi kerakyatan. Beda dengan tetangga saya yang memasang spanduk “Jangan Pilih Capres Neolib”, tapi membeli buku tulis untuk anaknya di Carrefour. Katanya, anaknya jijik dikerubungi lalat pasar.
Kasihan juga melihat teman saya melongo dengan “propaganda” saya. Saya hibur: “Sudahlah, bagus Anda menonton debat sampai selesai dan tak mematikan tv.” Dia menjawab kalem: “Kalau tv saya matikan, saya bisa ketiduran. Debat Kamis malam itu kan menunggu Piala Konfederasi, saya gila bola.”
(Koran Tempo Minggu 21 Juni 2009)
Prita
Di ruangan komputer sebuah sekolah menengah pertama, Ibu Guru menanyakan kepada anak didiknya: "Siapa di antara kalian yang senang mengirim e-mail menceritakan orang lain? Ayo, ngaku!"
Murid usia belasan tahun ini saling toleh sebelum sembilan orang mengacungkan tangan. Bu Guru menunjuk: "Ayo Putri, beri contoh e-mail-mu dan siapa yang kau kirimi e-mail itu." Putri tenang saja. "Bunyinya begini, Bu Guru: hai teman-teman, hati-hati dengan Baskoro, dia jahat, suka mencuri permenku. E-mail saya kirim ke sahabat kelompok dua, tujuh penerima."
Bu Guru lalu mengacungkan koran yang sejak tadi dipegangnya. "Anak-anak, menulis e-mail seperti itu sekarang berbahaya. Kalau Baskoro atau keluarganya mengadukan Putri ke polisi, Putri bisa dipenjara enam tahun dan membayar denda satu miliar. Undang-undangnya begitu, Putri mencemarkan nama baik orang lewat Internet, di koran ini ada beritanya," ujar Bu Guru. Anak didik yang sebelumnya ceria itu serentak melongo, Putri bahkan pucat mukanya.
Kisah di atas setengah fiksi. Yang fiksi dialog-dialognya, karena Luh Putri Devi, keponakan saya dari garis ibu, tak menceritakan dengan detail suasana itu. Setengahnya lagi benar, Ibu Guru di lab komputer sekolah favorit itu meminta anak didiknya berhati-hati menulis e-mail, sambil mengulas kasus Prita Mulyasari di Tangerang. Putri jadi trauma. "Sekarang takut banget deh, Paman, nggak mau lagi main Internet," katanya.
Prita, konon, juga trauma. Tak disangka, curahan hati kepada sepuluh temannya, perihal pengalaman ia dirawat di RS Omni Tangerang, akan berbuntut penjara. Bagaimana e-mail kepada sepuluh "teman pribadi" itu menyebar sampai dibaca pihak rumah sakit tentulah tak sulit dilacak. Bisa dengan teknik sederhana, misalnya, salah satu dari sepuluh orang ini meneruskan ke "teman lain", lalu tersebar ke mana-mana. Atau e-mail itu "bocor", sesuatu yang mudah terjadi di dunia maya Internet.
Prita tak membayangkan masuk penjara hanya karena menulis e-mail. Saya pun tak membayangkan juga karena, berdasarkan pengamatan saya di dunia Internet, "pencemaran nama" yang mirip itu setiap saat ada. Mailing list yang paling beradab, misalnya yang berlabel agama dengan menggunakan moderator sebagai penyaring, pun tak pernah lepas dari gosip yang menjurus pencemaran nama baik. Apalagi mailing list tanpa moderator, bahkan apalagi e-mail antarpribadi.
RS Omni sudah menggugat. Tapi lihatlah hasilnya. Tatkala Prita dipenjara, ada ratusan--jangan-jangan ribuan--posting yang mengecam rumah sakit itu dengan bahasa yang "jauh lebih mencemarkan". Bahkan muncul pemboikotan di cabang lain rumah sakit itu. Dukungan kepada Prita di Facebook mencapai ratusan ribu, setiap detik bertambah. Entah di blog dan mailing list--yang tak mungkin semua saya buka. Dunia maya, saat ini, menjadi kekuatan alternatif dalam membentuk opini publik. Kekuatan yang dahsyat.
Apa bisa kekuatan dahsyat itu diberangus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, terutama oleh Pasal 27 ayat 3 (delik pencemaran nama baik) dan Pasal 45 (denda Rp 1 miliar)? Berapa anggaran negara harus disediakan untuk membangun penjara yang menampung "pencemar nama baik" seperti Prita itu? Teramat konyol jika negeri ini sampai mendirikan Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pencemaran Nama Baik di Internet.
Lagi pula, mana batas pencemaran nama itu? Apakah "Say No to Megawati" atau "Boediono Mbahnya Neolib"--yang gentayangan di Internet--termasuk pencemaran nama baik? Perlu dirumuskan apa kriteria pencemaran itu agar jelas apakah Prita dan Putri perlu dibui atau tidak.
(Koran Tempo Minggu 14 Juni 2009)
Selasa, Juni 16, 2009
Satu Putaran
Pemilihan presiden saat ini ada kemajuan yang berarti. Calon hanya ada tiga pasang, berkurang dibanding pada lima tahun lalu, dengan lima pasang calon. Namun, berapa pun calonnya, kalau lebih dari dua pasang, sangat besar kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan presiden. Apalagi ketiganya punya kekuatan yang berimbang.
Melihat betapa sibuknya ketiga pasang calon ini memanfaatkan semua celah untuk kampanye, tak akan ada yang menang mutlak-mutlakan. Menang mutlak itu hanya ada di era Soeharto. Ini pun sejatinya bukan menang, karena Soeharto takut ada pemilihan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memilih presiden, dipaksakan memunculkan calon tunggal. Kalau sudah calon tunggal, siapa yang menang atau kalah?
Sekarang, ketika rekayasa menggiring suara rakyat tidak memberi jaminan--meski sudah diberi janji, termasuk uang sekalipun--muncul gerakan yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung satu putaran. Dasar pemikirannya bagus, bisa menghemat beberapa triliun rupiah di tengah krisis ekonomi. Cuma, Gerakan Nasional "Setuju Satu Putaran Saja" itu ketua umumnya Denny J.A. (tak usah ditanya siapa yang memilihnya jadi ketua umum) dan menggiring pemilih untuk mencontreng SBY-Boediono. Artinya, gerakan ini merupakan bagian dari kampanye SBY-Boediono.
Tentu saja tim sukses dua pasangan yang lain jadi berang. Padahal, jika menerapkan kampanye yang damai dan bersahabat, konsep satu putaran itu bisa digulirkan oleh semua pasangan dengan jargon masing-masing. Tim sukses Mega-Prabowo, misalnya, akan menyambut ide itu dengan jargon "Oke, Satu Putaran, Pilih Mega-Prabowo". Kemudian tim sukses JK-Wiranto juga setuju satu putaran dengan menawarkan jargon "Pilih JK-Wiranto, Satu Putaran Lebih Cepat Lebih Baik".
Kampanye akan lebih menghibur. Yang jelas lebih mudah dicerna masyarakat dibanding saling sindir dengan istilah-istilah yang tak membumi. Seperti pada acara deklarasi "Pemilu Damai" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Penonton televisi terhibur oleh orasi Butet Kertaradjasa, yang mengkritik banyak hal, termasuk lembaga survei yang bisa dipesan. Banyak yang tertawa, termasuk menertawakan Butet, yang begitu profesional menerima pesanan dan "membela yang bayar", sampai-sampai orasinya--ini bukan monolog karena tak ada unsur seninya--lebih panjang ketimbang orasi calon wakil presiden. Butet saat itu dibayar Mega-Prabowo.
Dalam kasus ini, dua tim sukses yang lain kecolongan dengan tampilnya Butet. Yang terjadi barangkali adalah "kelemahan intelijen". Kalau terendus Butet akan berorasi di pihak Mega-Prabowo, tim sukses SBY-Boediono tentu bisa membayar Mandra, misalnya. Lalu JK-Wiranto membayar Jarwo Kuat atau Kelik Pelipur Lara, yang sudah biasa memerankan Jusuf Kalla di "negeri mimpi". Jika bagi pelucu itu disiapkan bahan untuk "menyerang lawan", tidak ada yang tak bisa.
Rupanya kampanye sekarang ini perlu lebih banyak memakai akal-akalan atau mencuri momen karena Komisi Pemilihan Umum begitu mudah dikibuli, termasuk pada acara yang dibuatnya sendiri, meskipun ditutup dengan permintaan maaf.
Cuma, semakin banyak akal-akalan--survei dan polling, gerakan terselubung satu putaran, orasi berbalut seni monolog, perjalanan dinas tapi kampanye, dan banyak lagi--semakin terbuka akal masyarakat bahwa semua calon itu sesungguhnya memamerkan kekurangan akalnya dalam merebut suara rakyat. Kesalahan para calon dan tim suksesnya hanya satu: mengira rakyat itu bodoh, sehingga dipakailah cara kampanye yang bodoh.
(Dari Koran Tempo 14 Juni 2009)
Kamis, Juni 04, 2009
Kapongor
Suatu hari ada orang yang bertanya pada saya, apakah benar menanam pohon kelapa di depan rumah bisa kapongor. Apa itu kapongor? Tanya saya memancing, “Dimarahi Bethara,” katanya.
Saya katakan, Bethara tak pernah marah, tetapi kapongor itu betul. Nanti kalau kelapanya berbuah lalu jatuh dan menimpa anak-anak yang masih kecil, kan berbahaya.
Di hari yang lain, seseorang bertanya, apa berani menebang pohon kepuh di setra. Pohon itu sudah tua, kalau dahannya rontok berbahaya buat orang yang ada di bawahnya. Lagi pula di setra akan dibangun balai panjang untuk “mesayuban” dari terik matahari atau hujan. Saya jawab: “Potong saja.” Lalu saya ditanya lagi, apa tidak kapongor? Saya katakan; “Tidak”. Dan betul setelah bertahun-tahun tak ada yang berani menebang pohon kepuh yang dibilang keramat itu, sekarang sudah lenyap. Setra jadi asri dan ada bale “mesayuban”.
Ada lagi yang unik. Seseorang yang baru menjadi nenek konsultasi ke saya, dia mau ke balian. Dia ingin bertanya, siapa nama cucunya yang baik agar anak itu tumbuh sehat dan cerdas di masa depan. Saya tanya dulu, apa bapak dan ibunya sudah memberi nama pada anaknya itu? Sudah, katanya. Nama pemberian orang tuanya cukup panjang: Ni Putu Juniwati Putri Dewi. Nenek itu khawatir nama panjang itu akan membuat keluarga itu kepongor, karena nama-nama leluhurnya hanyalah Wayan Sobret, Ketut Manyong, Nengah Keplug dan sebagainya.
Saya katakan kepada nenek itu: “Jangan sekali-sekali menanyakan nama ke balian, nanti nama itu diganti atau dikatakan jelek. Ini nama bagus sekali, anak itu akan cerdas.” Ketika sang nenek diam, saya katakan lagi; “Kalau tanya ke balian paling disebutkan anak itu keberatan nama, lalu sakit-sakitan. Supaya sehat namanya diganti menjadi Putu Lenjog, malah nanti anak itu jadi malu.”
Kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi di pedesaan. malah ada yang sampai bentrok dalam kekeluargaan. Misalnya soal kawitan, dan ini cerita nyata. Sebuah keluarga ada anaknya yang sakit gatal-gatal, lama tak sembuh. Ditanyakan ke balian, eh, ternyata salah kawitan. Selama ini keluarga besarnya itu termasuk soroh Pasek Bendesa. Menurut balian, seharusnya Pasek Kayu Selem. Keluarga itu mantap pindah kawitan, namun keluarganya yang lain tak mau. Alasannya juga sudah menanyakan ke balian yang lain. Apa yang terjadi? Karena takut kapongor terus-menerus -- yang ditandai dengan sakit gatal itu -- keluarga yang anaknya sakit itu pindah kawitan. Ya, akhirnya pecah dadia, pecah panti dan seterusnya.
Saya mengenal keluarga besar itu dan saya tentu tak mau mencampuri urusan soroh berdasarkan omongan balian. Apalagi seumur-umur saya tak pernah bersinggungan dengan balian. Tapi saya siap menolong keluarga itu.
Pertolongan yang pertama saya lakukan, bukan soal kemana mencari soroh yang benar. Tetapi mengajak anak yang sakit gatal itu ke dokter kulit di Denpasar. Ternyata anak itu mengidap penyakit kulit akibat virus yang memang harus diobati secara benar dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya sakitnya sembuh. Setelah anak itu sehat, kepada keluarga besar itu saya minta mempelajari silsilah kawitan berdasarkan babad yang ada. Nah, terserah mereka untuk memilih, mau ke mana. Yang jelas, tak ada urusan kapongor di sini, yang ada urusan virus yang menyerang kulit yang tak bisa disembuhkan oleh obat dari Puskesmas atau loloh dari balian.
Belum lama ini ada keluarga yang juga “minta izin” ke saya, apa baik menanyakan ke balian, apakah kakek dan neneknya yang baru diaben sudah mendapat tempat yang “pas” di sana. Saya tidak heran soal ini, sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Saya tanya alasannya, meski pun saya sudah bisa menebaknya. “Ya, siapa tahu, banten ngabennya kurang ini kurang itu, atau salah runtutan upacaranya,” katanya. Saya katakan, perbuatan menanyakan ke balian itu justru melanggar ajaran agama. Pertama, karena kita menjadi tidak yakin setiap melaksanakan yadnya. Padahal syarat dari yadnya adalah keyakinan. Kedua, kita tidak tulus menyerahkan urusan ritual kepada Sulinggih yang muput, padahal ketulusan ini utama. Jangan pernah ragu dengan Sulinggih begitu kita memilih beliau untuk muput. Ketiga, tak ada urusan Hyang Pitara atau apapun sebutannya setelah diaben menjadi marah atau tak mendapat tempat yang “pas” hanya gara-gara banten. Keempat, siapa balian itu? Kalau balian itu tak pernah mempelajari tingkat pengabenan, omongannya bisa jadi ngawur.
Masyarakat Bali -- meskipun tidak begitu banyak lagi seperti dulu -- masih percaya pada balian jenis ini. Maksudnya balian untuk meluasang, balian baas pipis, balian dasaran, atau sebutan lainnya. Yakni balian yang entah dengan teknik atau ilmu yang beragam, dipercaya bisa menjadi perantara dari roh orang yang sudah tiada. Atau kalau tidak “kemasukan roh” seolah-olah tahu dan bisa menebak segala sumber yang jadi pangkah masalah “pasiennya”. Dari sinilah kemudian muncul istilah kapongor karena berbagai hal. Kapongor salah upacara, kapongor salah banten, kapongor salah memberi nama dan sebagainya.
Anehnya, jarang sekali balian berkata: “Kamu kapongor oleh Hyang Pitara ini karena suka minum arak, suka berjudi, suka metajen, suka selingkuh, suka narkoba, suka memirat.” Kalau ada balian seperti itu, mungkin baik juga, masyarakat Bali bisa lebih sejahtra.
(Editorial Majalah Hindu Raditya, edisi Juni 2009)
Neolib
Di sebuah warung berlabel “mini market” di kawasan Ubud, Bali, saya terkejut menyaksikan adegan ini. Seorang anak muda tergopoh-gopoh menuju rak obat dan bertanya pada pelayan: “Ada neolib?”
Ia tak bergurau mengucapkan kata itu. Pelayan, perempuan yang juga muda, menjawabnya dengan kalem, jauh pula dari nada canda: “Neolib untuk flu, apa neolib untuk nyeri?” Si lelaki menjawab cepat: “Neolib untuk flu.” Pelayan memberikan satu bungkus tablet bergambar kepala orang. Transaksi terjadi, lalu anak muda itu pergi.
Setengah penasaran saya mendekati pelayan. “Kenapa obat yang sudah populer itu disebut neolib?” Barulah pelayan itu tersenyum, manis juga, dan khas pelayan warung di kawasan pariwisata. “Di sini orang sudah terbiasa dengan plesetan yang dipopulerkan televisi. Semua obat dengan awalan neo disebut neolib, makanya saya tanya, neolib untuk flu atau nyeri. Sering pula disebut neolib tablet atau neolib krim,” ujar si pelayan.
Konon, plesetan itu hanya awalnya saja menimbulkan nada canda. Begitu lewat tiga hari apalagi seminggu, plesetan sudah tak ada nada candanya lagi, sudah biasa-biasa saja. Ternyata banyak juga jenis “plesetan politik”, bukan hanya neolib. Kalau ada orang yang tadinya jarang bergaul atau enggan menyapa, lalu tiba-tiba ramah, orang itu dijuluki: “kerakyat-rakyatan”. Misalnya: “Pak Dogler sekarang kerakyat-rakyatan, pasti ada maunya.”
Anehnya, julukan “kerakyat-rakyatan” hampir selalu berkonotasi negatif. Ada temannya yang lain. Ketika seorang pengendara sepeda motor meraung-raungkan mesin motornya saat melintas di depan mini market itu, petugas parkir berteriak: “lanjutkan, lanjutkan, lebih cepat lebih baik mati”. Begitu pula ketika petugas parkir menggoda cewek, pedagang bakso menggoda: “Pak Parkir, lanjutkan, lanjutkan, mumpung istri tak ada…”
Apa tahu arti neolib? Ini pertanyaan yang saya ajukan kepada pelayan warung, pedagang bakso, dan petugas parkir. Pelayan hanya tertawa karena memang tak tahu. Pedagang bakso juga tertawa, lalu dia bilang: “Saya belum gila, tak perlu neolib”. Dan ini jawaban petugas parkir, agak panjang: “Itu kan dagelan bapak-bapak di televisi. Semua bersilat kata. Semua mengaku pintar. Semua mengaku dekat rakyat. Kita nonton senang saja, banyak kata-kata baru untuk bahan becanda.” Saya tanya, kalau diberi kesempatan bicara, mau bilang apa kepada bapak-bapak itu? Tak lama berpikir, petugas parkir berkata: “Berhenti saja deh ngomong membela rakyat, kok nggak tahu malu ya? Kan kelakuannya sudah diketahui rakyat.”
Malam ini, mungkin besok malam pula, kata neolib boleh jadi masih beredar. Pesaing pasangan SBY-Budiono terus menghunjamkan istilah neolib ini untuk menyerang. Budiono jadi sasaran tembak oleh orang-orang yang berada di kubu JK-Win dan Mega-Prabowo. Tembakan yang berhasil, bukan karena penembak yang piawai, tetapi Budiono mau menyediakan diri bersibuk-sibuk membantah. Ia menari dalam irama gendang lawannya.
Jadi, Budiono memang lugu dan “kurang mahir” berakrobat politik. Bukan saja dituduh membawa paham neolib, tapi juga disebut “mbahnya neolib” atau seperti yang dibilang tim suksesnya Mega-Pro, “ayatulahnya neolib”. Sampai kapan Budiono terus menari?
Padahal, isu neolib sudah ditertawakan masyarakat. Bahkan slogan yang diembel-embeli “kerakyatan” juga dicibir. Orang desa yang lugu bertanya: “Para jenderal yang bertarung itu kok bisa kaya sekali, berapa gajinya sebagai tentara? Sekarang ngaku membela rakyat, apa nggak nilep uang rakyat sebelumnya?” Mungkin ini perlu jawaban.
(Dari Koran Tempo Minggu 31 Mei 2009)
Tentara Kita
Kalau tiba-tiba mendengar ada suara bergemuruh, cobalah segera menatap langit. Siapa tahu ada pesawat terbang yang oleng, lalu menabrak rumah Anda. Peringatan ini ditujukan kepada semua penduduk negeri tanpa kecuali, karena kecelakaan pesawat bisa terjadi di mana saja. Namun, warga yang diam di dekat pangkalan militer, tentu lebih waspada.
Terbakarnya pesawat Hercules di Magetan, pekan lalu, sungguh tragedi yang mengenaskan. Ini kecelakaan pesawat yang ke sekian dengan korban yang banyak. Korbannya tentara kita – lebih akrab disebut begitu dibandingkan Tentara Nasional Indonesia. Juga banyak warga sipil, keluarga tentara dan pemilik rumah yang dilabrak.
Dianalisa dari berbagai sudut, diinvestigasi dari berbagai faktor, tetap muncul sangkaan kuat penyebab jatuhnya pesawat karena usianya yang uzur, perawatannya yang minim, dan mungkin saja suku cadangnya “asli tapi palsu”. Kabut boleh dijadikan kambing hitam, tetapi banyak pesawat tentara kita yang memang sudah tua.
Apa pun hasil investigasinya, saya ikut berbela sungkawa kepada para korban. Hanya, saya menyesalkan ada wakil rakyat yang mendadak menjadi pahlawan, muncul di televisi yang meminta semua pejabat terkait mundur. Dari Kepala Staf TNI AU, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan yang tidak disebutkan, Presiden. Kata wakil rakyat itu, pejabat ini sudah tak punya rasa malu dengan berbagai kecelakaan pesawat yang menewaskan perwira-perwira terbaik tentara kita.
Kalau salah yang dicari, yang benar tidak akan didapat. Siapa yang mengkritisi anggaran pertahanan di DPR? Siapa yang dulu -- dan berulang kali dikatakan – bahwa anggaran pertahanan tak perlu mendapat prioritas? Sudah lama tentara kita tidak mendapatkan prioritas dari sisi anggaran. Di zaman global yang menghormati hak asasi manusia ini, kata sejumlah politisi, tak ada negara menyerang negara. Artinya, faktor ancaman dari luar nol koma kosong. Jadi, lebih baik membangun bendungan, pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pabrik pupuk, dibandingkan membeli senjata termasuk pesawat militer. Di masa damai dan tenang ini, begitu diucapkan, membangun puskesmas dan memperbaiki nasib petani jauh lebih penting dari memikirkan tentara.
Akhirnya, Nusantara ribuan pulau ini punya anggaran pertahanan jauh di bawah Singapura, negeri satu pulau. Tentara kita mulai “tak dianggap”, baik oleh orang luar, juga oleh orang dalam. Dulu, perayaan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober senantiasa ditunggu masyarakat karena akan ada akrobatik udara atau aksi memukau di lautan. Masyarakat bangga, anak-anak kecil pun memakai “baju tentara”. Kini, tak ada lagi. Perayaan 5 Oktober diisi perwira cakep dan cantik melakukan gerakan seragam dengan langkah tegap: satu, dua, satu, dua. Memang ada unjuk ketrampilan, tetapi itu sebatas tentara yang menebas balok es dengan tangan kosong. Kurang membanggakan. Bukan saja balok es lebih murah ketimbang pesawat tempur, ketrampilan itu jamak ada di dunia persilatan, bahkan di pesantren. Lihat di Pasar Senen Jakarta, atau di sepanjang Malioboro Yogyakarta, busana anak-anak dengan atribut militer sudah jauh berkurang dibandingkan dulu.
Saat ini, ketiga pasang calon presiden, semuanya ada unsur tentara. Ada dua mantan jenderal kesohor menjadi calon wakil presiden, ada satu mantan jenderal yang lebih kesohor lagi menjadi calon presiden.. Siapa pun yang terpilih, semestinya bisa berjuang kembali membangun tentara kita. Petani memang perlu disejahtrakan, tetapi tentara juga, karena petani dan tentara adalah juga manusia.
(Dari Koran Tempo Minggu 17 Mei 2009)
Senin, Mei 11, 2009
Rani
Saya tidak sedang menulis Rani, atau nama lengkap di kartu tanda penduduknya, Rhani Juliani. Mantan caddy golf yang menjadi wanita terpopuler saat ini karena kasus pembunuhan Nasrudin itu, tidak saya kenal. Bagaimana saya menulis orang-orang yang tidak saya kenal?
Tapi saya mengenal beberapa orang yang dipanggil akrab Rani. Dari penulis fiksi, penyanyi, aktifis pers kampus, tentu dengan nama lengkap yang berbeda. Salah satunya adalah Sutirani, gadis asal Temanggung, bekas tetangga saya sewaktu saya tinggal di Sidoarum, Godean, Yogyakarta.
Rani Temanggung ini begitu tamat SMA tidak melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, barangkali mirip Rani Tangerang di awal-awalnya. Ia ikut Bu De-nya ke Yogya, kursus memijat beberapa hari, lalu menjadi gadis pemijat di sebuah “panti pijat tradisional”. Tak sampai sebulan ia bertahan, banyak hal yang ia keluhkan pada saya. Belakangan saya dengar dia menjadi pramuria – sebutan keren pelayan – di toko Sami Jaya, kawasan Malioboro. Entah sekarang.
Kenapa saya sering ingat Rani? Ia pernah berkeluh, seorang pria setengah tua, suatu hari menjadi “pasiennya”. Setelah waktu habis, Rani mengingatkan pijatan sudah selesai. Pria itu setengah marah membentak: “Mana tradisionalnya?” Rani mulanya kaget, apa yang dimaksudkan “tradisional” itu. Syukur, pria itu hanya marah, lalu keluar.
Belakangan banyak pria yang terus menggoda: “Dik, jangan lupa tradisionalnya, ya?” Atau kalimat ini: “Kalau pakai tradisional, tambah berapa?” Lama-lama Rani tahu, apa yang dimaksudkan: berbuat mesum. Ia punya jurus menolak, dan teknik penolakan itu yang membuat saya kagum, sekaligus sering ingat dia. Ia hanya mengatakan begini: “Bapak kan sudah berumur, mungkin bapak punya anak gadis seusia saya, kalau anak gadis bapak dibegitukan, apa bapak tega?” Teknik ini mempan, tapi Rani memutuskan tak lagi bekerja di panti pijat berembel tradisional itu.
Jurus ini sering saya kutip kalau saya lagi berceloteh soal moral di berbagai kesempatan. Malah saya kembangkan. Misalnya, bagaimana menghindari perselingkuhan? Saya katakan: “Ketika Anda sedang berniat untuk berselingkuh dengan wanita idaman lain, cobalah merenung satu menit, bagaimana kalau istri Anda juga melakukan hal yang sama dengan pria idaman lainnya. Apakah Anda senang?”
Jika jurus itu tak mempan, coba lagi merenung satu menit, dan sebut nama Tuhan. Tak satu pun agama membenarkan perselingkuhan dan perzinahan. Surga ada di telapak kaki ibu, dan ibu itu adalah wanita, janganlah wanita dilecehkan. Ada kitab suci yang jelas menyebutkan: “di mana wanita dihina dan diperlakukan tak semestinya, di sana kekacauan akan muncul”.
Jika nama Tuhan sudah disebut dan Anda tetap berselingkuh, itu artinya setan lebih banyak disekeliling Anda. Ini pun termasuk “skenario “ Tuhan, mereka yang lemah akan dijadikan alat untuk memberi kesempatan bagi orang lain bekerja dengan baik. Kalau penjahat tidak ada, polisi tak ada kerjaan. Kalau koruptor tak ada, Komisi Pemberantasan Korupsi tak dibentuk. Sekarang Anda memilih, yang baik atau yang buruk?
Saya tak menyindir bahwa kasus Rani-Nasrudin-Antasari diawali dengan pelecehan seorang wanita, karena “sinetron” ini masih berlanjut. Saya juga tak mau mengulangi petuah yang sudah klise agar pemimpin berhati-hati terhadap 3 TA: tahta, harta dan wanita. Saya hanya ingin mengatakan: wahai kaum pria, hormatilah wanita.
Sesekali menulis tentang moral, bolehlah. Suasananya masih merayakan Waisak, hari penuh kedamaian. Selamat bagi yang merayakannya.
(Koran Tempo 10 Mei 2009)
Jumat, Mei 08, 2009
Yadnya Tak Harus Mahal
Upacara Pitra Yadnya atau ngaben atau pembakaran jenazah adalah pekerjaan mudah dan murah yang sering dipersulit sendiri, dan dimahal-mahalkan oleh penjual banten. Begitu seorang Pandita Mpu memberikan penataran di hadapan para pemangku. Lalu, beliau bercerita, bagaimana orang memper¬siapkan banten ngaben itu jauh-jauh hari. Pas ketika upacara, semua banten lumutan, janurnya kusut, kue dan sesajinya berjamur, semut merayap penuh di sana-sini. Baunya pun tak sedap lagi. Pandita Mpu pun melanjutkan ceramahnya: “Apa banten seperti itu kita haturkan kepada Tuhan untuk mengantar roh yang akan kita upacarai? Apa Tuhan tidak tersinggung diberikan banten yang sudah bengu (bau busuk)?”
Ini sebenarnya cerita lama, tetapi memang masih terjadi di pedesaan, apalagi kalau di pegunungan. Setiap melakukan dharmawacana ke luar Bali, saya pun sering ditanya soal ini, soal banten yang bau. Maklum, banten dikirim dari Bali, dipaketkan lewat kapal laut, jadi selain karena bau alamiah, juga kemasukan air laut. Jawaban saya adalah, saya tak tahu, apakah Tuhan tersinggung atau tidak. Saya belum pernah mendengar ungkapan Tuhan Maha Tersinggung. Tapi kalau hati kita sudah tidak enak meng¬haturkan banten yang “bengu” begitu, apalagi daging ayamnya sudah dipenuhi lalat, bisa jadi Tuhan memang ter-singgung. Bukan karena banten itu, tetapi karena kita sendiri sudah tidak sreg lagi, jadi Tuhan hanya mengikuti kondisi batin kita. Jelasnya saya katakan, “saya yang tersinggung kalau muput diberi banten bengu, karena itu kalau nanti saya sudah melinggih, jangan saya diminta muput jika bantennya bau. Saya mudah bersin.”
Umat Hindu di Bali, terutama di pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak banyak mendalami kitab-kitab agama, seringkali terjebak pada pola takut salah dalam mengha¬turkan banten. Takut tidak komplit, takut kurang ini atau kurang itu. Kalau salah, nanti Tuhan memberikan kutukan. Ida Bethara dan Bethara Kawitan juga memberikan kutukan atau setidak-tidaknya memberikan “sakit” sebagai sinyal dari adanya kesalahan itu. Istilah di pedesaan seperti “kepongor” atau “kepanesan” adalah suatu kepercayaan bahwa para leluhur kita — bahkan dalam tingkat tertinggi Hyang Widhi — menjatuhkan hukuman kepada umatnya karena melakukan tindakan yang salah atau kurang lengkap dalam melaksanakan upacara. Tuhan dan Bethara lebih sebagai penghukum, bukan sebagai Yang Maha Kasih, Yang Maha Pengampun.
Karena itu, supaya tidak salah, maka upacara ritual pun harus lengkap. Lengkap versi siapa? Lengkap menurut tradisi yang sudah turun-menurun, tanpa peduli lagi apakah tradisi itu benar atau sudah salah dari sononya. Karena itulah tidak sedikit orang yang menga¬dakan upacara ngaben sampai menjual harta warisan, agar pelaksanaan ritualnya disebut lengkap. Pokoknya demi upacara lengkap itu, pendidikan anaknya bisa dikorbankan, tanah produktif untuk kehidupan sehari-hari bisa digadaikan. Uang SPP anak dikorbankan karena harus membuat bebangkit. Padahal tanpa bebangkit pun yadnya bisa jalan.
Upacara Pitra Yadnya yang lengkap itu juga dikaitkan dengan kesenian, baik berupa bunyi-bunyian maupun pementasan tari. Ngaben tanpa bunyi angklung terasa begitu asing, kata orang.di kampung saya Tapi, kenapa tidak membunyikan gamelan angklung dari kaset lewat pengeras suara saja? Ini kan menghemat ratusan ribu.
Belum lagi tradisi gamelan gambang, yang konon satu-satunya gamelan yang bisa mengantarkan “pitara” ke sorga. Tanpa gamelan itu, tak ada jalan menuju sorga. Lalu lesung yang ditumbuk itu (ngeluntang), yang akan menyambut arwah-arwah yang akan diupacarai. Langkanya lesung penumbuk padi akan membuat kelabakan orang untuk mencari di mana ada lesung yang bisa disewa. Di sini saya selalu katakan, tradisi apapun yang ada di Bali selalu mengacu kepada tradisi agraris. Sekarang zaman global, padi tak perlu ditumbuk pakai lesung, ada mesin slip, kenapa ngaben tidak membunyikan mesin slip saja? Kan orang yang diaben belum tentu pula tahu lesung karena sudah hidup di zaman global.
Itu baru di tingkat bunyi-bunyian. Kemudian di tingkat pe¬mentasan, ada kepercayaan harus meminta tirtha dalang wayang kulit dengan lakon tertentu, yang ada kaitannya dengan sorga atau mencari air suci untuk mengantarkan roh ke surga. Lakon yang terkenal dalam kaitan ini adalah Biwa Swarga, Dewa Ruci dan berbagai variasinya yang tentu saja tak dikenal dalam ephos Mahabharata yang asli.
Pernah saya menanyakan kepada seorang dalang, kenapa ia mementaskan cerita yang aneh, yaitu Anoman ke sorga mencari tirtha. Bukan Bima sebagaimana lazimnya. Jawabannya enteng saja: “Saya tak biasa mendalang dengan lakon Mahabharata, saya spesialis Ramayana.” Pentas wayang kulit di Bali di masa lalu memang ada dua kubu: Mahabharata dan Ramayana yang dibedakan oleh gamelan pengiringnya. Nah ini kan lagi-lagi tradisi yang sudah ditinggalkan. Sekarang dalang Cenk-Blong (Wayan Nardayana), mau pentas Mahabharata atau Ramayana tetap saja pakai gamelan semar pegulingan. Tradisi tak harus dipertahankan, tetapi sastra agama harus dipertahankan.
Lalu, apa kaitannya pentas wayang kulit ini dengan upacara Pitra Yadnya? “Sebenarnya tak ada, karena tirtha dalang itu sendiri bisa diminta tanpa harus ada pementasan,” kata sang dalang. Ini benar sekali, bahkan tirtha dari Sang Dalang itu sendiri juga bukan keharusan. Kalau Pandita Mpu masih tergantung pada tirtha dalang untuk muput ngaben, wah, jangan mediksa dululah. Ini yang sering saya katakan.
Kesenian ini hanyalah embel-embel. Di Puri Gianyar kalau ada upacara pitra yadnya, biasanya dipentaskan tari gambuh, suatu hal yang tentu sulit untuk “ditiru” di daerah lain yang tidak mengenal tari klasik itu. Akhirnya kembali kepada masalah “perasaan batin” yang punya upacara, sejauh mana ia merasa sudah melak¬sanakan ritual itu secara lengkap. Kesenian itu sama saja akhirnya dengan banten, apakah kita puas dengan membuat yang sederhana kalau memang mampunya seperti itu? Atau kita memaksakan diri, padahal kita jelas tidak mampu?
Belakangan ini, dalam hal ritual di lingkungan keluarga, saya selalu mengatakan jangan menghambur-hamburkan yang tak perlu. Tetapi juga dipertimbangkan bagaimana kita bermasyarakat. Menyelenggarakan yadnya adalah juga menunjukkan cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau dana ada, kenapa harus memutar kaset yang berisi kidung dan gamelan, kenapa tidak mengundang sekehe shanti. Kenapa tidak mengundang sekehe topeng, sekehe angklung, dan sebagainya. Jangan dengan alasan sederhana, kita melakukan yadnya dengan “sepi ing demit” (sepi karena pelit).
Ada kawan saya dari Kalimantan yang heran melihat yadnya yang tergolong “megah” ketika anak saya potong gigi. “Pak Putu tidak konsisten, selalu menganjurkan yadnya yang sederhana, kok sekarang mewah, ada topeng, ada gamelan gong, ada angklung, ada gender ada banyak penari, undangannya pun banyak.,” katanya. Jawaban saya: “Ini karena Hyang Widhi suweca dengan saya. Saya diizinkan punya gamelan gong, lalu disumbang aklung oleh banjar, topeng punya sendiri, penari anak-anak ashram. Kalau saya beryadnya dengan sepi-sepi, kapan saya bisa menjamu warga desa saya sendiri?”
Lagi pula, saat saya beryadnya itu, saya masih hidup dengan “gaya Jakarta” dengan sobat-sobat yang juga datang dari Jakarta. Menjamu 200-an warga desa biayanya sama dengan makan sepuluh orang di hotel berbintang. Nanggap wayang kulit di Bali jauh lebih murah dari mendatangkan seorang MC kalau membuat acara di Jakarta. Jika ukurannya di bawa ke sini, tak ada alasan untuk berpelit-pelit dengan dalih “upacara agama terlalu mahal”. Justru kita disebut kikir atau pelit, beryadnya sederhana tetapi tiap malam mabuk-mabukan di kafe. Tentu harus tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, jangan membuat yadnya yang mewah saat gagal panen kopi, misalnya,
Begitu sebaliknya, kalau kita hidup serba kekurangan, untuk makan sehari-hari saja masih berjuang keras, untuk apakah kemewahan ritual yang hanya meneruskan tradisi lama itu? Tingkatan yadnya bisa diturunkan, kesenian tak menjadi keharusan, ritual bisa dibuat dengan murah. Jika perlu, ya, gabung saja menyelenggarakan yadnya seperti yang dilakukan oleh Semeton di Sekretariat Pasek ini. Ritual jangan sampai memberatkan.***
Kamis, Mei 07, 2009
Pemimpin
Ada kebiasaan baru yang tanpa saya tahu sejak kapan mulai. Yakni, setiap malam sebelum tidur, saya menganalisa informasi yang saya terima hari itu. Caranya sangat sederhana dengan mengajukan pertanyaan dalam hati: percaya akan kebenarannya atau tidak. Tentu ada alasannya, namun lebih banyak alasan itu berdasarkan wawasan saya yang dangkal. Maklumlah, saya bukan pengamat, juga bukan peramal.
Supaya lebih jelas, saya beri contoh. Saya tak percaya kalau Ibu Megawati akan mundur dari pencalonan presiden untuk memberi kesempatan pada kader-kader yang lebih muda. Ada kabar yang disampaikan oleh teman-teman (bukan kabar burung karena teman saya itu manusia), kalau Ibu Mega “mengalah” sehingga koalisi besar akan memunculkan calon presiden baru. Saya percaya Ibu Mega tetap akan bertarung, meski pun survey menyebutnya kalah.
Contoh lain, saya tak percaya kalau Soetrisno Bachir (SB) akan berani mengkhianati Amien Rais, seniornya. Pengkhianatan itu, misalnya, dengan menerima bujukan Prabowo untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden, padahal Mas Amien sudah jelas, gabung ke SBY. Analisa saya, ketika SB sedang merintis usahanya di Pekalongan dan saya masih jadi “gelandangan” di Jawa Tengah, saya mengenal SB orang yang santun. Apalagi Ibundanya menasehati, jangan berseberangan dengan Mas Amien. Apakah kesantunan ini kalah oleh ego kekuasaan?
Contoh lain lagi, saya tak bisa percaya kalau SBY akan mengandeng kader PKS sebagai wakilnya. SBY akan kehilangan pemilih nasionalis, pluralis, yang menjunjung kebhinekaan, karena kesan yang ditampilkan PKS adalah menegakkan syariat Islam. Analisa saya, SBY bisa terjungkal kalau salah pilih wakil.
Tentu saya minta maaf jika alasan dan analisa saya memang dangkal. Terbukti sering salah. Misalnya, suatu malam saya pernah tidak percaya kalau Wiranto mau menjadi calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla. Jendral kok jadi wakil seorang pengusaha. Nah, ternyata sang jendral dengan tegas telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden. Meski saya salah, saya sungguh bersyukur dan merasa “bersemangat” untuk ikut Pemilihan Presiden (ketika Pemilu Legislatif saya “kurang semangat”). Kenapa? Karena tiba-tiba saya ingat, pada 1994, ketika Wiranto menjabat Kastaf Kodam Jaya, beliau memanggil saya pukul enam pagi untuk mendiskusikan “bagaimana mempertahankan NKRI”. Saat itu saya “terlanjur” menjabat Ketua Umum Forum Cendekiawan Hindu dan kebetulan situasi politik ketika itu lagi hangat dengan “sekat-sekat primordial”.
Sebagai orang yang suka keluyuran di Nusantara (kalau keluar negeri tak punya ongkos dan takut kena flu babi), keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi dambaan saya. Dalam bahasa politisi “ini harga mati”, dalam bahasa almarhum Gombloh “merah darahku, putih hatiku”. Artinya, koalisi apapun yang dilahirkan partai politik, koalisi besar atau kecil, bangsa yang bhineka tunggal ika harus tetap utuh, atau mengutip lagu Coklat: “merah putih teruslah berkibar… “
Saya percaya tentang keutuhan Indonesia yang bhineka itu. Namun, tetap tergantung figur yang memimpin negeri ini. Masalahnya tidak banyak stock pemimpin yang, kalau dadanya dibelah, ada merah putih di sana. Apalagi ditambah bermoral dalam arti luas. Contoh kabar terakhir, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka pembunuhan, hanya karena cewek. Saya sudah membulatkan hati untuk tidak mempercayai kabar ini, supaya ada pemimpin yang masih saya hormati. Tapi kan saya sering salah. Sangat memprihatinkan.
Koraan Tempo 3 Mei 2009)
Selasa, April 28, 2009
Jusuf Kalla
Keputusan Jusuf Kalla (JK) pisah dengan Soesilo Bambang Yudhoyono membuat girang Romo Sugeng – begitulah lelaki ini saya panggil dengan akrab. Romo yang usianya sudah kepala tujuh tetapi masih berani makan tongseng kambing ini, bukan partisan partai. Ia petani, tapi lahan pertaniannya disewakan untuk perkebunan teh. Ia kerap saya temui di warung tongseng Bang Jarot yang terkenal di Desa Kemuning itu, desa terdekat sebelum menanjak menuju Candi Ceto di Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
“Seandainya JK masih berkoalisi dengan SBY, pertandingan tidak seru, karena yang menang sudah jelas. Ibarat Barcelona melawan Perseketos (persatuan sepakbola Kemoning – Ceto dan sekitarnya). Kan sempat muncul istilah boikot pemilihan presiden, tak mengajukan calon, bahkan ada usul supaya dikaji dasar hukum untuk jaga-jaga kalau ternyata calon presidennya tunggal, seperti di zaman Harto,” ujar penggemar bola dan penggila Lionel Messi ini
“Jadi, Romo akan memilih JK ketimbang SBY?” tanya saya asal-asalan.
“Lo, belum ke sana. Sampeyan nggak ngerti politik, sih. Posisi JK itu sekarang, baru pada mencairkan kembali semangat untuk bertanding yang tadinya sempat loyo. Dengan cerainya JK pada SBY, partai lain menaruh harapan untuk disambangi JK. Sebaliknya, JK pun bersemangat untuk mendatangi. Kalau JK berhasil membangun kekuatan, kan yang memilih jadi bersemangat karena hasilnya tidak pasti. Seni dalam memilih itu adalah jika kita tak bisa memastikan hasil akhirnya. Ketidak-pastian ini, seperti dialami para petaruh, memunculkan kegairahan.”
“Apa JK punya kekuatan, Romo?” tanya saya, masih asal-asalan.
“Dia kan pengusaha, jadi awalnya non-birokrat, lalu non-militer, kemudian non-Jawa. Non-non ini akan membuat pemilih untuk main coba-coba…”
“Romo, ini saya tak setuju, memilih pemimpin kok coba-coba, taruhannya bangsa Romo,” kata saya memotong.
“Lagi-lagi sampeyan tak tahu politik para pemilih,” kata Romo agak keras. “Sampeyan kemarin bilang, di Bali ada pelawak yang hanya cengangas-cengenges di panggung bisa meraih kursi di Senayan, mengalahkan para politikus karatan. Itu artinya, pemilih bosan dikibuli para politikus selama ini. Nah, apa bedanya dengan bangsa? Puluhan tahun dipimpin militer, berpuluh tahun dipimpin orang Jawa, berbilang tahun dipimpin birokrat tulen, hasilnya begini-begini saja. Coba pilih yang lain, jangan-jangan lebih bagus. Pergilah sampeyan ke Sulawesi, Kalimantan, Papua, Flores, pemikiran seperti ini berkembang.”
Saya diam, bukannya setuju, tetapi rikuh mendebat. Romo melanjutkan: “Kekuatan JK lainnya, ia dipojokkan dengan basa-basi khas Jawa, lalu mencuat harga dirinya. Ia sebenarnya ditolak mendampingi SBY kembali, tetapi pihak SBY berdalih: mbok sodorkan nama lebih dari satu. Ia tak diharap menghadiri rapat kabinet, tetapi dalihnya: kalau sibuk nggak usah ikut rapat. Kenapa tak berjelas-jelas saja? Dalam kasus ini, ada istilah ‘politik Inul’ yang pernah pula dinikmati SBY pada pemerintahan Mega. Pada saat seseorang dilecehkan --seperti Inul dilecehkan Rhoma Irama-- pada saat itulah simpati berhamburan datang.”
Saya merasa lebih baik diam, sehingga Romo nyerocos lagi: “Kelemahan JK, jika ia tak berhasil memimpin koalisi, lalu tetap hanya jadi orang nomor dua, maka tamatlah dia. Siapa pun orang pertamanya, kemungkinan koalisi itu menang melawan SBY sangat tipis.”
Saya ternganga, lalu permisi. Di lereng Gunung Lawu yang beraroma magis ini, sulit membedakan antara pengamat, peramal, paranormal, atau orang lagi stress.
(Diambil dari Koran Tempo 26 April 2009)
Selasa, April 21, 2009
Terburuk
Politisi yang kalah pada Pemilu 9 April, plus para tokoh yang nafsu besar berkuasa tapi tidak punya partai, berkumpul di rumah Ibu Megawati. Salah satu kesepakatannya, Pemilu 9 April lalu adalah Pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Kesimpulan itu diiyakan juga oleh mantan wakil Presiden Hamzah Haz.
Saya sepakat soal ini. Tak ada yang perlu dibantah.
Pemilu yang lalu membuat capek banyak orang. Calon legislator capek bukan main, bahkan ada yang nekad ingin istirahat selamanya, misalnya, gantung diri. Petugas Pemilu, dari panitia pemungutan suara sampai anggota komisi pemilihan umum, pasti capek juga. Pimpinan partai lebih capek lagi, mondar-mandir menawarkan koalisi.
Saya, yang mujur tidak menjadi calon legislator, juga capek. Mata capek melihat tabulasi suara di televisi yang tak beranjak naik. Kuping capek mendengar politisi yang saling tuduh lewat radio. Jadi, saya sepakat soal capek itu.
Pemilu direkayasa untuk kemenangan partai tertentu. Daftar pemilih tetap yang amburadul disengaja untuk menggelembungkan Partai Demokrat. Karena itu Pemilu harus digugat, tidak sah, dan perlu diulang. Ini pendapat sejumlah tokoh, bahkan tokoh yang pernah saya kagumi karena sempat menyebut diri calon presiden alternatif.
Saya, dengan mengurangi rasa hormat, tidak sepakat. Saya langsung mencoret sejumlah tokoh idola dalam memori otak saya.
Menjelang Pemilu, saya banyak di Bali dan di eks Karesidenan Surakarta, kadang di Solo kadang di Karanganyar. Orang-orang yang tak terdaftar di daftar pemilih tetap atau yang tak menerima surat panggilan mencontreng, kesal benar dengan “pemerintah”. “Pemerintah” disebut memihak partai besar, yaitu Partai Banteng Gemuk dan Partai Beringin. Lo, kenapa partai itu jadi tersangka? Maklum, yang jadi Bupati adalah kader PDI P dan Golkar. Bahkan di Bali, gubernurnya ikut kampanye PDI P. Bukankah dari “pemerintah” itu sumber daftar pemilih tetap yang amburadul? Maka, kader partai biru meradang, sedang kader partai merah dan partai kuning, tenang-tenang saja.
Eh, setelah Pemilu, terjadi keajaiban. Yang memprotes daftar pemilih tetap justru sebaliknya. Artinya, protes dan tidak memprotes, hujat dan tidak menghujat, tergantung siapa yang kalah dan siapa yang menang. Partai menang sudah nasibnya jadi tersangka dan partai kalah tak perlu malu untuk jadi penuntut.
Pemilu yang buruk, memang disepakati. Tetapi, buruk rupa Pemilu jangan cermin bangsa dibelah. Sistemlah yang membuat Pemilu jadi rumit, bertele-tele, dan amat mahal. Sistem lahir karena tuntutan undang-undang. Contoh kecil, pemilih harus terdaftar. Padahal kalau mau gampang, pemilih tinggal menyodorkan kartu tanda penduduk. Bukankah dengan KTP ber-NIK (nomor induk kependudukan) yang oleh orang desa disebut “KTP Nasional” tidak memungkinkan (teorinya) ada seorang memiliki dua KTP? Kalau pun ada – maklum masih ada desa yang tak punya komputer online dan banyak orang kota yang nakal – bukankah ada “tinta Pemilu” yang mencegah orang memilih dua kali? Tinggal pengawasan.
Yang gampang itu dipersulit oleh undang-undang. Ini hanya satu contoh, banyak contoh lain. Lalu siapa yang membuat undang-undang itu? Ya, wakil rakyat yang ditentukan oleh partai. Jadi, kalau Pemilu ini buruk, yang sesungguhnya buruk itu adalah orang-orang partai di Senayan.
Mari perbaiki dari pangkalnya, jangan menuduh, apalagi memprovokasi dengan wacana Pemilu tak sah atau perlu diulang. Rakyat, yang makin pintar, siap menghukum tokoh provokator. Saya, sebagian dari rakyat itu, meski pun tak cukup pintar.
Selasa, April 07, 2009
Jiwa yang Guncang Pasca Pemilu
Departemen Kesehatan sibuk mengurusi Pemilu. Bukan menyiapkan petugas yang menangani korban kampanye terbuka, tetapi mempersiapkan perawatan bagi mereka yang kena gangguan jiwa. Semua rumah sakit jiwa di Nusantara berstatus siaga satu begitu pencontrengan selesai.
Korban Pemilu bukan lagi rakyat, tetapi para calon legislator. Jenis penyakitnya bukan luka, tetapi jiwanya terguncang. Makanya Departemen Kesehatan tak menyiapkan Puskesmas atau rumah sakit umum, melainkan rumah sakit jiwa. Dalam bahasa rakyat, korban yang masuk ke rumah sakit ini adalah mereka yang tidak waras.
Karena korbannya orang berpendidikan – sebagian besar calon legislator memamerkan gelar akademiknya meski pun ngomongnya belepotan – kamar-kamar yang disiapkan di rumah sakit jiwa tergolong baik. Bahkan di Semarang disiapkan kelas VIP. Di daerah lain, seperti Magelang, Mataram atau Bangli (Bali) cukup kamar biasa.
Awalnya saya kira langkah ini mengada-ada. Setelah mendengarkan uraian pakar ilmu kesehatan jiwa seperti Dr. Luh Suryani di Bali, saya baru percaya bahwa ini soal serius. Luh Suryani dan lembaga swadaya yang dipimpinnya bahkan sudah menyiapkan diri sebelum Departemen Kesehatan sibuk.
Inilah Pemilu yang menghasilkan “orang gila”. Yang tidak terpilih masuk rumah sakit jiwa atau jadi beban sosial di masyarakat karena ulahnya pasti menyebalkan, yang terpilih kelihatan seperti waras tetapi jiwanya terganggu. Karena yang dipikirkannya adalah bagaimana bisa duduk aman sebagai wakil rakyat selama lima tahun sembari mendapatkan proyek-proyek berduit di luar gaji resmi. Jiwanya mudah labil begitu ada yang mempersoalkan kinerjanya.
Jika kita rajin mengamati para calon legislator, entah itu melihat bagaimana mereka tampil di baliho, tampil di iklan televisi lokal mapun radio, dan lebih-lebih lagi melihat ulahnya di saat kampanye, sebenarnya sudah banyak yang “terganggu jiwanya”. Mereka tak bisa membedakan antara harapan yang bisa diperjuangkan, dan khayalan yang hanya mimpi. Umumnya mereka membeo, begitu kata “perubahan” laku, semuanya bicara perubahan. Ini mencerminkan bahwa mereka sebenarnya tak menguasai apa-apa, hanya mengumbar slogan yang mereka sendiri tak memahami arti sebenarnya. Ada yang bergaya bak pahlawan yang ditunggu-tunggu, tapi dia lupa jejak langkahnya sudah terekam buruk di masyarakat. Orang tak bisa berubah drastis dalam sekejap – atau karena ada Pemilu. Hanya penari topeng yang bisa berubah total wataknya begitu topengnya diganti.
Gangguan jiwa ini bisa jadi karena sistem dan aturan Pemilu yang berubah. Orang bebas mendirikan partai – atas nama konstitusi yang tak boleh membatasi hak orang membentuk perserikatan. Dalam kebebasan, orang-orang yang jiwanya terganggu itu, tentu tak mengenal malu. Sudah nyata partainya tak mendapat dukungan, tetap dipaksakan ikut Pemilu. Dan calon legislator yang dimunculkan pun juga labil jiwanya.
Adapun partai besar, tidak memiliki cara rekrutmen kader yang benar dan sering pimpinan partai itu bersikap “membela yang bayar” selain “membela keluarga”. Nomor urut tidak didasarkan pada kemampuan kader, tetapi pada yang “bayar” dan “keluarga”. Ketika mendadak sistem berubah dan nomor urut tidak menentukan kemenangan seorang calon, para pemegang nomor besar mendapat angin untuk menantang. “Rasakan sekarang, siapa yang didukung rakyat,” mungkin begitu sumpahnya. Calon yang bernomor urut kecil, yang jiwanya sudah goncang karena harus bayar dan melakukan “penjilatan”, tiba-tiba harus berjuang keras pula. Semuanya kemudian mencari akal bagaimana cara agar bisa mendapatkan suara melebihi yang lain, termasuk cara yang tak masuk akal (bagi orang normal) seperti menjual harta warisan. Bagaimana tidak edan kalau hasilnya gagal?
Sistem dan aturan Pemilu perlu direformasi agar mendapatkan wakil rakyat yang jiwanya tidak terganggu. Peserta Pemilu mesti dikurangi, hanya partai yang mendapatkan dukungan signifikan. Caranya mudah kalau berani, yakni bubarkan partai yang tak mendapatkan suara minimal 10 persen. Ini contoh jika kita menghendaki maksimal ada 10 partai, syukur kurang dari itu. Partai sedikit namun sehat, persaingan nomor urut calon ditentukan berdasarkan “uji kelayakan” dan betul-betul yang paling pantas menjadi wakil rakyat. Pemenang kembalikan ke nomor urut, biarkan rakyat hanya mencoblos atau mencontreng lambang partai, tak perlu repot memelototi nama calon.
Ini artinya, kita kembali ke masa lalu. Tetapi yang “kembali” hanya sistem, pelaksanaan Pemilu tentu lebih demokratis, cerdas, berkualitas, termasuk slogan lama: jujur dan adil. Masalahnya, pasti banyak elit politik yang tak setuju. Persyaratan 2,5 persen suara untuk sebuah partai “bisa selamat” saja, sudah mau digugat. Mereka berdalih: “Kita bertekad melakukan perubahan…”
Nah, makan itu perubahan.***
(Pernah dimuat di Koran Tempo, awal April 2009)
Kasta di Bali: Kesalahpahaman yang Sudah Sirna
Ketika Mayor Jenderal Polisi I Made Mangku Pastika mencalonkan diri sebagai Gubernur Bali, ada elite politik di Jakarta yang tak yakin dengan kemenangannya. Alasannya ternyata sangat aneh. Dia mengatakan, pemimpin di Bali harus dari orang yang berkasta tinggi. Kalau kastanya rendah tak akan bisa terpilih sebagai Gubernur Bali. Lantas dia menyebut nama gubernur-gubernur Bali sebelumnya, seperti Dewa Beratha, Ida Bagus Oka, Ida Bagus Mantra.
Pernyataan ini membuktikan bahwa masalah kasta di Bali masih membingungkan banyak orang dan masalah kasta masih dikait-kaitkan dengan berbagai macam pekerjaan.
Di Bali sendiri masalah kasta sudah tidak relevan lagi dibicarakan, dan boleh disebutkan sudah tidak lagi menjadi “kesalah-pahaman”. Mungkin hanya masih berlaku di pedesaan dan itu pun pada kalangan tua. Generasi muda Bali sudah lama meninggalkan kasta. Dengan demikian menjadi aneh terdengar justru di luar Bali orang masih membicarakan kasta dengan segala embel-embelnya seperti di masa lalu.
Kasta sebenarnya ada di mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Atau kelas-kelas sosial di masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan “berkasta tinggi”. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain dari kasta, seperti “berdarah biru”, “kaum bangsawan” dan sebagainya yang menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. Bagi mereka yang berada “di atas” entah dengan sebutan “darah biru” atau “bangsawan” umumnya mempunyai komplek pemukiman yang disebut keraton atau puri. Di masa sekarang ini, kraton atau puri tentu tak punya kuasa apa-apa, namun penghuninya berusaha untuk tetap melestarikannya. Ada pun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja.
Di India kasta itu jumlahnya banyak sekali. Hampir setiap komunitas dengan kehidupan yang sama menyebut dirinya dengan kasta tertentu. Para pembuat gerabah pun membuat kasta tersendiri.
Di Bali juga unik. Ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda datang mempraktekkan politik pemecah belah, kasta dibuat dengan nama yang diambilkan dari ajaran Hindu, Catur Warna. Lama-lama orang Bali pun bingung, yang mana kasta dan yang mana ajaran Catur Warna. Kesalah-pahaman itu terus berkembang karena memang sengaja dibuat rancu oleh mereka yang terlanjur “berkasta tinggi”.
Ajaran Catur Warna dalam Hindu adalah menempatkan fungsi sosial seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Orang boleh memilih fungsi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Catur Warna itu terdiri dari Brahmana, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai rohaniawan. Kesatria, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menjalankan kerajaan: raja, patih, dan staf-stafnya. Jika dipakai ukuran masa kini, mereka itu adalah kepala pemerintahan, para pegawai negeri, polisi, tentara dan sebagainya. Wesya, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menggerakkan perekonomian. Dalam hal ini adalah pengusaha, pedagang dan sebagainya. Kemudian Sudra, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai pelayan, bekerja dengan mengandalkan tenaga.
Fungsi sosial ini bisa berubah-ubah. Pada awalnya semua akan lahir sebagai Sudra. Setelah memperoleh ilmu yang sesuai dengan minatnya, dia bisa meningkatkan diri sebagai pedagang, bekerja di pemerintahan, atau menjadi rohaniawan. Fungsi sosial ini tidak bisa diwariskan dan hanya melekat pada diri orang itu saja. Kalau orangtuanya Brahmana, anaknya bisa Sudra atau Kesatria atai Wesya. Begitu pula kalau orangtuanya Sudra, anaknya bisa saja Brahmana. Itulah ajaran Catur Warna dalam Hindu.
Yang jadi persoalan, ketika kasta diperkenalkan di Bali di masa penjajahan itu, nama-nama yang dipakai adalah nama Catur Warna: Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Jadi, pada saat itu semua fungsi Catur Warna diambil alih oleh kasta, termasuk gelarnya. Celakanya kemudian, gelar-gelar itu diwariskan turun temurun, diberikan kepada anak-anaknya tak peduli apakah anak itu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan ajaran Catur Warna atau tidak. Contohnya, kalau orang tuanya bergelar Cokorde, jabatan raja untuk di daerah tertentu, anaknya kemudian otomatis diberi gelar Cokorde pada saat lahir. Kalau orangtuanya Anak Agung, juga jabatan raja untuk daerah tertentu, anaknya yang baru lahir pun disebut Anak Agung. Demikianlah bertahun-tahun, bahkan berganti abad, sehingga antara kasta dan ajaran Catur Warna ini menjadi kacau.
Kekacauan ini lama-lama menjadi kesalah-pahaman.. Misalnya, ada anggapan bahwa yang berhak menjadi rohaniawan (pendeta Hindu) hanyalah mereka yang keturunan Brahmana versi kasta, yang nama depannya biasanya Ida Bagus. Mereka yang tak punya nama depan Ida Bagus disebut bukan keturunan Brahmana, jadi tak bisa menjadi pendeta. Begitu pula kasta lainnya, yang berhak menjadi pemimpin hanya keturunan Kesatria. Orang seperti I Made Mangku Pastika yang tak punya “nama gelar” tak akan bisa menjadi pemimpin karena kastanya hanya Sudra.
Demikianlah kesalah-pahaman itu, akhirnya dikoreksi terus menerus setelah majelis agama Hindu (Parisada Hindu Dharma Indonesia) berdiri pada 1959. Jauh sebelumnya, yakni pada 1951, DPRD Bali sudah menghapus larangan perkawinan “antar-kasta” yang merugikan “Kasta” bawah seperti Sudra. Kesulitan yang dihadapi dalam menghapus Kasta di Bali itu tentu karena masalah ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan berganti abad. Namun yang menyebabkan kesalah-pahaman itu bisa dijernihkan adalah adanya toleransi dan merupakan kesepakatan yang tak perlu ditulis, yakni masyarakat akhirnya memperlakukan nama-nama depan yang dulu merupakan gelar pemberian penjajah tetap bisa dipakai sebagai nama keturunan. Tetapi tidak ada kaitan dengan fungsi sosial, juga tak ada kaitan dengan ajaran Catur Warna. Artinya, siapa pun berhak menjadi Brahmana (rohaniawan atau pendeta), tidak harus dari keluarga Ida Bagus. Siapa pun berhak menjadi pemimpin (misalnya Bupati atau Gubernur), tak harus dari yang bergelar Kesatria versi kasta masa lalu.
Era modernisasi ikut mengubur perjalanan kasta di Bali. Banyak orang yang tidak memakai nama depan yang “berbau kasta”, dan nama itu hanya dipakai untuk kaitan upacara di lingkungan keluarga saja. Apalagi nama-nama orang Bali modern sudah kebarat-baratan atau ke india-indiaan. Juga faktor pekerjaan di mana orang yang dulu disebut berkasta Sudra, misalnya, kini memegang posisi penting, sementara yang berkasta di atasnya menjadi staf. Dengan demikian hormat-menghormati sudah tidak lagi berkaitan dengan “kasta” yang feodal itu.
I Made Mangku Pastika pun bisa menjadi Gubernur Bali, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Sudra. Wakil Gubernur adalah Anak Agung Puspayoga, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Kesatria. Staf di kantor gubernuran banyak yang bernama depan Ida Bagus, yang jika dikaitkan dengan kasta masa lalu adalah Brahmana. Terbuktilah kini, bahwa kasta masa lalu itu sudah terkubur. Yang tetap berlaku adalah ajaran Catur Warna, orang diberi kebebasan untuk menjadi Brahmana, Kesatria, Wesyaa maupun Sudra, asalkan mampu.
(Artikel ini pernah dimuat di Majalah Budaya Tapian, edisi Februari 2009)
Kembali ke Sawah
Setiap bencana membawa hikmah. Datangnya malapetaka menyisakan perenungan. Persoalannya adalah apakah kita akan mau mengambil hikmah dan mau merenungi kembali perjalanan kita di masa lalu untuk dijadikan sesuluh di masa depan?
Bali diguncang bom tahun 2002. Kita diberi hikmah bahwa industri pariwisata sangat rentan dengan keamanan. Perekonomian Bali yang bersandar pada dunia pariwisata hancur. Kita sempat merenung sejenak, apakah pariwisata model Bali ini sudah benar bertumpu pada pariwisata budaya? Namun perenungan itu tidak tuntas. Corak pariwisata jauh melenceng dari akar budaya Bali. Kontribusi pelaku budaya tak dihargai oleh hasil pariwisata. Toh, pelaku pariwisata tetap berusaha memulihkan bisnis itu, dan ketika menggeliat, bom kedua meledak.
Ada pepatah yang berbunyi: “Pelanduk yang paling tolol tak akan terantuk dua kali pada batu yang sama”. Orang Bali tentu bukan pelanduk yang tolol. Karena itu, setelah dua kali bom mengguncang, sebaiknya kita merenungi, apa yang sebenarnya terjadi pada Bali?
Orang Bali setuju daerahnya menjadi tujuan wisata Indonesia dengan catatan landasannya budaya. Maka lahirlah istilah pariwisata budaya. Artinya, yang dijual kepada wisatawan yang pertama dan utama adalah budaya. Tapi apa yang terjadi? “Halaman rumah” orang Bali, tempat budaya itu lahir, digerogoti terus. Tanah sawah dijadikan hotel atau ruko, jurang-jurang dipenuhi bungalows, air untuk pengairan dialirkan ke hotel-hotel, tempat suci direkayasa sehingga tidak lagi ada vibrasi kesucian sebagaimana dahulu. Orang Bali yang semula agraris dipaksa menjalani kehidupan industri, dan pola konsumtif pun diperkenalkan dengan gencar. Hotel, restoran, travel sebagian besar punya orang luar Bali, bahkan pengelola Bandara Ngurah Rai pun tak menyisihkan penghasilannya untuk Bali.
Bersamaan dengan itu Bali pun diserang dari “tingkah menengah bawah”. Pendatang yang membawa budayanya sendiri tak bisa dibendung, dan anehnya dibiarkan oleh pemimpin-pemimpin Bali. Maka lahirlah budaya berjualan koran di lampu lalu lintas, ngamen di rumah makan dan terminal, kaki lima di trotoar dan di sepanjang jalan, pemulung ke desa-desa, kafe juga ke desa-desa lengkap dengan wanita tuna susilanya. Rumah-rumah kumuh berdiri yang bertolak belakang dari konsep Tri Hita Karana, belum lagi tempat ibadah dengan segala perlengkapannya. Pola konsumtif orang Bali pun dimanfaatkan dengan baik oleh pendatang, semua kebutuhan ritual orang Bali disuplay dari Jawa Timur, dari janur, bunga, buah sampai telur bebek.
Kalau kita mencoba merenung dengan jujur, semua ini menghancurkan budaya orang Bali. Bagaimana mempertahankan subak kalau airnya sudah dibawa ke hotel, sawah dikapling, lalu yang memanen padi orang Jawa atau Lombok yang mendirikan kemah-kemah di jalanan? Berapa ritual yang hilang, dari mendak toya di pura bedugul sampai ngadegang Dewi Sri…. Bagaimana generasi muda Bali tertarik ke balai banjar untuk belajar menabuh dan mekidung, kalau kafe berdinding bambu dengan wanita menor ada di sudut-sudut desa? Bagaimana orang mau merawat pohon juwet, sotong, duku, dan lainnya, kalau orang Bali diarahkan membeli apel Amerika dan peer dari Cina untuk yadnya ke pura? Apalagi membuat dodol dan apem, lebih praktis dodol Garut dan dodol Kudus, sementara apem diganti roti kukus. Laklak Bali sudah sulit dicari di Denpasar, ada penggantinya, kue serabi dan dawet dari Banyumas.
Kalau Bali ingin ajeg dengan budayanya yang tinggi seperti masa lalu, sarana untuk melahirkan budaya itu jangan dihancurkan. Air Bali harus tetap untuk kepentingan subak agar pertanian tetap jalan, karena dari sawah itu berbagai budaya lahir. Kalau hotel-hotel besar membutuhkan air, cari alternatif lain, entah menyuling air limbah atau menyuling air laut. Jadi modal dasar budaya itu jangan digerogoti kalau betul pariwisata Bali diarahkan ke budaya. Apa modal dasar itu? Tak lain adalah tanah dan itu artinya tanah pertanian karena budaya Bali adalah budaya agraris.
Pemerintah harus memproteksi tanah pertanian Bali. Tanah Bali tak boleh jatuh ke tangan orang non-Bali. Pemerintah harus mensubsidi pertanian, baik dalam hal pengembangan produk maupun pemasarannya. Pemerintah harus mendorong agar orang Bali bisa mandiri. Jangan biarkan orang Bali tergantung pada orang luar, apalagi untuk kebutuhan menjalankan tirualnya, karena dari situlah sumber adanya budaya Bali yang adiluhung. Tokoh agama harus ikut turun tangan, bagaimana menyadarkan orang Bali bahwa persembahan untuk Tuhan yang paling utama adalah persembahan dari hasil jerih payah yang dihasilkan tanah Bali.
Mari kita ubah pola kehidupan di Bali, kita kembali ke sawah, ke sektor pertanian. Tentu saja menjadi petani moderen yang mempertimbangkan produk unggulan. Intelektual Unud harus menjadi pelopornya, seperti yang dilakukan seorang dosen pertanian Unud yang kini mengembangkan rebung bambu tabah (tiying tabah) di kampung saya. Kembali ke dunia agraris akan melanggengkan budaya Bali. Kalau tetap budaya menjadi tema pariwisata Bali, hasil pariwisata harus dikembalikan kepada petani Bali, pelaku budaya itu sendiri. Jangan serakah semuanya diboyong ke luar Bali.
Kamis, April 02, 2009
Anekdot Selingan Pemilu
Seseorang bertanya: "Bagaimana melayani Tuhan dengan baik?"
Dan ini jawabannya: "Sebelum engkau tahu bagaimana melayani sesama manusia dan makhluk di sekitarmu dengan baik, bagaimana mungkin dapat melayani Tuhah yang Maha Kuasa?"
Untuk dilayani maka engkau harus melayani orang lain dulu, untuk dihormati maka engkau harus menghormati orang lain dulu, untuk didukung maka engkau harus mendukung orang lain dulu, untuk menjadi wakil rakyat maka engkau harus menjadi rakyat yang patuh dulu. Untuk menjadi manusia, maka kau harus memanusiakan (me-wongke - bahasa Jawa) yang lain-lain dulu.
Nyepi
Tak disangka, saya mendapat ucapan “Selamat Hari Raya Nyepi” dari teman Facebook yang berada di Kota Manado. Akhir ucapannya begini: "Saya akan mengikuti nyepi malam Minggu ini, semoga bermanfaat untuk mengurangi pemanasan global."
Nyepi di malam Minggu? Oh ya, saya ingat imbauan yang ditayangkan di televisi, masyarakat yang peduli terhadap pemanasan global diharapkan mematikan lampu pada Sabtu, 28 Maret, pukul 20.30 selama satu jam. Pasti hal ini yang disebut "nyepi" oleh teman saya. Saya pun berjanji akan mengikuti hal itu.
Apakah Anda ikut memadamkan lampu selama satu jam semalam? Atau lebih dari satu jam? Atau lupa karena masih asyik menyaksikan acara "pertengkaran" di televisi: tentang daftar pemilih tetap yang amburadul, tentang calon legislator yang berulah aneh, tentang artis yang bertekad bulat menjadi politikus? Saya tentu akan salut kepada mereka yang ikut memadamkan lampu, toh televisi bisa dihidupkan, karena "televisi bukan lampu". Lagi pula padamnya lampu tak lama, persis seperti judul lagu pop, "satu jam saja".
Tapi, sahabatku, memadamkan lampu sekejap itu tentu bukan "nyepi" sebagaimana Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang taat. Nyepi bagi umat Hindu bukan hanya tidak menyalakan lampu, tapi juga tidak menonton televisi, tidak mendengarkan radio, tidak mendengarkan musik, tidak bepergian, tidak bekerja. Sekali lagi, ini bagi yang taat, karena lumrah ada saja umat yang tidak taat.
Nyepi itu ritual agama yang tidak terkait dengan pemanasan global dan penghematan energi. Bahwa belakangan banyak orang mengait-ngaitkan ritual itu dengan kebersihan udara, penghematan energi, langit yang semakin biru, dan sebagainya, anggap itu sebagai efek samping yang positif.
Lalu, untuk apa Nyepi? Ini adalah awal tahun Saka untuk suatu perenungan total, apa yang telah kita kerjakan selama setahun, apa yang salah, apa yang kurang, agar di tahun yang datang semuanya bisa diperbaiki. Nyepi adalah berhenti sejenak, stop melangkah. Diperlukan keheningan selama 24 jam untuk melakukan koreksi total. Langit pun gelap tanpa bulan.
Perenungan total dan introspeksi diri, saya kira, ada dalam berbagai agama, tentu dengan variasinya sendiri. Semua orang, apakah dia politikus atau pedagang atau makelar--profesi yang kini campur-baur--ataukah dia guru yang sekaligus tukang ojek, perlu "berhenti melangkah sejenak", lihat ke belakang apa yang salah, agar tidak terantuk pada batu yang sama.
Jika semua tokoh bangsa merenung dan melakukan introspeksi, dan kemudian bertekad bulat mengabdi kepada masyarakat, kenapa harus bertengkar? Kalau tujuannya sama, menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, perbedaan yang terjadi mestinya pada "dengan cara apa berbuat". Artinya, perbedaan itu bisa dimusyawarahkan. Cuma memang, untuk musyawarah, perlu silaturahmi, perlu bincang-bincang.
Sekarang situasi di Tanah Air sangat riuh, jauh dari nyepi yang intinya sepi. Padahal semua tokoh mengucapkan kata yang sama, yakni, "perubahan". Ada yang bilang: "Sambut perubahan tahun 2009, dukung kami." Yang lain berkata: "Kita perlu perubahan, bergabunglah.” Yang lainnya lagi berseru: "Kita sudah lakukan perubahan, lanjutkan." Bahkan ada yang membangun "rumah perubahan". Kata yang sama, tapi diucapkan dengan nada perlawanan terhadap pihak lain.
Coba renungkan satu jam saja--tanpa atau dengan mematikan lampu-- apakah perubahan itu selalu bagus? Yang dibutuhkan adalah "perbaikan", bukan "perubahan". Saya imbau para politikus menyepikan diri sejenak, agar tak makin menyebalkan.***
29 Maret 2009
Memenangkan Dharma
Tidak sembarang kemenangan, tentu saja. Yang dirayakan adalah kemenangan dharma. Dharma kalau disederhanakan artinya kebenaran. Jadi, menangnya kebenaran itulah yang dirayakan oleh umat Hindu. Sepintas seperti aneh, bukankah kebenaran itu semestinya selalu menang? Kalau kita hidup di zaman Satya Yuga atau Treta Yuga, barangkali betul. Tetapi ini era Kali Yuga, zaman penuh kegelapan, yang menang itu belum tentu yang benar. Para “penentu kebenaran” sudah direcoki oleh virus-virus angkara murka, kelobaan, kedengkian, iri hati, dan sifat buruk lainnya yang bertentangan dengan dharma. Itulah sifat-sifat adharma. Wasit bisa memihak, hakim dan jaksa bisa disuap. Bahkan pada diri kita sendiri bersemayam sifat-sifat adharma. Ketika anak kita belum mendapat pelayanan yang baik di rumah sakit, kita menempeleng perawat. Ketika seorang calon legislatif merasa disaingi calon lain, ia menyuruh orang untuk membakar baliho lawan, jika perlu membawa pedang terhunus, main tebas. Adharma bercokol dalam diri kita sendiri, besar dan kecilnya bervariasi.
Nah, sifat adharma itulah yang harus kita kalahkan. Kita awali dengan niat yang suci, melakukan pembersihan diri, baik dengan tapa, japa, brata yang dalam bahasa sekarang bisa kita sebut “tekad untuk berbuat suci”. Umat Hindu di Bali menyediakan hari yang disebut Sugian Bali dan Sugian Jawa, itulah hakekat pensucian diri.
Ketika segala yang kotor itu bisa kita bersihkan, mari kita belenggu keingingan jahat (adharma) kita. Leluhur kita di Bali mengenal Hari Penyekeban dilanjutkan Hari Penyajaan (di beberapa tempat disebut Pengejukan), itulah saatnya kita membelenggu nafsu jahat kita. Pada akhirnya segala yang jahat dan kotor kita musnahkan, kita “sembelih” sifat-sifat hewani buruk yang ada pada diri kita. Itu disebut Hari Penampahan. Jika semua tahap itu bisa kita lakoni dengan baik, pada Rabu Keliwon Wuku Dungulan semuanya itu kita syukuri sebagai kemenangan dharma. Inilah Galungan yang sejatinya.
Kita selalu memaknai Galungan tanpa pernah mencari apa arti di balik simbol-simbol yang diciptakan oleh leluhur kita ini. Kita sudah letih “jalan di tempat” dan tak pernah maju-maju dari jebakan ritual. Ritual memang perlu, tetapi bukan berhenti di sana. Ribuan babi disembelih orang Bali pada saat Penampahan Galungan, ribuan penjor berdiri di pinggir jalan, ratusan pura dikunjungi dan dihaturkan sesajen saat Galungan, tetapi apakah dharma sudah menang, apakah sifat-sifat adharma sudah berkurang? Lihat di sekeliling kita, umat Hindu bertengkar soal kuburan, alam Bali diperkosa dari pantai sampai gunung, berbeda partai saling bacok. Lalu apa arti merayakan Galungan kalau adharma tak pernah berkurang?
Galungan memang tak ada dalam kitab suci Weda. Namun, merayakan kemenangan dharma melawan adharma, yang pada hakekatnya adalah ajaran untuk selalu berbuat yang “benar”, menghiasai banyak sloka-sloka suci Weda. Karena Hindu menyebar di dunia dengan memberi keleluasaan untuk menyerap budaya lokal, maka “perayaan dharma” ini berbeda bentuknya. Perayaan itu pun kemudian dicarikan simbol-simbol lokal untuk lebih membumi, sehingga masyarakat yang awam mudah untuk menghayatinya.
Di India, misalnya, kemenangan dharma itu dirayakan dua kali setahun. Di bulan April (Waisaka) dirayakan dengan sebutan Wijaya Dasami. Simbol yang diambil adalah kemenangan Dewi Parwati mengalahkan raksasa Durgha yang bersembunyi di dalam tubuh Mahasura. Hari raya ini juga disebut Durga Nawa Ratri. Kemudian di bulan Oktober (Kartika) simbol yang diambil adalah kisah kemenangan Rama atas Rahwana. Perayaan ini disebut Rama Nawa Ratri. Inti dari kedua perayaan itu sama, bersyukur dan bersukaria atas kalahnya adharma, dan dirayakan sepuluh hari.
Barangkali untuk “menyesuaikan” dengan India di mana agama Hindu lahir, leluhur kita di Bali juga merayakan kemenangan dharma dua kali setahun, meski tak persis dengan tahun Masehi, karena perhitungan yang dipakai adalah wariga, bukan sasih. Dan perayaan yang disebut Galungan ini dijatuhkan pada Rabu Kliwon Dungulan, lalu ditutup dengan Hari Raya Kuningan, yang juga berjarak 10 hari.
Umat Hindu di Jawa sebaiknya juga merayakan Galungan. Dalam Kidung Panji Amalat Rasmi dan Kidung Pararaton, disebutkan pernah ada perayaan kemenangan dharma di zaman Majapahit pada wuku Dungulan. Seperti diketahui, wariga yang ada di Bali sumbernya adalah di Jawa, semuanya sama. Masalahnya mungkin – ini perlu dikaji—leluhur kita di Bali mengkaitkan perayaan Galungan itu dengan mitos Mayadenawa. Sampai saat ini, masyarakat Bali terjebak pada mitos itu. Padahal tak ada prasasti apapun tentang Mayadenawa yang dikaitkan dengan Galungan, kecuali karya sastra yang sifatnya fiksi. Yang ada adalah prasasti yang menyebutkan, orang Bali “lama sekali” tak merayakan Galungan, dan perayaan itu baru dibuat rutin kembali sejak tahun 1126 ketika Bali diperintah Sri Jayakusunu. Dikaitkannya Galungan dengan legenda Mayadenawa membuat Galungan menjadi “bali sentris” dan barangkali ini membuat umat Hindu non-Bali kurang sreg merayakan kemenangan dharma pada saat Galungan ini.
Ke depan kita harus lebih banyak lagi menelaah ajaran Hindu berdasarkan sastra dan tatwa. Bagi umat Hindu non-Bali, kalau memang tak sreg merayakan kemenangan dharma bersama-sama orang Bali, silakan membuat perayaan sendiri pada hari yang berbeda. Seperti halnya di India, ini menunjukkan Hindu begitu universal, ibarat taman dengan beragam bunga yang indah. Adapun bagi umat Hindu di Bali, mari kita rayakan Galungan dengan mencari inti filsafahnya, membunuh sifat-sifat adharma untuk kemenangan dharma, dan mensyukuri kemenangan itu.
Suksesnya perayaan Galungan seharusnya bisa dilihat dari masyarakat yang lebih tentram dan damai, bukan banyaknya orang mabuk di balai banjar yang disulap jadi bar. Lebih-lebih Galungan di tengah-tengah masa kampanye Pemilu. Kalau ketenangan masyarakat Bali terusik menjelang dan setelah Pemilu ini, maka Galungan sudah gagal total, tak ada gunanya penjor dan sesajen itu, karena adharma yang tetap menang. Selamat Hari Raya Galungan, untuk Anda yang bisa mengalahkan adharma.***
Supaya Tuhan Punya Utang
Suatu ketika, selesai saya bersembahyang di sebuah pura, saya memasukkan dana punia di kotak yang telah disediakan. Keponakan saya bertanya: “Untuk siapa dana punia itu? Kan tidak ada orang yang menjaga kotak itu?”
Saya jawab: “Kotak itu dijaga oleh Tuhan. Uang saya pun juga untuk Tuhan, supaya Tuhan punya utang sama saya.” Entah anak ini mengerti atau tidak, ia tak lagi bertanya.
Beberapa bulan kemudian, saya bersama dia datang ke Pura Dalem Puri di Besakih saat piodalan. Di sini, banyak umat memberikan dana punia. Ada panitia yang mencatat dan kemudian diumumkan namanya. Konon ada kebanggaan nama itu disebut dan didengar oleh banyak orang. Saya juga memberikan dana punia, dan dicatat oleh panitia.
Keponakan saya seperti orang bengong karena perhatiannya tertuju pada pengeras suara. Sampai akhir pembacaan nama-nama penyumbang pada sesi itu, ia tak mendengar nama saya disebut. “Kok sumbangan Paman tidak diumumkan?” Saya jawab: “Sudah diumumkan, kan saya memakai nama asal-asalan. Orang tak perlu tahu nama saya, tapi Tuhan sudah pasti tahu. Yang penting sekarang Tuhan punya utang sama saya.”
Keponakan saya masih penasaran. “Kalau begitu, sudah berapa banyak Tuhan berutang pada Paman?” “Utang-utang Tuhan yang dulu semuanya sudah dibayar lunas, bahkan pakai bunga segala. Utang Tuhan sekarang ini, ya, sebesar yang saya puniakan tadi,” kata saya.
Karena keponakan saya diam, saya jelaskan panjang lebar. Setiap saya memberikan dana punia, ada saja karunia Tuhan yang saya dapatkan. Rejeki saya tak pernah seret dan itu selalu saya syukuri betapa pun kecilnya. Orang sering bimbang, bagaimana berdana punia kalau tak ada uang, beri dulu dong rejeki. Orang-orang semacam ini, meski pun diberi rejeki berlimpah, tetap akan pelit berdana punia. Dia bisa berkata, “gaji saya hanya sejuta, bagaimana bisa menyumbang?” Ketika bulan depannya gaji naik lima juta, dia tetap berkata: “baru lima juta, kebutuhan saya kan banyak”. Bahkan ketika dia dapat rejeki tambahan di luar gaji, tetap tidak melaksanakan dana punia, padahal ini jelas “ujian Tuhan”. Nah, kok Tuhan diajak main-main.
Saya berkali-kali menerima anugrah Tuhan yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Suatu kali saya “setengah ditodong” Rp 5 juta untuk perbaikan pura. Karena “todongan” itu dilaksanakan dalam pertemuan di pura, saya terima. Di dompet ada sekitar satu juta uang. “Saya siap, uangnya minggu depan,” kata saya. Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke tempat seorang Sulinggih. Ternyata beliau sakit, saya pun membelikan obat-obatan dulu. Pulang ke rumah, yang saya pikirkan adalah bagaimana mencari uang, apa yang akan dijual. Saya tak punya tabungan lagi, uang sudah habis untuk membeli gamelan gong kebyar. Rupanya kegelisahan saya “dipantau” Tuhan. Sampai dirumah dan membuka email, dari email dari Seiichi Okawa di Tokyo. Isinya: “Buku Menggugat Bali edisi Jepang dicetak ulang yang ketiga, royalty sudah saya transfer ke bank bapak.” Rasanya saya seperti menangis terharu, tak pernah membayangkan rejeki itu, saya sudah melupakan buku itu pernah dicetak di Jepang. Saya sembahyang dan membayangkan Tuhan sebagai sahabat saya (Tuhan bisa diposisikan sebagai apa saja), lalu saya berucap: “Hyang Widhi, Kamu kok nggak mau saya utangi.”
Konsep dana punia dalam Hindu adalah menyerahkan sebagian kekayaan yang ada untuk makhluk Tuhan. Karena makhluk ciptaan Tuhan itu banyak sekali, ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, biarkanlah Tuhan yang mengaturnya, kepada siapa diberikan. Tuhan tentu menciptakan “alat” di dunia ini, boleh jadi berwujud panitia piodalan, sehingga hasil dana punia dipakai untuk piodalan atau memperbaiki pura. Mungkin saja “alat” itu bernama Lembaga Panti Asuhan, Lembaga Jompo, bahkan “alat” yang diciptakan Tuhan itu bernama Badan Dharma Dana Nasional. Lembaga ini tak akan berdiri tanpa campur tangan Tuhan. Nah, dana punia disalurkan oleh “alat-alat” yang diciptakan Tuhan itu, sesuai bidangnya. Karena itu, kalau kita menyumbang uang ke Lembaga Panti Asuhan jangan berharap uang itu akan dipakai memperbaiki pura.
Apa perlu dana punia dicatat? Perlu, dalam arti sebatas untuk bahan pertanggungan-jawab panitia atau lembaga atau “alat” ciptaan Tuhan itu. Meski perlu dicatat, tidaklah harus pemberi dana punia mencatatkan namanya, apalagi dimaksudkan untuk diumumkan atau dipamer-pamerkan. Memberi dana punia bukan untuk tujuan pamer. Kalau dipublikasikan tanpa niat pamer (supaya Istri tahu kemana uangnya Bapak), bolehlah. Ada seorang tokoh (sekarang jadi calon wakil rakyat) memberi dana punia kepada Panitia Pembangunan Pura dengan mengundang televisi swasta untuk peliputan. Biaya yang dihabiskan untuk peliputan Rp 3 juta, padahal dana punia yang disumbangkan itu hanya semen yang nilainya tak lebih dari Rp 2 juta.
Kenapa saya memberikan dana punia? Karena saya merasa kaya. Lo, mobilnya bekas, bajunya murah, kok mengaku kaya? Karena ada orang yang hanya punya motor bekas, bajunya robek, jadi saya lebih kaya. Lalu, pada saat yang punya motor bekas itu memberi dana punia, meskipun hanya seribu rupiah di pura (jangan menghitung besarnya dana punia, hitunglah ketulusannya), itu pasti karena dia juga mengaku kaya. Karena ada orang yang tak punya motor, jalan kaki ke mana-mana tanpa baju.
RgWeda X 117.5 menyebutkan: “Orang yang punya kekayaan harus bermurah hati untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada orang miskin. Dia harus melihat jalan kebajikan yang menguntungkan ini.” Ukuran “kaya” dan “miskin” hendaknya tidak dilihat dari jumlah harta. Ada orang yang hartanya berlimpah-limpah, tetapi dia selalu merasa “miskin” dan jarang memberikan dana punia. Orang ini pasti gelisah dengan kakayaanya, karena tidak tahu ada “jalan kebajikan” itu.
Bahkan orang itu tak ubahnya sebagai “mayat hidup”. Ini kalau kita percaya pada ajaran Hindu. Kitab Sarasamuscaya sloka 179 menyebutkan: Yasya pradanavandhyani dhananyayanti yanti ca, sa lohakarabhastreva evasannapi na jivati. Saya menerjemahkan sloka itu dengan puitis: “Mereka yang punya kekayaan tetapi tidak berdana punia, mereka ibarat orang mati. Hanya karena mereka masih bernapaslah yang membedakannya dengan mayat.”
Mari berdana punia sebelum kita menjadi mayat.
Kampanye
Ia memberi contoh, bagaimana partainya mengkampanyekan sembako murah. Pokoknya program kilat serba murah agar terjangkau oleh wong cilik. “Saya sebutkan, enam tahun lalu harga premium tiga ribu, sekarang empat ribu lima ratus. Harga beras dua ribu, sekarang lima ribu. Jadi lebih enak masa lalu,” katanya memberi contoh. Apa yang terjadi? “Rakyat menertawai saya. Perbandingan itu sangat konyol, kenapa tidak dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu, atau dibandingkan dengan zaman Majapahit sekalian?”
Saya juga ikut tertawa mendengar contoh ini. Ada contoh lain? “Banyak sekali, semuanya garis partai. Saya katakan, jika saya terpilih akan memberikan pupuk gratis dan semua petani mendapat cangkul, anak-anak petani yang masih sekolah akan mendapatkan laptop gratis,” katanya. Apa reaksi masyarakat? “Tadinya saya kira mereka senang, malah saya diejek sebagai pembual. Mereka bertanya, dari mana saya dapat duit? Saya tak bisa menjawab karena memang tak tahu dari mana sumber duitnya.”
Calon legislator ini seperti sudah stress, padahal kampanye baru memasuki minggu pertama. Ia mengaku modalnya cekak. Modal pertama menjual sawah, satu-satunya warisan orangtuanya. Dapat uang Rp 45 juta, sebanyak Rp 30 juta untuk menyuap pimpinan partainya agar bisa mendapat nomor urut satu. Ternyata nomor urut tak menentukan dan ia mengaku rugi besar ditelikung nomor urut di bawahnya. Terpaksa ia menghabiskan sisa anggaran untuk membuat baliho. Sekarang untuk modal kampanye ia menggadaikan rumahnya, dapat Rp 25 juta. “Ya, modalnya kecil, pesaing saya modalnya ratusan juta,” katanya.
Bahan kampanye, kata dia melanjutkan, sudah diprogram dari pusat, tapi tak nyambung dengan situasi setempat. Mau apa lagi, dia sendiri tak tahu bagaimana menyusun bahan kampanye. “Pernah saya lemparkan ke masyarakat soal gaji. Kalau saya terpilih, 70 persen gaji saya akan disumbangkan untuk orang miskin di pedesaan. Janji ini bukan saja menunai ejekan, malah saya nyaris diusir. Saya diteriaki: calon koruptor, calon penerima suap. Duh, sedihnya,” katanya nelangsa.
Saya bertanya, apa janji menyumbangkan gaji itu pernah disepakati oleh calon wakil rakyat? Dia membenarkan. Gaji wakil rakyat nanti, 30 persen untuk iuran partai, selebihnya disumbangkan saja, tak apa-apa. Toh akan ada uang tambahan di luar gaji resmi, misalnya, uang reses, uang sidang, uang dengar pendapat, uang studi banding, uang dari mitra kerja di eksekutif, uang dari badan usaha milik Negara, dan uang dari kontraktor yang proyeknya dibahas di legislatif. “Ini katanya soal biasa, kalau di pusat bisa mendapat milyaran, di provinsi dalam ratusan juta, di kabupaten paling apes lima puluh juta sebulan, belum lagi kalau mensahkan undang-undang atau peraturan daerah,” katanya. “Ini yang membuat saya tertarik mengadu nasib untuk menjadi calon legislator.”
Saya tak bisa memberi saran. Dia bilang: “Bagaimana kalau saya tak usah kampanye terbuka? Lebih baik membuat baliho lagi dengan kata-kata seperti yang sudah digariskan partai: mohon doa dan dukungan, siap berjuang untuk rakyat, tempat rakyat mengadu….”
Saya memotong: “Apa rakyat percaya? Anda sendiri justru mengadu ke saya…” Dia kaget, lalu katanya lirih: “Yang penting kan tidak diejek di depan umum.”
Mencontreng
Peserta kursus lebih banyak ibu-ibu, usianya sekitar 50-an ke atas. Mereka umumnya tak begitu lancar membaca dan menulis. Ketika sosialisasi diselenggarakan, mereka kebingungan. Padahal kertas suara hanya berisi lima partai, tapi ukurannya sama besar dengan yang dipakai Pemilu nanti.
Membuka dan melipat surat suara yang sebesar Koran itu saja sudah bikin pusing karena bilik pencontrengan kurang luas. Ada yang sampai bersimpuh, ada yang menempelkan dulu ke dinding. Jika lipatan kurang bagus, tak bisa masuk ke kotak suara, lubang kotak kekecilan. Kalau dipaksakan, surat suara robek, jadi tak sah.
KPU mendapat masukan bagaimana ukuran ideal bilik suara, termasuk lebar lubang kotak suara. Namun, Komisi merasa tak perlu bertanggungjawab jika masih terjadi salah contreng. Alasannya, masyarakat sudah tahu.
Tahu apa yang dicontreng, namun tak tahu “teknik” mencontreng. Orang kampung itu asing dengan pulpen dan alat tulis sejenis. Untuk memegang saja perlu latihan berkali-kali. “Saya sehari-hari pegang pisau, sekarang pegang pulpen, ya, tak bisa,” kata seseorang. Pemilu sebelumnya sangat gampang karena mencoblos, bagaimana pun cara memegang paku pencoblos, yang penting kan ada lubangnya. Sekarang, kalau memegang pulpen tidak benar, contrengan jadi tak pas dan kebanyakan melewati garis pemisah nomor. Ini tak sah, karena contrengan mengenai dua nama caleg.
“Kenapa tak mencontreng gambar partai saja, kan lebih mudah, karena ruangnya lebih besar,” tanya saya kepada penyelenggara kursus. Jawabnya: “Saya bisa rugi, itu kan suara mengambang, ini tarung bebas, saya harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya.”
Saya jadi maklum, kalau dari tiga “kursus mencontreng” itu, dua penyelenggara dari partai yang sama tapi caleg berbeda. Satu untuk nomor 4, satu lagi nomor 7. Peserta memang sudah diarahkan untuk mencontreng nomor urut itu. Mereka juga dibekali kartu sebesar kartu nama, yang mengingatkan kolom partai dan nomor yang dicontreng. Ketika latihan, ibu-ibu desa itu asyik menghafal angka yang akan dicontreng.
Kenapa sih ibu-ibu? Konon, pemilih muda tak mudah “dipegang”. Mereka kesannya “anti Pemilu”. Baliho caleg dicorat-coret, wajah manis perempuan diberi kumis dan cambang, wajah-wajah ganteng ditulisi kata: gombal, penipu, pemeras. Mereka mengaku akan golput, terpengaruh media massa yang menyoroti betapa buruknya perilaku anggota dewan. Sedangkan mereka yang lebih dewasa dan keluarga mapan mengaku, lebih baik sembahyang ke Pura Besakih daripada mencontreng. Maklum, 9 April nanti adalah puncak upacara Panca Wali Krama, ritual sepuluhtahunan.
Kursus ini ada daya tariknya. Selama tiga hari kursus, mereka dapat sebungkus kue dan sebungkus nasi. Lalu, ada janji, jika saat Pemilu nanti pelajaran di “kursus” itu benar, mereka dapat “upah” Rp 50 ribu. Variasi upah berbeda di setiap tempat kursus, Rp 50 ribu itu angka terendah.
Saya semakin yakin, Pemilu nanti adalah pemilu yang paling rumit di dunia: sistem yang cerdas untuk masyarakat yang bodoh. Partai politik yang terbesar di Bali (contoh yang hampir nyata) tetap akan mendapat urutan ketiga, karena pemenang pertama adalah suara tak sah, pemenang kedua golput. Tolonglah ada yang begerak, supaya keyakinan saya tak terbukti, mumpung masih ada waktu.
Sabtu, Februari 14, 2009
Bodoh
Karena saya sudah capek bicara dalam seminar, saya menanggapi seadanya: “Apa contohnya?”
Dia lalu menyebut kasus demo anarkis di Medan yang menyebabkan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat tewas. Pemekaran wilayah, menurut dia, hanyalah pintu masuk untuk berebut jabatan. Di mana-mana, pencetus ide pemekaran provinsi, kalau berhasil, punya kesempatan besar menjadi gubernur, pencetus pemekaran kabupaten menjadi bupati. Teman-temannya menjadi pejabat semua, minimal anggota dewan. Tak dipikirkan, berapa anggaran yang harus disediakan untuk mengisi jabatan dan fasilitas itu dan apakah sebanding dengan apa yang diperoleh rakyat akibat pemekaran. Usul pemekaran tetap ngotot diperjuangkan. Nah, ketika terjadi kebrutalan dan korban jatuh, bukan jabatan gubernur yang datang, tetapi “jabatan” sebagai tahanan. Ini kan bodoh.
“Ada contoh lain?” Tanya saya memotong. Dia bicara lagi: “Ya, kenapa menyalurkan pendapat harus lewat aksi brutal? Mahasiswa menuntut pemerintahan yang bersih, pagar kantor gubernur diobrak-abrik. Masa menuntut harga-harga turun, fasilitas umum di jalanan dirobohkan. Buruh menuntut gaji naik, jalur perekonomian penting diblokir. Mereka merusak dan membebani keuangan Negara dengan dalih memperbaiki keadaan. Ini kan pekerjaan orang bodoh.”
“Maksud saya, contoh versi lain, saya bosan dengan itu,” kata saya lagi. Dia berhenti sejenak lalu bicara: “Sekarang orang berebut ingin jadi wakil rakyat di daerah. Uang yang dihabiskan bermilyar rupiah untuk membuat baliho, memberi sumbangan, kenduri dan macam-macam. Padahal, kalau dia sudah jadi wakil rakyat, gajinya sekitar Rp 10 juta, katakan naik jadi Rp 20 juta. Lima tahun menjabat kan baru dapat Rp1,2 milyar. Bagaimana mengembalikan modal? Belum dipotong sumbangan partai dan untuk makan. Kenapa sebodoh itu?”
“Wah, contohnya klise. Ada yang lain?” kata saya. Tak butuh waktu lama, dia bicara: “Ibu Mega memasang iklan besar-besar yang menyalahkan pemerintah. Ini salah, itu melanggar janji, itu memutar fakta. Apa rakyat semua bodoh? Ketika Ibu Mega menjabat, memang nya tak ada yang salah? Rakyat berpaling, pasti karena ada sesuatu yang salah. Kalau cerdas, semestinya membuat iklan yang simpatik, seperti ikklannya partai lain.”
“Stop, Anda kok sinis dengan Ibu Mega. Saya tak mau contoh itu,” saya memotong. Dia cekatan sekali melanjutkan: “Kalau begitu soal kegundahan Presiden SBY, rumor ABS. ABS kan bisa macam-macam, bisa Asal Bukan Sutiyoso, Asal Bukan Sultan, Asal Bukan Surya Paloh, Asal Bukan Soekarno Putri, Asal Bukan Sontoloyo. Yang saya harapkan, Pak SBY bijaksana sehingga tak usah menanggapi hal-hal yang kecil. Tenang sajalah, jangan panik.”
“Itu contohnya terlalu tinggi,” kata saya. “Oke,” kata dia cepat-cepat, “ada ribuan orang mendatangi dukun tiban yang baru berumur sepuluh tahun, semuanya ingin kesembuhan instan. Dinas Kesehatan jatuh wibawanya dan tak ada orang cerdas yang memberikan pandangan kalau semuanya itu hanya sugesti…”
“Stop, itu menyangkut keyakinan, tak bisa diperdebatkan, ada contoh lain?” kata saya. Dia berpaling: “Tadi saya pikir saya yang bodoh, ternyata Anda jauh lebih bodoh, tak satu pun pertanyaan saya Anda tanggapi.” Orang itu pergi, saya sampai lupa menanyakan identitasnya.
(Diambil dari Koran Tempo, 8 Februari 2009)
Golput
Keluar rumah selangkah saja, sudah bertebaran baliho para calon legislatif. Wajah-wajah itu, membuat saya ngengir berkepanjangan. Ada yang bergaya orator ulung dengan latar belakang gambar Soekarno menuding. Ada yang seperti berteriak dengan latar foto Megawati yang mengacungkan tangan. Ada yang kalem, mirip terdakwa kasus korupsi, latar belakangnya gambar Sultan HB X yang juga kalem. Calon legislatif wanita seperti kontes Miss Universe, meski pun ada yang posenya seperti bakul jamu, tukang pijat, dan sebagainya.
Persaingan begitu ketat, calon wakil rakyat harus menjajakan wajah dan nomor urutnya lewat baliho dan (yang punya uang berlimpah) pasang iklan di koran. Pemilu sebelumnya lebih sederhana, partai yang menentukan siapa yang duduk atau tidak, pemilih pun mencoblos partai. Sekarang, setiap calon harus “unjuk gigi. Di pulau sekecil Bali saja ada 5079 calon legislatif yang bertarung memperebutkan 399 kursi. Kalau satu orang membuat sepuluh baliho maka ada 50 ribu lebih baliho. Ini angka terendah, karena seorang calon untuk wakil rakyat di pusat dan provinsi yang wilayah pemilihnya lebih luas, membutuhkan lebih dari 300-an baliho. Bayangkan berapa uang yang beredar dalam “bisnis baliho” ini, lalu bayangkan akan ada 4680 orang yang kalah dan mungkin punya utang.
Berapa milyar atau trilyun uang yang habis untuk baliho di seluruh Indonesia? Jika ini mau dihitung, saya bisa urung tersenyum. Saya lebih tertarik membaca slogan yang ada di baliho. Sebagian besar menyebutkan, akan berjuang untuk rakyat, dengan bahasa Indonesia yang rusak parah. Sebagian besar pula kurang percaya diri sehingga perlu menambah foto Soekarno, Megawati, Wiranto, Prabowo, Sultan HB X di latar belakangnya. Bahkan ada baliho dengan latar belakang Presiden AS, Obama. Slogannya: “Saatnya orang muda yang tampil”.
Karena bukan memilih partai, tetapi memilih orang, rasanya saya akan golput. Soalnya saya bingung. Dengan sistem Pemilu sekarang, domisili pemilih menyebabkan dorongan memilih itu berbeda. Kalau saya berdomisili di Klaten, misalnya, pilihannya gampang, antara Puan Maharani atau Hidayat Nurwahid. Bukan maksud saya memilih PDI Perjuangan atau memilih PKS, tetapi karena Puan cantik dan Hidayat Nurwahid saya kenal pemikirannya. Jadi, urusannya personal.
Saat ini saya berada di daerah pemilihan di mana calon-calon legislatifnya tak saya kenal ulahnya, selain fotonya yang nampang di baliho. Kalau saya mengikuti imbauan “memilih dengan cerdas dan tepat seraya menggunakan hati nurani”, maka pilihan saya adalah tetap tidak memilih alias golput. Ini menurut “hemat” saya, yang bisa berbeda menurut “hemat-hemat” orang lain.
Masalahnya, kenapa golput diharamkan oleh MUI? Kalau nurani saya berkata: itu calon koruptor, itu calon peselingkuh, itu calon wakil rakyat yang tak pernah sidang, itu calon yang hanya bisa omong, bukankah saya lebih baik menyelamatkan bangsa ini dengan cara tidak memilih mereka? Biar suara mereka tak memenuhi “bilangan pembagi pemilih”. Dengan ongkos yang tinggi berebut kursi di DPR atau DPRD, sudah pasti langkah pertama mereka di dewan adalah “bagaimana mengembalikan modal”. Untuk apa orang seperti itu diberi kursi? Dan akhirnya, untuk apa memilih kalau tak ada yang layak dipilih?