Di sebuah warung berlabel “mini market” di kawasan Ubud, Bali, saya terkejut menyaksikan adegan ini. Seorang anak muda tergopoh-gopoh menuju rak obat dan bertanya pada pelayan: “Ada neolib?”
Ia tak bergurau mengucapkan kata itu. Pelayan, perempuan yang juga muda, menjawabnya dengan kalem, jauh pula dari nada canda: “Neolib untuk flu, apa neolib untuk nyeri?” Si lelaki menjawab cepat: “Neolib untuk flu.” Pelayan memberikan satu bungkus tablet bergambar kepala orang. Transaksi terjadi, lalu anak muda itu pergi.
Setengah penasaran saya mendekati pelayan. “Kenapa obat yang sudah populer itu disebut neolib?” Barulah pelayan itu tersenyum, manis juga, dan khas pelayan warung di kawasan pariwisata. “Di sini orang sudah terbiasa dengan plesetan yang dipopulerkan televisi. Semua obat dengan awalan neo disebut neolib, makanya saya tanya, neolib untuk flu atau nyeri. Sering pula disebut neolib tablet atau neolib krim,” ujar si pelayan.
Konon, plesetan itu hanya awalnya saja menimbulkan nada canda. Begitu lewat tiga hari apalagi seminggu, plesetan sudah tak ada nada candanya lagi, sudah biasa-biasa saja. Ternyata banyak juga jenis “plesetan politik”, bukan hanya neolib. Kalau ada orang yang tadinya jarang bergaul atau enggan menyapa, lalu tiba-tiba ramah, orang itu dijuluki: “kerakyat-rakyatan”. Misalnya: “Pak Dogler sekarang kerakyat-rakyatan, pasti ada maunya.”
Anehnya, julukan “kerakyat-rakyatan” hampir selalu berkonotasi negatif. Ada temannya yang lain. Ketika seorang pengendara sepeda motor meraung-raungkan mesin motornya saat melintas di depan mini market itu, petugas parkir berteriak: “lanjutkan, lanjutkan, lebih cepat lebih baik mati”. Begitu pula ketika petugas parkir menggoda cewek, pedagang bakso menggoda: “Pak Parkir, lanjutkan, lanjutkan, mumpung istri tak ada…”
Apa tahu arti neolib? Ini pertanyaan yang saya ajukan kepada pelayan warung, pedagang bakso, dan petugas parkir. Pelayan hanya tertawa karena memang tak tahu. Pedagang bakso juga tertawa, lalu dia bilang: “Saya belum gila, tak perlu neolib”. Dan ini jawaban petugas parkir, agak panjang: “Itu kan dagelan bapak-bapak di televisi. Semua bersilat kata. Semua mengaku pintar. Semua mengaku dekat rakyat. Kita nonton senang saja, banyak kata-kata baru untuk bahan becanda.” Saya tanya, kalau diberi kesempatan bicara, mau bilang apa kepada bapak-bapak itu? Tak lama berpikir, petugas parkir berkata: “Berhenti saja deh ngomong membela rakyat, kok nggak tahu malu ya? Kan kelakuannya sudah diketahui rakyat.”
Malam ini, mungkin besok malam pula, kata neolib boleh jadi masih beredar. Pesaing pasangan SBY-Budiono terus menghunjamkan istilah neolib ini untuk menyerang. Budiono jadi sasaran tembak oleh orang-orang yang berada di kubu JK-Win dan Mega-Prabowo. Tembakan yang berhasil, bukan karena penembak yang piawai, tetapi Budiono mau menyediakan diri bersibuk-sibuk membantah. Ia menari dalam irama gendang lawannya.
Jadi, Budiono memang lugu dan “kurang mahir” berakrobat politik. Bukan saja dituduh membawa paham neolib, tapi juga disebut “mbahnya neolib” atau seperti yang dibilang tim suksesnya Mega-Pro, “ayatulahnya neolib”. Sampai kapan Budiono terus menari?
Padahal, isu neolib sudah ditertawakan masyarakat. Bahkan slogan yang diembel-embeli “kerakyatan” juga dicibir. Orang desa yang lugu bertanya: “Para jenderal yang bertarung itu kok bisa kaya sekali, berapa gajinya sebagai tentara? Sekarang ngaku membela rakyat, apa nggak nilep uang rakyat sebelumnya?” Mungkin ini perlu jawaban.
(Dari Koran Tempo Minggu 31 Mei 2009)
Kamis, Juni 04, 2009
Neolib
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
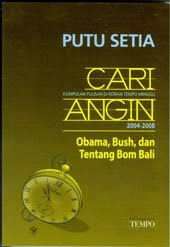


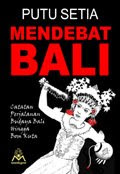

Tidak ada komentar:
Posting Komentar