Setiap bencana membawa hikmah. Datangnya malapetaka menyisakan perenungan. Persoalannya adalah apakah kita akan mau mengambil hikmah dan mau merenungi kembali perjalanan kita di masa lalu untuk dijadikan sesuluh di masa depan?
Bali diguncang bom tahun 2002. Kita diberi hikmah bahwa industri pariwisata sangat rentan dengan keamanan. Perekonomian Bali yang bersandar pada dunia pariwisata hancur. Kita sempat merenung sejenak, apakah pariwisata model Bali ini sudah benar bertumpu pada pariwisata budaya? Namun perenungan itu tidak tuntas. Corak pariwisata jauh melenceng dari akar budaya Bali. Kontribusi pelaku budaya tak dihargai oleh hasil pariwisata. Toh, pelaku pariwisata tetap berusaha memulihkan bisnis itu, dan ketika menggeliat, bom kedua meledak.
Ada pepatah yang berbunyi: “Pelanduk yang paling tolol tak akan terantuk dua kali pada batu yang sama”. Orang Bali tentu bukan pelanduk yang tolol. Karena itu, setelah dua kali bom mengguncang, sebaiknya kita merenungi, apa yang sebenarnya terjadi pada Bali?
Orang Bali setuju daerahnya menjadi tujuan wisata Indonesia dengan catatan landasannya budaya. Maka lahirlah istilah pariwisata budaya. Artinya, yang dijual kepada wisatawan yang pertama dan utama adalah budaya. Tapi apa yang terjadi? “Halaman rumah” orang Bali, tempat budaya itu lahir, digerogoti terus. Tanah sawah dijadikan hotel atau ruko, jurang-jurang dipenuhi bungalows, air untuk pengairan dialirkan ke hotel-hotel, tempat suci direkayasa sehingga tidak lagi ada vibrasi kesucian sebagaimana dahulu. Orang Bali yang semula agraris dipaksa menjalani kehidupan industri, dan pola konsumtif pun diperkenalkan dengan gencar. Hotel, restoran, travel sebagian besar punya orang luar Bali, bahkan pengelola Bandara Ngurah Rai pun tak menyisihkan penghasilannya untuk Bali.
Bersamaan dengan itu Bali pun diserang dari “tingkah menengah bawah”. Pendatang yang membawa budayanya sendiri tak bisa dibendung, dan anehnya dibiarkan oleh pemimpin-pemimpin Bali. Maka lahirlah budaya berjualan koran di lampu lalu lintas, ngamen di rumah makan dan terminal, kaki lima di trotoar dan di sepanjang jalan, pemulung ke desa-desa, kafe juga ke desa-desa lengkap dengan wanita tuna susilanya. Rumah-rumah kumuh berdiri yang bertolak belakang dari konsep Tri Hita Karana, belum lagi tempat ibadah dengan segala perlengkapannya. Pola konsumtif orang Bali pun dimanfaatkan dengan baik oleh pendatang, semua kebutuhan ritual orang Bali disuplay dari Jawa Timur, dari janur, bunga, buah sampai telur bebek.
Kalau kita mencoba merenung dengan jujur, semua ini menghancurkan budaya orang Bali. Bagaimana mempertahankan subak kalau airnya sudah dibawa ke hotel, sawah dikapling, lalu yang memanen padi orang Jawa atau Lombok yang mendirikan kemah-kemah di jalanan? Berapa ritual yang hilang, dari mendak toya di pura bedugul sampai ngadegang Dewi Sri…. Bagaimana generasi muda Bali tertarik ke balai banjar untuk belajar menabuh dan mekidung, kalau kafe berdinding bambu dengan wanita menor ada di sudut-sudut desa? Bagaimana orang mau merawat pohon juwet, sotong, duku, dan lainnya, kalau orang Bali diarahkan membeli apel Amerika dan peer dari Cina untuk yadnya ke pura? Apalagi membuat dodol dan apem, lebih praktis dodol Garut dan dodol Kudus, sementara apem diganti roti kukus. Laklak Bali sudah sulit dicari di Denpasar, ada penggantinya, kue serabi dan dawet dari Banyumas.
Kalau Bali ingin ajeg dengan budayanya yang tinggi seperti masa lalu, sarana untuk melahirkan budaya itu jangan dihancurkan. Air Bali harus tetap untuk kepentingan subak agar pertanian tetap jalan, karena dari sawah itu berbagai budaya lahir. Kalau hotel-hotel besar membutuhkan air, cari alternatif lain, entah menyuling air limbah atau menyuling air laut. Jadi modal dasar budaya itu jangan digerogoti kalau betul pariwisata Bali diarahkan ke budaya. Apa modal dasar itu? Tak lain adalah tanah dan itu artinya tanah pertanian karena budaya Bali adalah budaya agraris.
Pemerintah harus memproteksi tanah pertanian Bali. Tanah Bali tak boleh jatuh ke tangan orang non-Bali. Pemerintah harus mensubsidi pertanian, baik dalam hal pengembangan produk maupun pemasarannya. Pemerintah harus mendorong agar orang Bali bisa mandiri. Jangan biarkan orang Bali tergantung pada orang luar, apalagi untuk kebutuhan menjalankan tirualnya, karena dari situlah sumber adanya budaya Bali yang adiluhung. Tokoh agama harus ikut turun tangan, bagaimana menyadarkan orang Bali bahwa persembahan untuk Tuhan yang paling utama adalah persembahan dari hasil jerih payah yang dihasilkan tanah Bali.
Mari kita ubah pola kehidupan di Bali, kita kembali ke sawah, ke sektor pertanian. Tentu saja menjadi petani moderen yang mempertimbangkan produk unggulan. Intelektual Unud harus menjadi pelopornya, seperti yang dilakukan seorang dosen pertanian Unud yang kini mengembangkan rebung bambu tabah (tiying tabah) di kampung saya. Kembali ke dunia agraris akan melanggengkan budaya Bali. Kalau tetap budaya menjadi tema pariwisata Bali, hasil pariwisata harus dikembalikan kepada petani Bali, pelaku budaya itu sendiri. Jangan serakah semuanya diboyong ke luar Bali.
Selasa, April 07, 2009
Kembali ke Sawah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
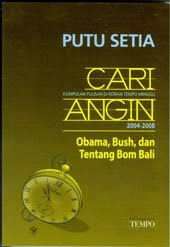


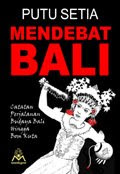

Tidak ada komentar:
Posting Komentar