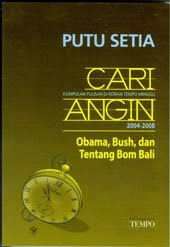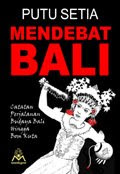Saya tidak sedang menulis Rani, atau nama lengkap di kartu tanda penduduknya, Rhani Juliani. Mantan caddy golf yang menjadi wanita terpopuler saat ini karena kasus pembunuhan Nasrudin itu, tidak saya kenal. Bagaimana saya menulis orang-orang yang tidak saya kenal?
Tapi saya mengenal beberapa orang yang dipanggil akrab Rani. Dari penulis fiksi, penyanyi, aktifis pers kampus, tentu dengan nama lengkap yang berbeda. Salah satunya adalah Sutirani, gadis asal Temanggung, bekas tetangga saya sewaktu saya tinggal di Sidoarum, Godean, Yogyakarta.
Rani Temanggung ini begitu tamat SMA tidak melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, barangkali mirip Rani Tangerang di awal-awalnya. Ia ikut Bu De-nya ke Yogya, kursus memijat beberapa hari, lalu menjadi gadis pemijat di sebuah “panti pijat tradisional”. Tak sampai sebulan ia bertahan, banyak hal yang ia keluhkan pada saya. Belakangan saya dengar dia menjadi pramuria – sebutan keren pelayan – di toko Sami Jaya, kawasan Malioboro. Entah sekarang.
Kenapa saya sering ingat Rani? Ia pernah berkeluh, seorang pria setengah tua, suatu hari menjadi “pasiennya”. Setelah waktu habis, Rani mengingatkan pijatan sudah selesai. Pria itu setengah marah membentak: “Mana tradisionalnya?” Rani mulanya kaget, apa yang dimaksudkan “tradisional” itu. Syukur, pria itu hanya marah, lalu keluar.
Belakangan banyak pria yang terus menggoda: “Dik, jangan lupa tradisionalnya, ya?” Atau kalimat ini: “Kalau pakai tradisional, tambah berapa?” Lama-lama Rani tahu, apa yang dimaksudkan: berbuat mesum. Ia punya jurus menolak, dan teknik penolakan itu yang membuat saya kagum, sekaligus sering ingat dia. Ia hanya mengatakan begini: “Bapak kan sudah berumur, mungkin bapak punya anak gadis seusia saya, kalau anak gadis bapak dibegitukan, apa bapak tega?” Teknik ini mempan, tapi Rani memutuskan tak lagi bekerja di panti pijat berembel tradisional itu.
Jurus ini sering saya kutip kalau saya lagi berceloteh soal moral di berbagai kesempatan. Malah saya kembangkan. Misalnya, bagaimana menghindari perselingkuhan? Saya katakan: “Ketika Anda sedang berniat untuk berselingkuh dengan wanita idaman lain, cobalah merenung satu menit, bagaimana kalau istri Anda juga melakukan hal yang sama dengan pria idaman lainnya. Apakah Anda senang?”
Jika jurus itu tak mempan, coba lagi merenung satu menit, dan sebut nama Tuhan. Tak satu pun agama membenarkan perselingkuhan dan perzinahan. Surga ada di telapak kaki ibu, dan ibu itu adalah wanita, janganlah wanita dilecehkan. Ada kitab suci yang jelas menyebutkan: “di mana wanita dihina dan diperlakukan tak semestinya, di sana kekacauan akan muncul”.
Jika nama Tuhan sudah disebut dan Anda tetap berselingkuh, itu artinya setan lebih banyak disekeliling Anda. Ini pun termasuk “skenario “ Tuhan, mereka yang lemah akan dijadikan alat untuk memberi kesempatan bagi orang lain bekerja dengan baik. Kalau penjahat tidak ada, polisi tak ada kerjaan. Kalau koruptor tak ada, Komisi Pemberantasan Korupsi tak dibentuk. Sekarang Anda memilih, yang baik atau yang buruk?
Saya tak menyindir bahwa kasus Rani-Nasrudin-Antasari diawali dengan pelecehan seorang wanita, karena “sinetron” ini masih berlanjut. Saya juga tak mau mengulangi petuah yang sudah klise agar pemimpin berhati-hati terhadap 3 TA: tahta, harta dan wanita. Saya hanya ingin mengatakan: wahai kaum pria, hormatilah wanita.
Sesekali menulis tentang moral, bolehlah. Suasananya masih merayakan Waisak, hari penuh kedamaian. Selamat bagi yang merayakannya.
(Koran Tempo 10 Mei 2009)
Senin, Mei 11, 2009
Rani
Jumat, Mei 08, 2009
Yadnya Tak Harus Mahal
Upacara Pitra Yadnya atau ngaben atau pembakaran jenazah adalah pekerjaan mudah dan murah yang sering dipersulit sendiri, dan dimahal-mahalkan oleh penjual banten. Begitu seorang Pandita Mpu memberikan penataran di hadapan para pemangku. Lalu, beliau bercerita, bagaimana orang memper¬siapkan banten ngaben itu jauh-jauh hari. Pas ketika upacara, semua banten lumutan, janurnya kusut, kue dan sesajinya berjamur, semut merayap penuh di sana-sini. Baunya pun tak sedap lagi. Pandita Mpu pun melanjutkan ceramahnya: “Apa banten seperti itu kita haturkan kepada Tuhan untuk mengantar roh yang akan kita upacarai? Apa Tuhan tidak tersinggung diberikan banten yang sudah bengu (bau busuk)?”
Ini sebenarnya cerita lama, tetapi memang masih terjadi di pedesaan, apalagi kalau di pegunungan. Setiap melakukan dharmawacana ke luar Bali, saya pun sering ditanya soal ini, soal banten yang bau. Maklum, banten dikirim dari Bali, dipaketkan lewat kapal laut, jadi selain karena bau alamiah, juga kemasukan air laut. Jawaban saya adalah, saya tak tahu, apakah Tuhan tersinggung atau tidak. Saya belum pernah mendengar ungkapan Tuhan Maha Tersinggung. Tapi kalau hati kita sudah tidak enak meng¬haturkan banten yang “bengu” begitu, apalagi daging ayamnya sudah dipenuhi lalat, bisa jadi Tuhan memang ter-singgung. Bukan karena banten itu, tetapi karena kita sendiri sudah tidak sreg lagi, jadi Tuhan hanya mengikuti kondisi batin kita. Jelasnya saya katakan, “saya yang tersinggung kalau muput diberi banten bengu, karena itu kalau nanti saya sudah melinggih, jangan saya diminta muput jika bantennya bau. Saya mudah bersin.”
Umat Hindu di Bali, terutama di pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak banyak mendalami kitab-kitab agama, seringkali terjebak pada pola takut salah dalam mengha¬turkan banten. Takut tidak komplit, takut kurang ini atau kurang itu. Kalau salah, nanti Tuhan memberikan kutukan. Ida Bethara dan Bethara Kawitan juga memberikan kutukan atau setidak-tidaknya memberikan “sakit” sebagai sinyal dari adanya kesalahan itu. Istilah di pedesaan seperti “kepongor” atau “kepanesan” adalah suatu kepercayaan bahwa para leluhur kita — bahkan dalam tingkat tertinggi Hyang Widhi — menjatuhkan hukuman kepada umatnya karena melakukan tindakan yang salah atau kurang lengkap dalam melaksanakan upacara. Tuhan dan Bethara lebih sebagai penghukum, bukan sebagai Yang Maha Kasih, Yang Maha Pengampun.
Karena itu, supaya tidak salah, maka upacara ritual pun harus lengkap. Lengkap versi siapa? Lengkap menurut tradisi yang sudah turun-menurun, tanpa peduli lagi apakah tradisi itu benar atau sudah salah dari sononya. Karena itulah tidak sedikit orang yang menga¬dakan upacara ngaben sampai menjual harta warisan, agar pelaksanaan ritualnya disebut lengkap. Pokoknya demi upacara lengkap itu, pendidikan anaknya bisa dikorbankan, tanah produktif untuk kehidupan sehari-hari bisa digadaikan. Uang SPP anak dikorbankan karena harus membuat bebangkit. Padahal tanpa bebangkit pun yadnya bisa jalan.
Upacara Pitra Yadnya yang lengkap itu juga dikaitkan dengan kesenian, baik berupa bunyi-bunyian maupun pementasan tari. Ngaben tanpa bunyi angklung terasa begitu asing, kata orang.di kampung saya Tapi, kenapa tidak membunyikan gamelan angklung dari kaset lewat pengeras suara saja? Ini kan menghemat ratusan ribu.
Belum lagi tradisi gamelan gambang, yang konon satu-satunya gamelan yang bisa mengantarkan “pitara” ke sorga. Tanpa gamelan itu, tak ada jalan menuju sorga. Lalu lesung yang ditumbuk itu (ngeluntang), yang akan menyambut arwah-arwah yang akan diupacarai. Langkanya lesung penumbuk padi akan membuat kelabakan orang untuk mencari di mana ada lesung yang bisa disewa. Di sini saya selalu katakan, tradisi apapun yang ada di Bali selalu mengacu kepada tradisi agraris. Sekarang zaman global, padi tak perlu ditumbuk pakai lesung, ada mesin slip, kenapa ngaben tidak membunyikan mesin slip saja? Kan orang yang diaben belum tentu pula tahu lesung karena sudah hidup di zaman global.
Itu baru di tingkat bunyi-bunyian. Kemudian di tingkat pe¬mentasan, ada kepercayaan harus meminta tirtha dalang wayang kulit dengan lakon tertentu, yang ada kaitannya dengan sorga atau mencari air suci untuk mengantarkan roh ke surga. Lakon yang terkenal dalam kaitan ini adalah Biwa Swarga, Dewa Ruci dan berbagai variasinya yang tentu saja tak dikenal dalam ephos Mahabharata yang asli.
Pernah saya menanyakan kepada seorang dalang, kenapa ia mementaskan cerita yang aneh, yaitu Anoman ke sorga mencari tirtha. Bukan Bima sebagaimana lazimnya. Jawabannya enteng saja: “Saya tak biasa mendalang dengan lakon Mahabharata, saya spesialis Ramayana.” Pentas wayang kulit di Bali di masa lalu memang ada dua kubu: Mahabharata dan Ramayana yang dibedakan oleh gamelan pengiringnya. Nah ini kan lagi-lagi tradisi yang sudah ditinggalkan. Sekarang dalang Cenk-Blong (Wayan Nardayana), mau pentas Mahabharata atau Ramayana tetap saja pakai gamelan semar pegulingan. Tradisi tak harus dipertahankan, tetapi sastra agama harus dipertahankan.
Lalu, apa kaitannya pentas wayang kulit ini dengan upacara Pitra Yadnya? “Sebenarnya tak ada, karena tirtha dalang itu sendiri bisa diminta tanpa harus ada pementasan,” kata sang dalang. Ini benar sekali, bahkan tirtha dari Sang Dalang itu sendiri juga bukan keharusan. Kalau Pandita Mpu masih tergantung pada tirtha dalang untuk muput ngaben, wah, jangan mediksa dululah. Ini yang sering saya katakan.
Kesenian ini hanyalah embel-embel. Di Puri Gianyar kalau ada upacara pitra yadnya, biasanya dipentaskan tari gambuh, suatu hal yang tentu sulit untuk “ditiru” di daerah lain yang tidak mengenal tari klasik itu. Akhirnya kembali kepada masalah “perasaan batin” yang punya upacara, sejauh mana ia merasa sudah melak¬sanakan ritual itu secara lengkap. Kesenian itu sama saja akhirnya dengan banten, apakah kita puas dengan membuat yang sederhana kalau memang mampunya seperti itu? Atau kita memaksakan diri, padahal kita jelas tidak mampu?
Belakangan ini, dalam hal ritual di lingkungan keluarga, saya selalu mengatakan jangan menghambur-hamburkan yang tak perlu. Tetapi juga dipertimbangkan bagaimana kita bermasyarakat. Menyelenggarakan yadnya adalah juga menunjukkan cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau dana ada, kenapa harus memutar kaset yang berisi kidung dan gamelan, kenapa tidak mengundang sekehe shanti. Kenapa tidak mengundang sekehe topeng, sekehe angklung, dan sebagainya. Jangan dengan alasan sederhana, kita melakukan yadnya dengan “sepi ing demit” (sepi karena pelit).
Ada kawan saya dari Kalimantan yang heran melihat yadnya yang tergolong “megah” ketika anak saya potong gigi. “Pak Putu tidak konsisten, selalu menganjurkan yadnya yang sederhana, kok sekarang mewah, ada topeng, ada gamelan gong, ada angklung, ada gender ada banyak penari, undangannya pun banyak.,” katanya. Jawaban saya: “Ini karena Hyang Widhi suweca dengan saya. Saya diizinkan punya gamelan gong, lalu disumbang aklung oleh banjar, topeng punya sendiri, penari anak-anak ashram. Kalau saya beryadnya dengan sepi-sepi, kapan saya bisa menjamu warga desa saya sendiri?”
Lagi pula, saat saya beryadnya itu, saya masih hidup dengan “gaya Jakarta” dengan sobat-sobat yang juga datang dari Jakarta. Menjamu 200-an warga desa biayanya sama dengan makan sepuluh orang di hotel berbintang. Nanggap wayang kulit di Bali jauh lebih murah dari mendatangkan seorang MC kalau membuat acara di Jakarta. Jika ukurannya di bawa ke sini, tak ada alasan untuk berpelit-pelit dengan dalih “upacara agama terlalu mahal”. Justru kita disebut kikir atau pelit, beryadnya sederhana tetapi tiap malam mabuk-mabukan di kafe. Tentu harus tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, jangan membuat yadnya yang mewah saat gagal panen kopi, misalnya,
Begitu sebaliknya, kalau kita hidup serba kekurangan, untuk makan sehari-hari saja masih berjuang keras, untuk apakah kemewahan ritual yang hanya meneruskan tradisi lama itu? Tingkatan yadnya bisa diturunkan, kesenian tak menjadi keharusan, ritual bisa dibuat dengan murah. Jika perlu, ya, gabung saja menyelenggarakan yadnya seperti yang dilakukan oleh Semeton di Sekretariat Pasek ini. Ritual jangan sampai memberatkan.***
Kamis, Mei 07, 2009
Pemimpin
Ada kebiasaan baru yang tanpa saya tahu sejak kapan mulai. Yakni, setiap malam sebelum tidur, saya menganalisa informasi yang saya terima hari itu. Caranya sangat sederhana dengan mengajukan pertanyaan dalam hati: percaya akan kebenarannya atau tidak. Tentu ada alasannya, namun lebih banyak alasan itu berdasarkan wawasan saya yang dangkal. Maklumlah, saya bukan pengamat, juga bukan peramal.
Supaya lebih jelas, saya beri contoh. Saya tak percaya kalau Ibu Megawati akan mundur dari pencalonan presiden untuk memberi kesempatan pada kader-kader yang lebih muda. Ada kabar yang disampaikan oleh teman-teman (bukan kabar burung karena teman saya itu manusia), kalau Ibu Mega “mengalah” sehingga koalisi besar akan memunculkan calon presiden baru. Saya percaya Ibu Mega tetap akan bertarung, meski pun survey menyebutnya kalah.
Contoh lain, saya tak percaya kalau Soetrisno Bachir (SB) akan berani mengkhianati Amien Rais, seniornya. Pengkhianatan itu, misalnya, dengan menerima bujukan Prabowo untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden, padahal Mas Amien sudah jelas, gabung ke SBY. Analisa saya, ketika SB sedang merintis usahanya di Pekalongan dan saya masih jadi “gelandangan” di Jawa Tengah, saya mengenal SB orang yang santun. Apalagi Ibundanya menasehati, jangan berseberangan dengan Mas Amien. Apakah kesantunan ini kalah oleh ego kekuasaan?
Contoh lain lagi, saya tak bisa percaya kalau SBY akan mengandeng kader PKS sebagai wakilnya. SBY akan kehilangan pemilih nasionalis, pluralis, yang menjunjung kebhinekaan, karena kesan yang ditampilkan PKS adalah menegakkan syariat Islam. Analisa saya, SBY bisa terjungkal kalau salah pilih wakil.
Tentu saya minta maaf jika alasan dan analisa saya memang dangkal. Terbukti sering salah. Misalnya, suatu malam saya pernah tidak percaya kalau Wiranto mau menjadi calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla. Jendral kok jadi wakil seorang pengusaha. Nah, ternyata sang jendral dengan tegas telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden. Meski saya salah, saya sungguh bersyukur dan merasa “bersemangat” untuk ikut Pemilihan Presiden (ketika Pemilu Legislatif saya “kurang semangat”). Kenapa? Karena tiba-tiba saya ingat, pada 1994, ketika Wiranto menjabat Kastaf Kodam Jaya, beliau memanggil saya pukul enam pagi untuk mendiskusikan “bagaimana mempertahankan NKRI”. Saat itu saya “terlanjur” menjabat Ketua Umum Forum Cendekiawan Hindu dan kebetulan situasi politik ketika itu lagi hangat dengan “sekat-sekat primordial”.
Sebagai orang yang suka keluyuran di Nusantara (kalau keluar negeri tak punya ongkos dan takut kena flu babi), keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi dambaan saya. Dalam bahasa politisi “ini harga mati”, dalam bahasa almarhum Gombloh “merah darahku, putih hatiku”. Artinya, koalisi apapun yang dilahirkan partai politik, koalisi besar atau kecil, bangsa yang bhineka tunggal ika harus tetap utuh, atau mengutip lagu Coklat: “merah putih teruslah berkibar… “
Saya percaya tentang keutuhan Indonesia yang bhineka itu. Namun, tetap tergantung figur yang memimpin negeri ini. Masalahnya tidak banyak stock pemimpin yang, kalau dadanya dibelah, ada merah putih di sana. Apalagi ditambah bermoral dalam arti luas. Contoh kabar terakhir, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka pembunuhan, hanya karena cewek. Saya sudah membulatkan hati untuk tidak mempercayai kabar ini, supaya ada pemimpin yang masih saya hormati. Tapi kan saya sering salah. Sangat memprihatinkan.
Koraan Tempo 3 Mei 2009)