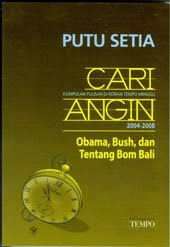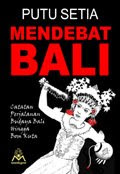Sejumlah ulama Islam di Mesir melahirkan fatwa tentang pelarangan yoga bagi kaum Muslim. Hal ini diikuti oleh Malaysia yang mengharamkan bagi umat Muslim untuk ikut yoga. Di Indonesia, meski pun tak begitu muncul di permukaan, ada desakah agar Majelis Ulama Islam (MUI) melakukan pengkajian terhadap yoga dan kalau memang bertentangan dengan ajaran Islam supaya MUI mengambil sikap yang tegas.
Kami, penganut Hindu, tentu menghormati sikap mereka. Tugas majelis ulama memang harus melindungi umatnya dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Majelis ulama harus menjadi benteng dari kemurnian ajaran agama dari berbagai virus lain yang bisa memperlemah ajaran itu sendiri. Agama sudah mempunyai patokan dan ukuran yang khas dan memang harus diikuti oleh penganutnya. Patokan dan ukuran itu dasarnya adalah kitab suci yang dipakai masing-masing agama.
Artinya, apakah saudara kita umat Islam mengharamkan yoga atau tidak, itu bukan urusan umat Hindu. Itu urusan umat Islam sendiri. Umat Hindu tak perlu ikut campur, apalagi dibuat resah. Juga jangan sekali-sekali punya perasaan kecewa apalagi lalu muncul sikap marah atau protes, kenapa yoga diharamkan. Masing-masing agama punya koridor sendiri, punya “rumah” sendiri. Sepanjang hal itu tidak mengganggu urusan umat lain, tak ada alasan apa pun untuk menggugatnya. Sekali lagi haram atau halal yoga bagi umat Islam itu adalah urusan saudara kita umat Muslim yang kita cintai.
Yoga memang dekat sekali dengan Agama Hindu karena yoga lahir di kalangan komunitas Hindu. Dan yoga diperkenalkan lalu diajarkan secara turun temurun oleh para Rsi dan para murid-muridnya kemudian menyebarkan yoga ke seluruh dunia.
Namun yoga sejatinya jauh dari ritual agama. Yoga murni olahraga, baik yang mengatur masalah phisik dengan berbagai gerakan maupun mengatur pernafasan dengan berbagai teknik. Antara gerakan phisik dan pernafasan ini melahirkan satu keseimbangan yang menyehatkan tubuh.
Bahwa yoga diawali dengan doa, itu benar sekali. Namun doa dalam hal ini bukanlah ritual agama, tetapi lebih pada “penganjali” (istilah Hindu) atau “salam” (istilah Islam yang sudah umum) atau sesungguhnya “permohonan agar semuanya berlangsung selamat”. Semua agama mengajarkan untuk melafalkan “panganjali” atau ”salam” sebelum melakukan kegiatan apa pun. Umat Hindu biasa mengucapkan Om Awignam Astu sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Kalau kegiatan itu di depan banyak orang, misalnya, menyampaikan pidato, tentu didahului oleh Om Swastyatu. Jadi, Om Swastyastu adalah “penganjali” untuk ditujukan kepada sesama manusia agar diberkati oleh Tuhan, Om Awignam Astu adalah “penganjali” kepada Tuhan agar apa yang akan dikerjakan diberi keselamatan atau anugerah.
Dalam contoh yang sangat nyata sekali kita misalnya mendengar umat Islam mengucapkan “Bismilah….” dan seterusnya, sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Jika kegiatan itu misalnya membacakan pidato di depan umum (supaya contohnya sama dengan di atas) maka didahului dengan “Assalamalaikum….” dan seterusnya. Padahal pidato-pidato itu tidak disampaikan dalam kegiatan ritual agama, tetapi rapat kerja partai, atau arisan, misalnya.
Dalam praktek yoga umumnya memang didahului oleh doa atau mengucapkan mantram. Karena yoga diperkenalkan pertama-tama pada komunitas Hindu, sudah tentu doanya itu dalam doa Hindu. Dan tujuan doa itu juga meminta “perlindungan” dari Tuhan Hyang Widhi agar diberi keselamatan, lalu “penghormatan” kepada para Rsi penemu yoga, sebagai guru yang telah menularkan ilmu ini secara turun-temurun (parampara).
Nah, kalau dalam perkembangan zaman global ini yoga tidak hanya diikuti oleh orang Hindu tetapi juga diikuti oleh pemeluk agama lain, bukankah doa itu bisa disampaikan dalam tradisi masing-masing agama? Toh tidak ada kewajiban mengucapkan doa itu secara keras, cukup berbisik kecil atau bahkan cukup di dalam hati saja. Jadi, sesungguhnya dalam mengawali yoga sebagai suatu teknik olahraga tubuh dan pernafasan, doa pembuka itu bisa disampaikan dengan doa agama masing-masing pengikutnya.
Saya pernah ikut dan mendalami teknik Meditasi Usadha yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Merta Ada. Beliau penganut Buddha yang taat. Ketika mengawali meditasi itu selalu ada ruang untuk menyampaikan doa, dan selalu instruksinya adalah: “Berdoa sesuai keyakinan masing-masing”. Bukan berdoa dalam agama Buddha. Hanya pada akhir meditasi, instruktur memberikan “doa” yang sangat umum dan universal, juga dalam bahasa Indonesia, bunyinya: “Semoga semua makhluk berbahagia”, dan itu diucapkan tiga kali. Tak ada yang keberatan dengan “doa penutup“ yang universal ini. Namun, karena saya tak paham benar apa kriteria makhluk itu (apakah bakteri, kuman-kuman dan semua makluk jahat harus didoakan supaya bahagia juga), maka saya seringkali menutup acara meditasi itu dengan doa Hindu, sesuai agama yang saya anut. Jadi saya mengucapkan “Om Shanti, Shanti, Shanti, Om” sebagai pengganti “Semua makhluk berbahagia.”
Dalam kegiatan Meditasi Angka, suatu meditasi yang diperkenalkan oleh Made Darmayasa di Indonesia, doa pembuka itu juga selalu ada. Jika meditasi itu hanya diikuti oleh penganut Hindu, apalagi dilaksanakan di senter Meditasi Angka di Padanggalak, Bali, doa itu panjang. Ada pemujaan untuk banyak dewa. Namun, jika Meditasi Angka dilakukan di hotel berbintang di Jakarta dan pesertanya dari berbagai agama, doa itu sangat universal dan kalau pun disertai doa khusus yang sesuai dengan agama peserta meditasi, itu dilakukan di dalam hati.
Kembali ke yoga, diharamkan atau dihalalkan untuk kalangan Muslim, adalah sepenuhnya urusan mereka. Tentu umat Hindu tak mengharapkan Parisada (majelis agama Hindu) suatu saat melarang umat Hindu melakukan senam jantung sehat atau bermain karate, kungfu bahkan sepakbola, hanya karena olahraga itu diciptakan oleh orang yang bukan penganut Hindu. Olahraga, menurut saya, sepertinya jauh dari wilayah agama.
(Versi lain dari Editorial Majalah Hindu Raditya edisi Januari 2009)
Selengkapnya