Saya menyesal tidak mengikuti debat calon presiden, Kamis malam lalu. Ada acara yang tak memungkinkan menyetel televisi. Namun, teman saya mengaku lebih menyesal lagi karena menonton debat itu sampai selesai. “Tak ada perdebatannya, saya hampir mengantuk,” katanya.
“Anda jangan seperti pengamat politik. Begini salah, begitu salah. Kalau calon presiden saling melempar argumentasi, dikatakan saling serang dan saling sindir. Kalau rukun, dibilang adem ayem. Anda mau apa sih?”
Ucapan saya itu mengagetkan teman saya. “Tapi ini betul-betul bukan debat, ini hanya giliran pidato, bahkan saling dukung. Ganti dong acaranya menjadi ‘kampanye bareng’ atau apalah,” katanya.
Saya jelaskan, kultur Indonesia memang begitu, lebih-lebih para elitnya. Beraninya cuma di belakang, bukan berhadap-hadapan. Kalau Mega ada di Bekasi, ia berani menyerang SBY karena yang diserang tidak ada. Kalau Jusuf Kalla di Aceh, ia berani menyerang SBY yang ada di Malang. Sebaliknya, SBY pun ringan menyindir Mega atau JK, ketika berada di Malang. Jika ketiganya bertemu, semuanya akan rikuh. SBY kan pernah jadi bawahan Mega, JK masih menjadi wakilnya SBY. Kualat bertengkar dengan mantan bos. Adapun Mega, kalau sudah dipuji oleh keduanya, ya, tak bisa marah lagi, apalagi beliau seorang Ibu, simbol keramahan. Justru kalau terjadi perdebatan, ini melanggar petuah orangtua; “nak, jangan bertengkar di tempat ramai.” Ini budaya Nusantara, khususnya Jawa.
“Debat Barrack Obama dengan John Mc Cain kok bisa menarik? Padahal saya cuma baca teks terjemahannya,” kata teman saya.
“Itu karena tradisinya beda,” kata saya. Di Amerika Serikat, budaya debat adalah budaya keilmuan, pakai otak. Yang mendengar juga menggunakan otak. Selesai berdebat mereka salaman, penontonnya juga bisa pulang bareng. Di sini, perdebatan berarti ada ketidak-sepahaman dan itu bisa melahirkan dendam, bisa tak bicara dalam waktu lama, apalagi salaman. Perdebatan nyaris berarti pertengkaran. Penontonnya juga begitu, bisa saling menggebuk mobil saat pulang. Peserta kuis siaran langsung di televisi saja bisa berantem usai acara karena tak senang disindir.
Pengamat kita itu aneh kalau ingin menonton debat yang bermutu, ini belum zamannya. Misalnya, ada calon presiden yang mengumbar isu ekonomi kerakyatan. Lalu, calon presiden yang lain menanyakan, apakah mereka pernah membeli baju di Pasar Ciputat yang berlumpur kalau hujan itu? Jangankan beli baju, kacamata saja membelinya di mal. Kalau sakit bukannya ke Puskesmas, malah ke Singapura. Tim suksesnya juga begitu. Neolib diserang habis-habisan, tapi membeli dasi di Mal Ambasador, bukan di Pasar Cipete. Semua calon itu bermasalah soal “kerakyatan”, semuanya tak tahu isi hati “wong cilik”.
“Anda kenal Siti Musdah Mulia?” Teman saya bengong. Dia itu dosen, doktor, juga ibu rumah tangga. Suatu kali saat acara Indonesian Conference on Religion and Peace – beliau ketuanya– dia bilang ke saya: tak pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan. Padahal dia tak pernah ngomong ekonomi kerakyatan. Beda dengan tetangga saya yang memasang spanduk “Jangan Pilih Capres Neolib”, tapi membeli buku tulis untuk anaknya di Carrefour. Katanya, anaknya jijik dikerubungi lalat pasar.
Kasihan juga melihat teman saya melongo dengan “propaganda” saya. Saya hibur: “Sudahlah, bagus Anda menonton debat sampai selesai dan tak mematikan tv.” Dia menjawab kalem: “Kalau tv saya matikan, saya bisa ketiduran. Debat Kamis malam itu kan menunggu Piala Konfederasi, saya gila bola.”
(Koran Tempo Minggu 21 Juni 2009)
Jumat, Juli 03, 2009
Debat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
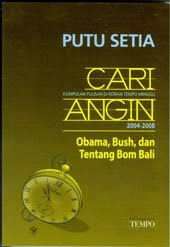


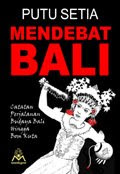

Tidak ada komentar:
Posting Komentar