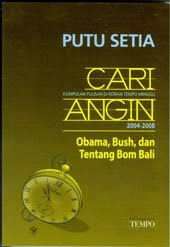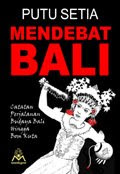Selesai seminar yang mengulas masalah moral, seseorang menghampiri saya dan langsung bicara: “Saya ingin tanggapan. Saya mengamati banyak sekali orang bodoh di sekitar kita, apakah ini juga termasuk ciri kegelapan dalam era Kali Yuga? Atau mungkin saya yang bodoh?”
Karena saya sudah capek bicara dalam seminar, saya menanggapi seadanya: “Apa contohnya?”
Karena saya sudah capek bicara dalam seminar, saya menanggapi seadanya: “Apa contohnya?”
Dia lalu menyebut kasus demo anarkis di Medan yang menyebabkan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat tewas. Pemekaran wilayah, menurut dia, hanyalah pintu masuk untuk berebut jabatan. Di mana-mana, pencetus ide pemekaran provinsi, kalau berhasil, punya kesempatan besar menjadi gubernur, pencetus pemekaran kabupaten menjadi bupati. Teman-temannya menjadi pejabat semua, minimal anggota dewan. Tak dipikirkan, berapa anggaran yang harus disediakan untuk mengisi jabatan dan fasilitas itu dan apakah sebanding dengan apa yang diperoleh rakyat akibat pemekaran. Usul pemekaran tetap ngotot diperjuangkan. Nah, ketika terjadi kebrutalan dan korban jatuh, bukan jabatan gubernur yang datang, tetapi “jabatan” sebagai tahanan. Ini kan bodoh.
“Ada contoh lain?” Tanya saya memotong. Dia bicara lagi: “Ya, kenapa menyalurkan pendapat harus lewat aksi brutal? Mahasiswa menuntut pemerintahan yang bersih, pagar kantor gubernur diobrak-abrik. Masa menuntut harga-harga turun, fasilitas umum di jalanan dirobohkan. Buruh menuntut gaji naik, jalur perekonomian penting diblokir. Mereka merusak dan membebani keuangan Negara dengan dalih memperbaiki keadaan. Ini kan pekerjaan orang bodoh.”
“Maksud saya, contoh versi lain, saya bosan dengan itu,” kata saya lagi. Dia berhenti sejenak lalu bicara: “Sekarang orang berebut ingin jadi wakil rakyat di daerah. Uang yang dihabiskan bermilyar rupiah untuk membuat baliho, memberi sumbangan, kenduri dan macam-macam. Padahal, kalau dia sudah jadi wakil rakyat, gajinya sekitar Rp 10 juta, katakan naik jadi Rp 20 juta. Lima tahun menjabat kan baru dapat Rp1,2 milyar. Bagaimana mengembalikan modal? Belum dipotong sumbangan partai dan untuk makan. Kenapa sebodoh itu?”
“Wah, contohnya klise. Ada yang lain?” kata saya. Tak butuh waktu lama, dia bicara: “Ibu Mega memasang iklan besar-besar yang menyalahkan pemerintah. Ini salah, itu melanggar janji, itu memutar fakta. Apa rakyat semua bodoh? Ketika Ibu Mega menjabat, memang nya tak ada yang salah? Rakyat berpaling, pasti karena ada sesuatu yang salah. Kalau cerdas, semestinya membuat iklan yang simpatik, seperti ikklannya partai lain.”
“Stop, Anda kok sinis dengan Ibu Mega. Saya tak mau contoh itu,” saya memotong. Dia cekatan sekali melanjutkan: “Kalau begitu soal kegundahan Presiden SBY, rumor ABS. ABS kan bisa macam-macam, bisa Asal Bukan Sutiyoso, Asal Bukan Sultan, Asal Bukan Surya Paloh, Asal Bukan Soekarno Putri, Asal Bukan Sontoloyo. Yang saya harapkan, Pak SBY bijaksana sehingga tak usah menanggapi hal-hal yang kecil. Tenang sajalah, jangan panik.”
“Itu contohnya terlalu tinggi,” kata saya. “Oke,” kata dia cepat-cepat, “ada ribuan orang mendatangi dukun tiban yang baru berumur sepuluh tahun, semuanya ingin kesembuhan instan. Dinas Kesehatan jatuh wibawanya dan tak ada orang cerdas yang memberikan pandangan kalau semuanya itu hanya sugesti…”
“Stop, itu menyangkut keyakinan, tak bisa diperdebatkan, ada contoh lain?” kata saya. Dia berpaling: “Tadi saya pikir saya yang bodoh, ternyata Anda jauh lebih bodoh, tak satu pun pertanyaan saya Anda tanggapi.” Orang itu pergi, saya sampai lupa menanyakan identitasnya.
(Diambil dari Koran Tempo, 8 Februari 2009)