Departemen Kesehatan sibuk mengurusi Pemilu. Bukan menyiapkan petugas yang menangani korban kampanye terbuka, tetapi mempersiapkan perawatan bagi mereka yang kena gangguan jiwa. Semua rumah sakit jiwa di Nusantara berstatus siaga satu begitu pencontrengan selesai.
Korban Pemilu bukan lagi rakyat, tetapi para calon legislator. Jenis penyakitnya bukan luka, tetapi jiwanya terguncang. Makanya Departemen Kesehatan tak menyiapkan Puskesmas atau rumah sakit umum, melainkan rumah sakit jiwa. Dalam bahasa rakyat, korban yang masuk ke rumah sakit ini adalah mereka yang tidak waras.
Karena korbannya orang berpendidikan – sebagian besar calon legislator memamerkan gelar akademiknya meski pun ngomongnya belepotan – kamar-kamar yang disiapkan di rumah sakit jiwa tergolong baik. Bahkan di Semarang disiapkan kelas VIP. Di daerah lain, seperti Magelang, Mataram atau Bangli (Bali) cukup kamar biasa.
Awalnya saya kira langkah ini mengada-ada. Setelah mendengarkan uraian pakar ilmu kesehatan jiwa seperti Dr. Luh Suryani di Bali, saya baru percaya bahwa ini soal serius. Luh Suryani dan lembaga swadaya yang dipimpinnya bahkan sudah menyiapkan diri sebelum Departemen Kesehatan sibuk.
Inilah Pemilu yang menghasilkan “orang gila”. Yang tidak terpilih masuk rumah sakit jiwa atau jadi beban sosial di masyarakat karena ulahnya pasti menyebalkan, yang terpilih kelihatan seperti waras tetapi jiwanya terganggu. Karena yang dipikirkannya adalah bagaimana bisa duduk aman sebagai wakil rakyat selama lima tahun sembari mendapatkan proyek-proyek berduit di luar gaji resmi. Jiwanya mudah labil begitu ada yang mempersoalkan kinerjanya.
Jika kita rajin mengamati para calon legislator, entah itu melihat bagaimana mereka tampil di baliho, tampil di iklan televisi lokal mapun radio, dan lebih-lebih lagi melihat ulahnya di saat kampanye, sebenarnya sudah banyak yang “terganggu jiwanya”. Mereka tak bisa membedakan antara harapan yang bisa diperjuangkan, dan khayalan yang hanya mimpi. Umumnya mereka membeo, begitu kata “perubahan” laku, semuanya bicara perubahan. Ini mencerminkan bahwa mereka sebenarnya tak menguasai apa-apa, hanya mengumbar slogan yang mereka sendiri tak memahami arti sebenarnya. Ada yang bergaya bak pahlawan yang ditunggu-tunggu, tapi dia lupa jejak langkahnya sudah terekam buruk di masyarakat. Orang tak bisa berubah drastis dalam sekejap – atau karena ada Pemilu. Hanya penari topeng yang bisa berubah total wataknya begitu topengnya diganti.
Gangguan jiwa ini bisa jadi karena sistem dan aturan Pemilu yang berubah. Orang bebas mendirikan partai – atas nama konstitusi yang tak boleh membatasi hak orang membentuk perserikatan. Dalam kebebasan, orang-orang yang jiwanya terganggu itu, tentu tak mengenal malu. Sudah nyata partainya tak mendapat dukungan, tetap dipaksakan ikut Pemilu. Dan calon legislator yang dimunculkan pun juga labil jiwanya.
Adapun partai besar, tidak memiliki cara rekrutmen kader yang benar dan sering pimpinan partai itu bersikap “membela yang bayar” selain “membela keluarga”. Nomor urut tidak didasarkan pada kemampuan kader, tetapi pada yang “bayar” dan “keluarga”. Ketika mendadak sistem berubah dan nomor urut tidak menentukan kemenangan seorang calon, para pemegang nomor besar mendapat angin untuk menantang. “Rasakan sekarang, siapa yang didukung rakyat,” mungkin begitu sumpahnya. Calon yang bernomor urut kecil, yang jiwanya sudah goncang karena harus bayar dan melakukan “penjilatan”, tiba-tiba harus berjuang keras pula. Semuanya kemudian mencari akal bagaimana cara agar bisa mendapatkan suara melebihi yang lain, termasuk cara yang tak masuk akal (bagi orang normal) seperti menjual harta warisan. Bagaimana tidak edan kalau hasilnya gagal?
Sistem dan aturan Pemilu perlu direformasi agar mendapatkan wakil rakyat yang jiwanya tidak terganggu. Peserta Pemilu mesti dikurangi, hanya partai yang mendapatkan dukungan signifikan. Caranya mudah kalau berani, yakni bubarkan partai yang tak mendapatkan suara minimal 10 persen. Ini contoh jika kita menghendaki maksimal ada 10 partai, syukur kurang dari itu. Partai sedikit namun sehat, persaingan nomor urut calon ditentukan berdasarkan “uji kelayakan” dan betul-betul yang paling pantas menjadi wakil rakyat. Pemenang kembalikan ke nomor urut, biarkan rakyat hanya mencoblos atau mencontreng lambang partai, tak perlu repot memelototi nama calon.
Ini artinya, kita kembali ke masa lalu. Tetapi yang “kembali” hanya sistem, pelaksanaan Pemilu tentu lebih demokratis, cerdas, berkualitas, termasuk slogan lama: jujur dan adil. Masalahnya, pasti banyak elit politik yang tak setuju. Persyaratan 2,5 persen suara untuk sebuah partai “bisa selamat” saja, sudah mau digugat. Mereka berdalih: “Kita bertekad melakukan perubahan…”
Nah, makan itu perubahan.***
(Pernah dimuat di Koran Tempo, awal April 2009)
Selasa, April 07, 2009
Jiwa yang Guncang Pasca Pemilu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
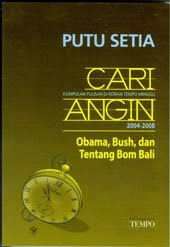


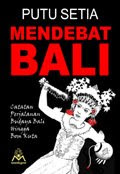

Tidak ada komentar:
Posting Komentar