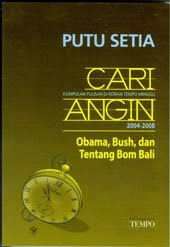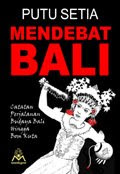Di tengah riuh gemuruh kampanye calon presiden, di antara ribuan kata diumbar para tim sukses, banyak yang mencemaskan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih tepatnya, bukan keberadaan Komisi –disebut begitu saja supaya singkat— itu yang dipersoalkan, tetapi ada upaya yang membuat Komisi makin busuk. “Memangnya mangga yang bisa busuk?” kata hati saya.
Namun, saya ikut cemas kalau benar ada upaya yang sistematis untuk memperlemah kerja Komisi. Berbagai cobaan dihadapi Komisi. Ibarat pepatah, makin tinggi pohon makin keras mendapat terjangan angin. Dan “terjangan angin” itu saya rasakan ketika Wakil Ketua Komisi Chandra M. Hamzah diperiksa polisi selama tujuh jam dalam kasus penyadapan telepon seluler Rhani, cewek yang jadi saksi kunci pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Diperiksa tujuh jam? Ini yang mencemaskan, lebih-lebih bagi mereka yang tak tahu lika-liku pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Banyak muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana tekniknya polisi memeriksa seorang “terperiksa” begitu lama? Apakah pertanyaan diajukan dengan begitu pelannya dan “terperiksa” menjawab dengan terbata-bata? Atau mungkin diselingi nonton tayangan gossip di televisi? Apalagi dalam kasus Chandra M. Hamzah ini pertanyaannya –semestinya- amat sederhana.
Dari sini muncullah kekhawatiran di masyarakat, sepertinya Chandra mau “dibidik”, jika tidak kenapa mesti berlama-lama diperiksa. Kalau Chandra sampai “kena bidik” dan kemudian menjadi “tersangka”, maka berkurang lagi pimpinan Komisi setelah Ketua Komisi (Antasari Azhar) dinyatakan nonaktif. “Di sinilah pembusukan itu,” kata seseorang, entah siapa.
Apa pentingnya dan siapa yang berkepentingan dengan “busuknya” Komisi? Oh, banyak. Para koruptor, baik yang sudah merasa akan diseret maupun yang masih gentayangan di tim sukses masing-masing calon presiden, berharap Komisi bukan saja “busuk” tetapi “lumpuh”. Ketika seorang anggota dewan yang terhormat berkoar-koar di televisi dalam kapasitas sebagai tim sukses calon presiden, seorang teman menelepon saya: “Lihat orang itu, dia kan disebut-sebut menerima cek saat memenangkan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia, kapan ditangkap ya?”
Masih ada puluhan teman anggota dewan itu yang seharusnya sudah dipanggil Komisi – atau langsung diperiksa tujuh jam dan ditangkap – jika saja semua pihak mendorong Komisi untuk lebih semangat. Jadi, ini dugaan beberapa teman dan saya setuju, anggota Dewan banyak yang sebenarnya ingin agar Komisi lumpuh, bukan hanya busuk. Bukti lainnya, rancangan undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga dibahas, padahal sebentar lagi anggota Dewan berganti.
Tapi, apakah kepolisian ingin juga Komisi itu “busuk”? Saya tak mau berkomentar, takut kena masalah dan nanti “diperiksa tujuh jam”. Saya hanya ingin mengatakan, memang asal-usul adanya Komisi itu adalah para penyidik – kepolisian dan kejaksaan—dianggap “kurang semangat” dalam memberantas korupsi di negeri ini, meski pun kedua penegak hukum ini punya wewenang menangkap koruptor dan sudah dijalankan. Kalau saja polisi dan jaksa bersemangat “maju tak gentar” memberantas korupsi tanpa melihat “ada bulu atau tidak”, tak akan ada Komisi, apalagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teorinya begitu, para hakim di Pengadilan Negeri sudah cukup menghukum koruptor.
Sayangnya, ketiga calon presiden, tak jelas betul apa sikapnya. Mereka bisa bilang, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan lebih cepat lebih baik untuk tegaknya ekonomi kerakyatan, tapi mau diapakan KPK ini?
(Koran Tempo Minggu 28 Juni 2009)
Jumat, Juli 03, 2009
KPK
Debat
Saya menyesal tidak mengikuti debat calon presiden, Kamis malam lalu. Ada acara yang tak memungkinkan menyetel televisi. Namun, teman saya mengaku lebih menyesal lagi karena menonton debat itu sampai selesai. “Tak ada perdebatannya, saya hampir mengantuk,” katanya.
“Anda jangan seperti pengamat politik. Begini salah, begitu salah. Kalau calon presiden saling melempar argumentasi, dikatakan saling serang dan saling sindir. Kalau rukun, dibilang adem ayem. Anda mau apa sih?”
Ucapan saya itu mengagetkan teman saya. “Tapi ini betul-betul bukan debat, ini hanya giliran pidato, bahkan saling dukung. Ganti dong acaranya menjadi ‘kampanye bareng’ atau apalah,” katanya.
Saya jelaskan, kultur Indonesia memang begitu, lebih-lebih para elitnya. Beraninya cuma di belakang, bukan berhadap-hadapan. Kalau Mega ada di Bekasi, ia berani menyerang SBY karena yang diserang tidak ada. Kalau Jusuf Kalla di Aceh, ia berani menyerang SBY yang ada di Malang. Sebaliknya, SBY pun ringan menyindir Mega atau JK, ketika berada di Malang. Jika ketiganya bertemu, semuanya akan rikuh. SBY kan pernah jadi bawahan Mega, JK masih menjadi wakilnya SBY. Kualat bertengkar dengan mantan bos. Adapun Mega, kalau sudah dipuji oleh keduanya, ya, tak bisa marah lagi, apalagi beliau seorang Ibu, simbol keramahan. Justru kalau terjadi perdebatan, ini melanggar petuah orangtua; “nak, jangan bertengkar di tempat ramai.” Ini budaya Nusantara, khususnya Jawa.
“Debat Barrack Obama dengan John Mc Cain kok bisa menarik? Padahal saya cuma baca teks terjemahannya,” kata teman saya.
“Itu karena tradisinya beda,” kata saya. Di Amerika Serikat, budaya debat adalah budaya keilmuan, pakai otak. Yang mendengar juga menggunakan otak. Selesai berdebat mereka salaman, penontonnya juga bisa pulang bareng. Di sini, perdebatan berarti ada ketidak-sepahaman dan itu bisa melahirkan dendam, bisa tak bicara dalam waktu lama, apalagi salaman. Perdebatan nyaris berarti pertengkaran. Penontonnya juga begitu, bisa saling menggebuk mobil saat pulang. Peserta kuis siaran langsung di televisi saja bisa berantem usai acara karena tak senang disindir.
Pengamat kita itu aneh kalau ingin menonton debat yang bermutu, ini belum zamannya. Misalnya, ada calon presiden yang mengumbar isu ekonomi kerakyatan. Lalu, calon presiden yang lain menanyakan, apakah mereka pernah membeli baju di Pasar Ciputat yang berlumpur kalau hujan itu? Jangankan beli baju, kacamata saja membelinya di mal. Kalau sakit bukannya ke Puskesmas, malah ke Singapura. Tim suksesnya juga begitu. Neolib diserang habis-habisan, tapi membeli dasi di Mal Ambasador, bukan di Pasar Cipete. Semua calon itu bermasalah soal “kerakyatan”, semuanya tak tahu isi hati “wong cilik”.
“Anda kenal Siti Musdah Mulia?” Teman saya bengong. Dia itu dosen, doktor, juga ibu rumah tangga. Suatu kali saat acara Indonesian Conference on Religion and Peace – beliau ketuanya– dia bilang ke saya: tak pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan. Padahal dia tak pernah ngomong ekonomi kerakyatan. Beda dengan tetangga saya yang memasang spanduk “Jangan Pilih Capres Neolib”, tapi membeli buku tulis untuk anaknya di Carrefour. Katanya, anaknya jijik dikerubungi lalat pasar.
Kasihan juga melihat teman saya melongo dengan “propaganda” saya. Saya hibur: “Sudahlah, bagus Anda menonton debat sampai selesai dan tak mematikan tv.” Dia menjawab kalem: “Kalau tv saya matikan, saya bisa ketiduran. Debat Kamis malam itu kan menunggu Piala Konfederasi, saya gila bola.”
(Koran Tempo Minggu 21 Juni 2009)
Prita
Di ruangan komputer sebuah sekolah menengah pertama, Ibu Guru menanyakan kepada anak didiknya: "Siapa di antara kalian yang senang mengirim e-mail menceritakan orang lain? Ayo, ngaku!"
Murid usia belasan tahun ini saling toleh sebelum sembilan orang mengacungkan tangan. Bu Guru menunjuk: "Ayo Putri, beri contoh e-mail-mu dan siapa yang kau kirimi e-mail itu." Putri tenang saja. "Bunyinya begini, Bu Guru: hai teman-teman, hati-hati dengan Baskoro, dia jahat, suka mencuri permenku. E-mail saya kirim ke sahabat kelompok dua, tujuh penerima."
Bu Guru lalu mengacungkan koran yang sejak tadi dipegangnya. "Anak-anak, menulis e-mail seperti itu sekarang berbahaya. Kalau Baskoro atau keluarganya mengadukan Putri ke polisi, Putri bisa dipenjara enam tahun dan membayar denda satu miliar. Undang-undangnya begitu, Putri mencemarkan nama baik orang lewat Internet, di koran ini ada beritanya," ujar Bu Guru. Anak didik yang sebelumnya ceria itu serentak melongo, Putri bahkan pucat mukanya.
Kisah di atas setengah fiksi. Yang fiksi dialog-dialognya, karena Luh Putri Devi, keponakan saya dari garis ibu, tak menceritakan dengan detail suasana itu. Setengahnya lagi benar, Ibu Guru di lab komputer sekolah favorit itu meminta anak didiknya berhati-hati menulis e-mail, sambil mengulas kasus Prita Mulyasari di Tangerang. Putri jadi trauma. "Sekarang takut banget deh, Paman, nggak mau lagi main Internet," katanya.
Prita, konon, juga trauma. Tak disangka, curahan hati kepada sepuluh temannya, perihal pengalaman ia dirawat di RS Omni Tangerang, akan berbuntut penjara. Bagaimana e-mail kepada sepuluh "teman pribadi" itu menyebar sampai dibaca pihak rumah sakit tentulah tak sulit dilacak. Bisa dengan teknik sederhana, misalnya, salah satu dari sepuluh orang ini meneruskan ke "teman lain", lalu tersebar ke mana-mana. Atau e-mail itu "bocor", sesuatu yang mudah terjadi di dunia maya Internet.
Prita tak membayangkan masuk penjara hanya karena menulis e-mail. Saya pun tak membayangkan juga karena, berdasarkan pengamatan saya di dunia Internet, "pencemaran nama" yang mirip itu setiap saat ada. Mailing list yang paling beradab, misalnya yang berlabel agama dengan menggunakan moderator sebagai penyaring, pun tak pernah lepas dari gosip yang menjurus pencemaran nama baik. Apalagi mailing list tanpa moderator, bahkan apalagi e-mail antarpribadi.
RS Omni sudah menggugat. Tapi lihatlah hasilnya. Tatkala Prita dipenjara, ada ratusan--jangan-jangan ribuan--posting yang mengecam rumah sakit itu dengan bahasa yang "jauh lebih mencemarkan". Bahkan muncul pemboikotan di cabang lain rumah sakit itu. Dukungan kepada Prita di Facebook mencapai ratusan ribu, setiap detik bertambah. Entah di blog dan mailing list--yang tak mungkin semua saya buka. Dunia maya, saat ini, menjadi kekuatan alternatif dalam membentuk opini publik. Kekuatan yang dahsyat.
Apa bisa kekuatan dahsyat itu diberangus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, terutama oleh Pasal 27 ayat 3 (delik pencemaran nama baik) dan Pasal 45 (denda Rp 1 miliar)? Berapa anggaran negara harus disediakan untuk membangun penjara yang menampung "pencemar nama baik" seperti Prita itu? Teramat konyol jika negeri ini sampai mendirikan Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pencemaran Nama Baik di Internet.
Lagi pula, mana batas pencemaran nama itu? Apakah "Say No to Megawati" atau "Boediono Mbahnya Neolib"--yang gentayangan di Internet--termasuk pencemaran nama baik? Perlu dirumuskan apa kriteria pencemaran itu agar jelas apakah Prita dan Putri perlu dibui atau tidak.
(Koran Tempo Minggu 14 Juni 2009)