Hingar bingar urusan politik tak terpengaruh oleh bulan puasa. Perilaku politisi dan calon politisi tetap sama: bagaimana merebut kursi pada Pemilu yang akan datang. Kalau memang harus bertengkar dengan kawan separtai, ya, apa boleh buat, dilakoni saja. Kalau tersingkir, cari partai lain. Ibarat judul film di masa lalu, “masih ada kereta yang akan lewat”.
Di Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, kader-kader Partai Hanura bertenggar memperebutkan nomor kecil dalam urutan calon legislatif. Papan nama, spanduk, baliho dihancurkan. Di beberapa kota di Jawa, Partai Demokrat bernasib sama. Bendera partai sendiri dibakar. Sang Guru Bangsa, Abdurrahman Wahid menyerukan untuk mengepung Komisi Pemilihan Umum di daerah-daerah karena selalu memihak kubu Mauhaimin. Partai lain, baik yang besar maupun yang menengah, pun riuh dengan pergolakan.
Yang unik – sekaligus menyebalkan – mereka yang mengaku “kader partai” ini sepertinya tak bisa hidup kalau berada di luar jalur legislatif. Mereka enggan menanggalkan status “wakil rakyat”, seolah-olah jabatan itu dibawanya sejak lahir, pemberian nenek-moyangnya. Lihat saja kenyataan yang ada. Karena tidak dicalonkan lagi di partainya, seorang kader lalu hengkang ke partai yang baru. Di situ namanya bertengger sebagai calon legislatif. Fenomena ini sepertinya merata di seluruh tanah air. Seorang peneliti mencatat, bertambah banyaknya partai yang ikut pemilu ternyata tidak banyak memunculkan nama-nama baru. Orangnya itu-itu saja, hanya ganti baju baru. Kalau pun ada “kader” baru, itu berada di urutan bawah, dan juga hanya sekadar memperpanjang daftar: ada mertua, istri, keponakan.
Lantas, apa yang bisa diharapkan dari Pemilu yang akan datang? Wajah-wajah yang duduk sebagai wakil rakyat nyaris akan sama. Mereka kembali reuni, kembali membicarakan komisi. Urusan mensejahtrakan rakyat, membela wong cilik, semuanya gombal. Saat ini saja, sidang-sidang dewan lebih banyak diisi kursi kosong. Penyebabnya ada dua: pertama, yang merasa tidak dicalonkan lagi, malas bersidang alias ngambek. Kedua, yang merasa dicalonkan lagi, sibuk bertengkar untuk mendapatkan nomor kecil.
Entah apa yang salah di Bumi Nusantara ini, teori dan prakteknya tak pernah akur. Teorinya: makin banyak partai, makin terbuka kesempatan untuk mencari pemimpin bangsa. Prakteknya: calon pemimpin tetap itu-itu saja. Tak ada wajah baru yang muncul. Ada anak-anak muda yang mau tampil, tapi tidak punya partai, aneh kan? Teorinya: makin banyak partai, makin bebas rakyat menyalurkan aspirasinya karena banyak pilihan. Prakteknya: rakyat semakin cuek, justru merasa terganggu oleh bendera partai yang berjubel merusak keindahan jalan. Teorinya: dengan multi partai, para aktivis yang selama ini vokal tetapi merasa tak terwakili dalam partai yang ada, bisa membuat partai baru. Prakteknya: mereka tetap ada “di luar sistem” dan partai baru didirikan oleh “kader” sempalan partai lama.
Barangkali teorinya “terlalu tinggi” tak sesuai dengan tingkat perilaku anak bangsa yang “masih rendah”. Bagaimana kalau dilabrak? Misalnya, jika sebuah partai hanya mendapat suara 5 persen, langsung dibubarkan dan semua “kadernya” di-blacklist, tak boleh menjadi pengurus partai apa pun lagi. Tentu partai akan mengecil, sepuluh sudah terlalu banyak, lima lebih bagus. Namun, gagasan ini pasti ditentang, karena orang Indonesia – di sini uniknya lagi – sadar konstitusi: ini melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat. Nah, “makan” itu kebebasan.
(Diambil dari Koran Tempo edisi Minggu 7 September 2008)
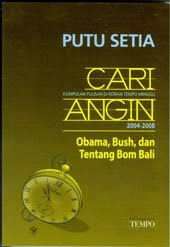


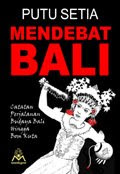

1 komentar:
Om Suastiastu,
Selamat dini hari Ida Bawati. Maaf, saya tidak kirim komentar untuk tulisan anda, tetapi ingin berkenalan. Jalan-jalan di blog, tanpa sengaja ketemu blog anda.
Om Santi Santi Santi, Om
Posting Komentar