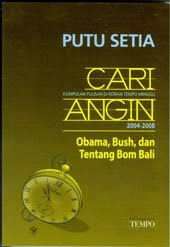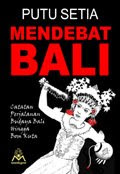Kamis, Agustus 27, 2009
Jumat, Juli 03, 2009
KPK
Di tengah riuh gemuruh kampanye calon presiden, di antara ribuan kata diumbar para tim sukses, banyak yang mencemaskan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih tepatnya, bukan keberadaan Komisi –disebut begitu saja supaya singkat— itu yang dipersoalkan, tetapi ada upaya yang membuat Komisi makin busuk. “Memangnya mangga yang bisa busuk?” kata hati saya.
Namun, saya ikut cemas kalau benar ada upaya yang sistematis untuk memperlemah kerja Komisi. Berbagai cobaan dihadapi Komisi. Ibarat pepatah, makin tinggi pohon makin keras mendapat terjangan angin. Dan “terjangan angin” itu saya rasakan ketika Wakil Ketua Komisi Chandra M. Hamzah diperiksa polisi selama tujuh jam dalam kasus penyadapan telepon seluler Rhani, cewek yang jadi saksi kunci pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Diperiksa tujuh jam? Ini yang mencemaskan, lebih-lebih bagi mereka yang tak tahu lika-liku pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Banyak muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana tekniknya polisi memeriksa seorang “terperiksa” begitu lama? Apakah pertanyaan diajukan dengan begitu pelannya dan “terperiksa” menjawab dengan terbata-bata? Atau mungkin diselingi nonton tayangan gossip di televisi? Apalagi dalam kasus Chandra M. Hamzah ini pertanyaannya –semestinya- amat sederhana.
Dari sini muncullah kekhawatiran di masyarakat, sepertinya Chandra mau “dibidik”, jika tidak kenapa mesti berlama-lama diperiksa. Kalau Chandra sampai “kena bidik” dan kemudian menjadi “tersangka”, maka berkurang lagi pimpinan Komisi setelah Ketua Komisi (Antasari Azhar) dinyatakan nonaktif. “Di sinilah pembusukan itu,” kata seseorang, entah siapa.
Apa pentingnya dan siapa yang berkepentingan dengan “busuknya” Komisi? Oh, banyak. Para koruptor, baik yang sudah merasa akan diseret maupun yang masih gentayangan di tim sukses masing-masing calon presiden, berharap Komisi bukan saja “busuk” tetapi “lumpuh”. Ketika seorang anggota dewan yang terhormat berkoar-koar di televisi dalam kapasitas sebagai tim sukses calon presiden, seorang teman menelepon saya: “Lihat orang itu, dia kan disebut-sebut menerima cek saat memenangkan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia, kapan ditangkap ya?”
Masih ada puluhan teman anggota dewan itu yang seharusnya sudah dipanggil Komisi – atau langsung diperiksa tujuh jam dan ditangkap – jika saja semua pihak mendorong Komisi untuk lebih semangat. Jadi, ini dugaan beberapa teman dan saya setuju, anggota Dewan banyak yang sebenarnya ingin agar Komisi lumpuh, bukan hanya busuk. Bukti lainnya, rancangan undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga dibahas, padahal sebentar lagi anggota Dewan berganti.
Tapi, apakah kepolisian ingin juga Komisi itu “busuk”? Saya tak mau berkomentar, takut kena masalah dan nanti “diperiksa tujuh jam”. Saya hanya ingin mengatakan, memang asal-usul adanya Komisi itu adalah para penyidik – kepolisian dan kejaksaan—dianggap “kurang semangat” dalam memberantas korupsi di negeri ini, meski pun kedua penegak hukum ini punya wewenang menangkap koruptor dan sudah dijalankan. Kalau saja polisi dan jaksa bersemangat “maju tak gentar” memberantas korupsi tanpa melihat “ada bulu atau tidak”, tak akan ada Komisi, apalagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teorinya begitu, para hakim di Pengadilan Negeri sudah cukup menghukum koruptor.
Sayangnya, ketiga calon presiden, tak jelas betul apa sikapnya. Mereka bisa bilang, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan lebih cepat lebih baik untuk tegaknya ekonomi kerakyatan, tapi mau diapakan KPK ini?
(Koran Tempo Minggu 28 Juni 2009)
Debat
Saya menyesal tidak mengikuti debat calon presiden, Kamis malam lalu. Ada acara yang tak memungkinkan menyetel televisi. Namun, teman saya mengaku lebih menyesal lagi karena menonton debat itu sampai selesai. “Tak ada perdebatannya, saya hampir mengantuk,” katanya.
“Anda jangan seperti pengamat politik. Begini salah, begitu salah. Kalau calon presiden saling melempar argumentasi, dikatakan saling serang dan saling sindir. Kalau rukun, dibilang adem ayem. Anda mau apa sih?”
Ucapan saya itu mengagetkan teman saya. “Tapi ini betul-betul bukan debat, ini hanya giliran pidato, bahkan saling dukung. Ganti dong acaranya menjadi ‘kampanye bareng’ atau apalah,” katanya.
Saya jelaskan, kultur Indonesia memang begitu, lebih-lebih para elitnya. Beraninya cuma di belakang, bukan berhadap-hadapan. Kalau Mega ada di Bekasi, ia berani menyerang SBY karena yang diserang tidak ada. Kalau Jusuf Kalla di Aceh, ia berani menyerang SBY yang ada di Malang. Sebaliknya, SBY pun ringan menyindir Mega atau JK, ketika berada di Malang. Jika ketiganya bertemu, semuanya akan rikuh. SBY kan pernah jadi bawahan Mega, JK masih menjadi wakilnya SBY. Kualat bertengkar dengan mantan bos. Adapun Mega, kalau sudah dipuji oleh keduanya, ya, tak bisa marah lagi, apalagi beliau seorang Ibu, simbol keramahan. Justru kalau terjadi perdebatan, ini melanggar petuah orangtua; “nak, jangan bertengkar di tempat ramai.” Ini budaya Nusantara, khususnya Jawa.
“Debat Barrack Obama dengan John Mc Cain kok bisa menarik? Padahal saya cuma baca teks terjemahannya,” kata teman saya.
“Itu karena tradisinya beda,” kata saya. Di Amerika Serikat, budaya debat adalah budaya keilmuan, pakai otak. Yang mendengar juga menggunakan otak. Selesai berdebat mereka salaman, penontonnya juga bisa pulang bareng. Di sini, perdebatan berarti ada ketidak-sepahaman dan itu bisa melahirkan dendam, bisa tak bicara dalam waktu lama, apalagi salaman. Perdebatan nyaris berarti pertengkaran. Penontonnya juga begitu, bisa saling menggebuk mobil saat pulang. Peserta kuis siaran langsung di televisi saja bisa berantem usai acara karena tak senang disindir.
Pengamat kita itu aneh kalau ingin menonton debat yang bermutu, ini belum zamannya. Misalnya, ada calon presiden yang mengumbar isu ekonomi kerakyatan. Lalu, calon presiden yang lain menanyakan, apakah mereka pernah membeli baju di Pasar Ciputat yang berlumpur kalau hujan itu? Jangankan beli baju, kacamata saja membelinya di mal. Kalau sakit bukannya ke Puskesmas, malah ke Singapura. Tim suksesnya juga begitu. Neolib diserang habis-habisan, tapi membeli dasi di Mal Ambasador, bukan di Pasar Cipete. Semua calon itu bermasalah soal “kerakyatan”, semuanya tak tahu isi hati “wong cilik”.
“Anda kenal Siti Musdah Mulia?” Teman saya bengong. Dia itu dosen, doktor, juga ibu rumah tangga. Suatu kali saat acara Indonesian Conference on Religion and Peace – beliau ketuanya– dia bilang ke saya: tak pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan. Padahal dia tak pernah ngomong ekonomi kerakyatan. Beda dengan tetangga saya yang memasang spanduk “Jangan Pilih Capres Neolib”, tapi membeli buku tulis untuk anaknya di Carrefour. Katanya, anaknya jijik dikerubungi lalat pasar.
Kasihan juga melihat teman saya melongo dengan “propaganda” saya. Saya hibur: “Sudahlah, bagus Anda menonton debat sampai selesai dan tak mematikan tv.” Dia menjawab kalem: “Kalau tv saya matikan, saya bisa ketiduran. Debat Kamis malam itu kan menunggu Piala Konfederasi, saya gila bola.”
(Koran Tempo Minggu 21 Juni 2009)
Prita
Di ruangan komputer sebuah sekolah menengah pertama, Ibu Guru menanyakan kepada anak didiknya: "Siapa di antara kalian yang senang mengirim e-mail menceritakan orang lain? Ayo, ngaku!"
Murid usia belasan tahun ini saling toleh sebelum sembilan orang mengacungkan tangan. Bu Guru menunjuk: "Ayo Putri, beri contoh e-mail-mu dan siapa yang kau kirimi e-mail itu." Putri tenang saja. "Bunyinya begini, Bu Guru: hai teman-teman, hati-hati dengan Baskoro, dia jahat, suka mencuri permenku. E-mail saya kirim ke sahabat kelompok dua, tujuh penerima."
Bu Guru lalu mengacungkan koran yang sejak tadi dipegangnya. "Anak-anak, menulis e-mail seperti itu sekarang berbahaya. Kalau Baskoro atau keluarganya mengadukan Putri ke polisi, Putri bisa dipenjara enam tahun dan membayar denda satu miliar. Undang-undangnya begitu, Putri mencemarkan nama baik orang lewat Internet, di koran ini ada beritanya," ujar Bu Guru. Anak didik yang sebelumnya ceria itu serentak melongo, Putri bahkan pucat mukanya.
Kisah di atas setengah fiksi. Yang fiksi dialog-dialognya, karena Luh Putri Devi, keponakan saya dari garis ibu, tak menceritakan dengan detail suasana itu. Setengahnya lagi benar, Ibu Guru di lab komputer sekolah favorit itu meminta anak didiknya berhati-hati menulis e-mail, sambil mengulas kasus Prita Mulyasari di Tangerang. Putri jadi trauma. "Sekarang takut banget deh, Paman, nggak mau lagi main Internet," katanya.
Prita, konon, juga trauma. Tak disangka, curahan hati kepada sepuluh temannya, perihal pengalaman ia dirawat di RS Omni Tangerang, akan berbuntut penjara. Bagaimana e-mail kepada sepuluh "teman pribadi" itu menyebar sampai dibaca pihak rumah sakit tentulah tak sulit dilacak. Bisa dengan teknik sederhana, misalnya, salah satu dari sepuluh orang ini meneruskan ke "teman lain", lalu tersebar ke mana-mana. Atau e-mail itu "bocor", sesuatu yang mudah terjadi di dunia maya Internet.
Prita tak membayangkan masuk penjara hanya karena menulis e-mail. Saya pun tak membayangkan juga karena, berdasarkan pengamatan saya di dunia Internet, "pencemaran nama" yang mirip itu setiap saat ada. Mailing list yang paling beradab, misalnya yang berlabel agama dengan menggunakan moderator sebagai penyaring, pun tak pernah lepas dari gosip yang menjurus pencemaran nama baik. Apalagi mailing list tanpa moderator, bahkan apalagi e-mail antarpribadi.
RS Omni sudah menggugat. Tapi lihatlah hasilnya. Tatkala Prita dipenjara, ada ratusan--jangan-jangan ribuan--posting yang mengecam rumah sakit itu dengan bahasa yang "jauh lebih mencemarkan". Bahkan muncul pemboikotan di cabang lain rumah sakit itu. Dukungan kepada Prita di Facebook mencapai ratusan ribu, setiap detik bertambah. Entah di blog dan mailing list--yang tak mungkin semua saya buka. Dunia maya, saat ini, menjadi kekuatan alternatif dalam membentuk opini publik. Kekuatan yang dahsyat.
Apa bisa kekuatan dahsyat itu diberangus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, terutama oleh Pasal 27 ayat 3 (delik pencemaran nama baik) dan Pasal 45 (denda Rp 1 miliar)? Berapa anggaran negara harus disediakan untuk membangun penjara yang menampung "pencemar nama baik" seperti Prita itu? Teramat konyol jika negeri ini sampai mendirikan Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pencemaran Nama Baik di Internet.
Lagi pula, mana batas pencemaran nama itu? Apakah "Say No to Megawati" atau "Boediono Mbahnya Neolib"--yang gentayangan di Internet--termasuk pencemaran nama baik? Perlu dirumuskan apa kriteria pencemaran itu agar jelas apakah Prita dan Putri perlu dibui atau tidak.
(Koran Tempo Minggu 14 Juni 2009)
Selasa, Juni 16, 2009
Satu Putaran
Pemilihan presiden saat ini ada kemajuan yang berarti. Calon hanya ada tiga pasang, berkurang dibanding pada lima tahun lalu, dengan lima pasang calon. Namun, berapa pun calonnya, kalau lebih dari dua pasang, sangat besar kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan presiden. Apalagi ketiganya punya kekuatan yang berimbang.
Melihat betapa sibuknya ketiga pasang calon ini memanfaatkan semua celah untuk kampanye, tak akan ada yang menang mutlak-mutlakan. Menang mutlak itu hanya ada di era Soeharto. Ini pun sejatinya bukan menang, karena Soeharto takut ada pemilihan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memilih presiden, dipaksakan memunculkan calon tunggal. Kalau sudah calon tunggal, siapa yang menang atau kalah?
Sekarang, ketika rekayasa menggiring suara rakyat tidak memberi jaminan--meski sudah diberi janji, termasuk uang sekalipun--muncul gerakan yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung satu putaran. Dasar pemikirannya bagus, bisa menghemat beberapa triliun rupiah di tengah krisis ekonomi. Cuma, Gerakan Nasional "Setuju Satu Putaran Saja" itu ketua umumnya Denny J.A. (tak usah ditanya siapa yang memilihnya jadi ketua umum) dan menggiring pemilih untuk mencontreng SBY-Boediono. Artinya, gerakan ini merupakan bagian dari kampanye SBY-Boediono.
Tentu saja tim sukses dua pasangan yang lain jadi berang. Padahal, jika menerapkan kampanye yang damai dan bersahabat, konsep satu putaran itu bisa digulirkan oleh semua pasangan dengan jargon masing-masing. Tim sukses Mega-Prabowo, misalnya, akan menyambut ide itu dengan jargon "Oke, Satu Putaran, Pilih Mega-Prabowo". Kemudian tim sukses JK-Wiranto juga setuju satu putaran dengan menawarkan jargon "Pilih JK-Wiranto, Satu Putaran Lebih Cepat Lebih Baik".
Kampanye akan lebih menghibur. Yang jelas lebih mudah dicerna masyarakat dibanding saling sindir dengan istilah-istilah yang tak membumi. Seperti pada acara deklarasi "Pemilu Damai" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Penonton televisi terhibur oleh orasi Butet Kertaradjasa, yang mengkritik banyak hal, termasuk lembaga survei yang bisa dipesan. Banyak yang tertawa, termasuk menertawakan Butet, yang begitu profesional menerima pesanan dan "membela yang bayar", sampai-sampai orasinya--ini bukan monolog karena tak ada unsur seninya--lebih panjang ketimbang orasi calon wakil presiden. Butet saat itu dibayar Mega-Prabowo.
Dalam kasus ini, dua tim sukses yang lain kecolongan dengan tampilnya Butet. Yang terjadi barangkali adalah "kelemahan intelijen". Kalau terendus Butet akan berorasi di pihak Mega-Prabowo, tim sukses SBY-Boediono tentu bisa membayar Mandra, misalnya. Lalu JK-Wiranto membayar Jarwo Kuat atau Kelik Pelipur Lara, yang sudah biasa memerankan Jusuf Kalla di "negeri mimpi". Jika bagi pelucu itu disiapkan bahan untuk "menyerang lawan", tidak ada yang tak bisa.
Rupanya kampanye sekarang ini perlu lebih banyak memakai akal-akalan atau mencuri momen karena Komisi Pemilihan Umum begitu mudah dikibuli, termasuk pada acara yang dibuatnya sendiri, meskipun ditutup dengan permintaan maaf.
Cuma, semakin banyak akal-akalan--survei dan polling, gerakan terselubung satu putaran, orasi berbalut seni monolog, perjalanan dinas tapi kampanye, dan banyak lagi--semakin terbuka akal masyarakat bahwa semua calon itu sesungguhnya memamerkan kekurangan akalnya dalam merebut suara rakyat. Kesalahan para calon dan tim suksesnya hanya satu: mengira rakyat itu bodoh, sehingga dipakailah cara kampanye yang bodoh.
(Dari Koran Tempo 14 Juni 2009)
Kamis, Juni 04, 2009
Kapongor
Suatu hari ada orang yang bertanya pada saya, apakah benar menanam pohon kelapa di depan rumah bisa kapongor. Apa itu kapongor? Tanya saya memancing, “Dimarahi Bethara,” katanya.
Saya katakan, Bethara tak pernah marah, tetapi kapongor itu betul. Nanti kalau kelapanya berbuah lalu jatuh dan menimpa anak-anak yang masih kecil, kan berbahaya.
Di hari yang lain, seseorang bertanya, apa berani menebang pohon kepuh di setra. Pohon itu sudah tua, kalau dahannya rontok berbahaya buat orang yang ada di bawahnya. Lagi pula di setra akan dibangun balai panjang untuk “mesayuban” dari terik matahari atau hujan. Saya jawab: “Potong saja.” Lalu saya ditanya lagi, apa tidak kapongor? Saya katakan; “Tidak”. Dan betul setelah bertahun-tahun tak ada yang berani menebang pohon kepuh yang dibilang keramat itu, sekarang sudah lenyap. Setra jadi asri dan ada bale “mesayuban”.
Ada lagi yang unik. Seseorang yang baru menjadi nenek konsultasi ke saya, dia mau ke balian. Dia ingin bertanya, siapa nama cucunya yang baik agar anak itu tumbuh sehat dan cerdas di masa depan. Saya tanya dulu, apa bapak dan ibunya sudah memberi nama pada anaknya itu? Sudah, katanya. Nama pemberian orang tuanya cukup panjang: Ni Putu Juniwati Putri Dewi. Nenek itu khawatir nama panjang itu akan membuat keluarga itu kepongor, karena nama-nama leluhurnya hanyalah Wayan Sobret, Ketut Manyong, Nengah Keplug dan sebagainya.
Saya katakan kepada nenek itu: “Jangan sekali-sekali menanyakan nama ke balian, nanti nama itu diganti atau dikatakan jelek. Ini nama bagus sekali, anak itu akan cerdas.” Ketika sang nenek diam, saya katakan lagi; “Kalau tanya ke balian paling disebutkan anak itu keberatan nama, lalu sakit-sakitan. Supaya sehat namanya diganti menjadi Putu Lenjog, malah nanti anak itu jadi malu.”
Kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi di pedesaan. malah ada yang sampai bentrok dalam kekeluargaan. Misalnya soal kawitan, dan ini cerita nyata. Sebuah keluarga ada anaknya yang sakit gatal-gatal, lama tak sembuh. Ditanyakan ke balian, eh, ternyata salah kawitan. Selama ini keluarga besarnya itu termasuk soroh Pasek Bendesa. Menurut balian, seharusnya Pasek Kayu Selem. Keluarga itu mantap pindah kawitan, namun keluarganya yang lain tak mau. Alasannya juga sudah menanyakan ke balian yang lain. Apa yang terjadi? Karena takut kapongor terus-menerus -- yang ditandai dengan sakit gatal itu -- keluarga yang anaknya sakit itu pindah kawitan. Ya, akhirnya pecah dadia, pecah panti dan seterusnya.
Saya mengenal keluarga besar itu dan saya tentu tak mau mencampuri urusan soroh berdasarkan omongan balian. Apalagi seumur-umur saya tak pernah bersinggungan dengan balian. Tapi saya siap menolong keluarga itu.
Pertolongan yang pertama saya lakukan, bukan soal kemana mencari soroh yang benar. Tetapi mengajak anak yang sakit gatal itu ke dokter kulit di Denpasar. Ternyata anak itu mengidap penyakit kulit akibat virus yang memang harus diobati secara benar dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya sakitnya sembuh. Setelah anak itu sehat, kepada keluarga besar itu saya minta mempelajari silsilah kawitan berdasarkan babad yang ada. Nah, terserah mereka untuk memilih, mau ke mana. Yang jelas, tak ada urusan kapongor di sini, yang ada urusan virus yang menyerang kulit yang tak bisa disembuhkan oleh obat dari Puskesmas atau loloh dari balian.
Belum lama ini ada keluarga yang juga “minta izin” ke saya, apa baik menanyakan ke balian, apakah kakek dan neneknya yang baru diaben sudah mendapat tempat yang “pas” di sana. Saya tidak heran soal ini, sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Saya tanya alasannya, meski pun saya sudah bisa menebaknya. “Ya, siapa tahu, banten ngabennya kurang ini kurang itu, atau salah runtutan upacaranya,” katanya. Saya katakan, perbuatan menanyakan ke balian itu justru melanggar ajaran agama. Pertama, karena kita menjadi tidak yakin setiap melaksanakan yadnya. Padahal syarat dari yadnya adalah keyakinan. Kedua, kita tidak tulus menyerahkan urusan ritual kepada Sulinggih yang muput, padahal ketulusan ini utama. Jangan pernah ragu dengan Sulinggih begitu kita memilih beliau untuk muput. Ketiga, tak ada urusan Hyang Pitara atau apapun sebutannya setelah diaben menjadi marah atau tak mendapat tempat yang “pas” hanya gara-gara banten. Keempat, siapa balian itu? Kalau balian itu tak pernah mempelajari tingkat pengabenan, omongannya bisa jadi ngawur.
Masyarakat Bali -- meskipun tidak begitu banyak lagi seperti dulu -- masih percaya pada balian jenis ini. Maksudnya balian untuk meluasang, balian baas pipis, balian dasaran, atau sebutan lainnya. Yakni balian yang entah dengan teknik atau ilmu yang beragam, dipercaya bisa menjadi perantara dari roh orang yang sudah tiada. Atau kalau tidak “kemasukan roh” seolah-olah tahu dan bisa menebak segala sumber yang jadi pangkah masalah “pasiennya”. Dari sinilah kemudian muncul istilah kapongor karena berbagai hal. Kapongor salah upacara, kapongor salah banten, kapongor salah memberi nama dan sebagainya.
Anehnya, jarang sekali balian berkata: “Kamu kapongor oleh Hyang Pitara ini karena suka minum arak, suka berjudi, suka metajen, suka selingkuh, suka narkoba, suka memirat.” Kalau ada balian seperti itu, mungkin baik juga, masyarakat Bali bisa lebih sejahtra.
(Editorial Majalah Hindu Raditya, edisi Juni 2009)
Neolib
Di sebuah warung berlabel “mini market” di kawasan Ubud, Bali, saya terkejut menyaksikan adegan ini. Seorang anak muda tergopoh-gopoh menuju rak obat dan bertanya pada pelayan: “Ada neolib?”
Ia tak bergurau mengucapkan kata itu. Pelayan, perempuan yang juga muda, menjawabnya dengan kalem, jauh pula dari nada canda: “Neolib untuk flu, apa neolib untuk nyeri?” Si lelaki menjawab cepat: “Neolib untuk flu.” Pelayan memberikan satu bungkus tablet bergambar kepala orang. Transaksi terjadi, lalu anak muda itu pergi.
Setengah penasaran saya mendekati pelayan. “Kenapa obat yang sudah populer itu disebut neolib?” Barulah pelayan itu tersenyum, manis juga, dan khas pelayan warung di kawasan pariwisata. “Di sini orang sudah terbiasa dengan plesetan yang dipopulerkan televisi. Semua obat dengan awalan neo disebut neolib, makanya saya tanya, neolib untuk flu atau nyeri. Sering pula disebut neolib tablet atau neolib krim,” ujar si pelayan.
Konon, plesetan itu hanya awalnya saja menimbulkan nada canda. Begitu lewat tiga hari apalagi seminggu, plesetan sudah tak ada nada candanya lagi, sudah biasa-biasa saja. Ternyata banyak juga jenis “plesetan politik”, bukan hanya neolib. Kalau ada orang yang tadinya jarang bergaul atau enggan menyapa, lalu tiba-tiba ramah, orang itu dijuluki: “kerakyat-rakyatan”. Misalnya: “Pak Dogler sekarang kerakyat-rakyatan, pasti ada maunya.”
Anehnya, julukan “kerakyat-rakyatan” hampir selalu berkonotasi negatif. Ada temannya yang lain. Ketika seorang pengendara sepeda motor meraung-raungkan mesin motornya saat melintas di depan mini market itu, petugas parkir berteriak: “lanjutkan, lanjutkan, lebih cepat lebih baik mati”. Begitu pula ketika petugas parkir menggoda cewek, pedagang bakso menggoda: “Pak Parkir, lanjutkan, lanjutkan, mumpung istri tak ada…”
Apa tahu arti neolib? Ini pertanyaan yang saya ajukan kepada pelayan warung, pedagang bakso, dan petugas parkir. Pelayan hanya tertawa karena memang tak tahu. Pedagang bakso juga tertawa, lalu dia bilang: “Saya belum gila, tak perlu neolib”. Dan ini jawaban petugas parkir, agak panjang: “Itu kan dagelan bapak-bapak di televisi. Semua bersilat kata. Semua mengaku pintar. Semua mengaku dekat rakyat. Kita nonton senang saja, banyak kata-kata baru untuk bahan becanda.” Saya tanya, kalau diberi kesempatan bicara, mau bilang apa kepada bapak-bapak itu? Tak lama berpikir, petugas parkir berkata: “Berhenti saja deh ngomong membela rakyat, kok nggak tahu malu ya? Kan kelakuannya sudah diketahui rakyat.”
Malam ini, mungkin besok malam pula, kata neolib boleh jadi masih beredar. Pesaing pasangan SBY-Budiono terus menghunjamkan istilah neolib ini untuk menyerang. Budiono jadi sasaran tembak oleh orang-orang yang berada di kubu JK-Win dan Mega-Prabowo. Tembakan yang berhasil, bukan karena penembak yang piawai, tetapi Budiono mau menyediakan diri bersibuk-sibuk membantah. Ia menari dalam irama gendang lawannya.
Jadi, Budiono memang lugu dan “kurang mahir” berakrobat politik. Bukan saja dituduh membawa paham neolib, tapi juga disebut “mbahnya neolib” atau seperti yang dibilang tim suksesnya Mega-Pro, “ayatulahnya neolib”. Sampai kapan Budiono terus menari?
Padahal, isu neolib sudah ditertawakan masyarakat. Bahkan slogan yang diembel-embeli “kerakyatan” juga dicibir. Orang desa yang lugu bertanya: “Para jenderal yang bertarung itu kok bisa kaya sekali, berapa gajinya sebagai tentara? Sekarang ngaku membela rakyat, apa nggak nilep uang rakyat sebelumnya?” Mungkin ini perlu jawaban.
(Dari Koran Tempo Minggu 31 Mei 2009)
Tentara Kita
Kalau tiba-tiba mendengar ada suara bergemuruh, cobalah segera menatap langit. Siapa tahu ada pesawat terbang yang oleng, lalu menabrak rumah Anda. Peringatan ini ditujukan kepada semua penduduk negeri tanpa kecuali, karena kecelakaan pesawat bisa terjadi di mana saja. Namun, warga yang diam di dekat pangkalan militer, tentu lebih waspada.
Terbakarnya pesawat Hercules di Magetan, pekan lalu, sungguh tragedi yang mengenaskan. Ini kecelakaan pesawat yang ke sekian dengan korban yang banyak. Korbannya tentara kita – lebih akrab disebut begitu dibandingkan Tentara Nasional Indonesia. Juga banyak warga sipil, keluarga tentara dan pemilik rumah yang dilabrak.
Dianalisa dari berbagai sudut, diinvestigasi dari berbagai faktor, tetap muncul sangkaan kuat penyebab jatuhnya pesawat karena usianya yang uzur, perawatannya yang minim, dan mungkin saja suku cadangnya “asli tapi palsu”. Kabut boleh dijadikan kambing hitam, tetapi banyak pesawat tentara kita yang memang sudah tua.
Apa pun hasil investigasinya, saya ikut berbela sungkawa kepada para korban. Hanya, saya menyesalkan ada wakil rakyat yang mendadak menjadi pahlawan, muncul di televisi yang meminta semua pejabat terkait mundur. Dari Kepala Staf TNI AU, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan yang tidak disebutkan, Presiden. Kata wakil rakyat itu, pejabat ini sudah tak punya rasa malu dengan berbagai kecelakaan pesawat yang menewaskan perwira-perwira terbaik tentara kita.
Kalau salah yang dicari, yang benar tidak akan didapat. Siapa yang mengkritisi anggaran pertahanan di DPR? Siapa yang dulu -- dan berulang kali dikatakan – bahwa anggaran pertahanan tak perlu mendapat prioritas? Sudah lama tentara kita tidak mendapatkan prioritas dari sisi anggaran. Di zaman global yang menghormati hak asasi manusia ini, kata sejumlah politisi, tak ada negara menyerang negara. Artinya, faktor ancaman dari luar nol koma kosong. Jadi, lebih baik membangun bendungan, pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pabrik pupuk, dibandingkan membeli senjata termasuk pesawat militer. Di masa damai dan tenang ini, begitu diucapkan, membangun puskesmas dan memperbaiki nasib petani jauh lebih penting dari memikirkan tentara.
Akhirnya, Nusantara ribuan pulau ini punya anggaran pertahanan jauh di bawah Singapura, negeri satu pulau. Tentara kita mulai “tak dianggap”, baik oleh orang luar, juga oleh orang dalam. Dulu, perayaan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober senantiasa ditunggu masyarakat karena akan ada akrobatik udara atau aksi memukau di lautan. Masyarakat bangga, anak-anak kecil pun memakai “baju tentara”. Kini, tak ada lagi. Perayaan 5 Oktober diisi perwira cakep dan cantik melakukan gerakan seragam dengan langkah tegap: satu, dua, satu, dua. Memang ada unjuk ketrampilan, tetapi itu sebatas tentara yang menebas balok es dengan tangan kosong. Kurang membanggakan. Bukan saja balok es lebih murah ketimbang pesawat tempur, ketrampilan itu jamak ada di dunia persilatan, bahkan di pesantren. Lihat di Pasar Senen Jakarta, atau di sepanjang Malioboro Yogyakarta, busana anak-anak dengan atribut militer sudah jauh berkurang dibandingkan dulu.
Saat ini, ketiga pasang calon presiden, semuanya ada unsur tentara. Ada dua mantan jenderal kesohor menjadi calon wakil presiden, ada satu mantan jenderal yang lebih kesohor lagi menjadi calon presiden.. Siapa pun yang terpilih, semestinya bisa berjuang kembali membangun tentara kita. Petani memang perlu disejahtrakan, tetapi tentara juga, karena petani dan tentara adalah juga manusia.
(Dari Koran Tempo Minggu 17 Mei 2009)
Senin, Mei 11, 2009
Rani
Saya tidak sedang menulis Rani, atau nama lengkap di kartu tanda penduduknya, Rhani Juliani. Mantan caddy golf yang menjadi wanita terpopuler saat ini karena kasus pembunuhan Nasrudin itu, tidak saya kenal. Bagaimana saya menulis orang-orang yang tidak saya kenal?
Tapi saya mengenal beberapa orang yang dipanggil akrab Rani. Dari penulis fiksi, penyanyi, aktifis pers kampus, tentu dengan nama lengkap yang berbeda. Salah satunya adalah Sutirani, gadis asal Temanggung, bekas tetangga saya sewaktu saya tinggal di Sidoarum, Godean, Yogyakarta.
Rani Temanggung ini begitu tamat SMA tidak melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, barangkali mirip Rani Tangerang di awal-awalnya. Ia ikut Bu De-nya ke Yogya, kursus memijat beberapa hari, lalu menjadi gadis pemijat di sebuah “panti pijat tradisional”. Tak sampai sebulan ia bertahan, banyak hal yang ia keluhkan pada saya. Belakangan saya dengar dia menjadi pramuria – sebutan keren pelayan – di toko Sami Jaya, kawasan Malioboro. Entah sekarang.
Kenapa saya sering ingat Rani? Ia pernah berkeluh, seorang pria setengah tua, suatu hari menjadi “pasiennya”. Setelah waktu habis, Rani mengingatkan pijatan sudah selesai. Pria itu setengah marah membentak: “Mana tradisionalnya?” Rani mulanya kaget, apa yang dimaksudkan “tradisional” itu. Syukur, pria itu hanya marah, lalu keluar.
Belakangan banyak pria yang terus menggoda: “Dik, jangan lupa tradisionalnya, ya?” Atau kalimat ini: “Kalau pakai tradisional, tambah berapa?” Lama-lama Rani tahu, apa yang dimaksudkan: berbuat mesum. Ia punya jurus menolak, dan teknik penolakan itu yang membuat saya kagum, sekaligus sering ingat dia. Ia hanya mengatakan begini: “Bapak kan sudah berumur, mungkin bapak punya anak gadis seusia saya, kalau anak gadis bapak dibegitukan, apa bapak tega?” Teknik ini mempan, tapi Rani memutuskan tak lagi bekerja di panti pijat berembel tradisional itu.
Jurus ini sering saya kutip kalau saya lagi berceloteh soal moral di berbagai kesempatan. Malah saya kembangkan. Misalnya, bagaimana menghindari perselingkuhan? Saya katakan: “Ketika Anda sedang berniat untuk berselingkuh dengan wanita idaman lain, cobalah merenung satu menit, bagaimana kalau istri Anda juga melakukan hal yang sama dengan pria idaman lainnya. Apakah Anda senang?”
Jika jurus itu tak mempan, coba lagi merenung satu menit, dan sebut nama Tuhan. Tak satu pun agama membenarkan perselingkuhan dan perzinahan. Surga ada di telapak kaki ibu, dan ibu itu adalah wanita, janganlah wanita dilecehkan. Ada kitab suci yang jelas menyebutkan: “di mana wanita dihina dan diperlakukan tak semestinya, di sana kekacauan akan muncul”.
Jika nama Tuhan sudah disebut dan Anda tetap berselingkuh, itu artinya setan lebih banyak disekeliling Anda. Ini pun termasuk “skenario “ Tuhan, mereka yang lemah akan dijadikan alat untuk memberi kesempatan bagi orang lain bekerja dengan baik. Kalau penjahat tidak ada, polisi tak ada kerjaan. Kalau koruptor tak ada, Komisi Pemberantasan Korupsi tak dibentuk. Sekarang Anda memilih, yang baik atau yang buruk?
Saya tak menyindir bahwa kasus Rani-Nasrudin-Antasari diawali dengan pelecehan seorang wanita, karena “sinetron” ini masih berlanjut. Saya juga tak mau mengulangi petuah yang sudah klise agar pemimpin berhati-hati terhadap 3 TA: tahta, harta dan wanita. Saya hanya ingin mengatakan: wahai kaum pria, hormatilah wanita.
Sesekali menulis tentang moral, bolehlah. Suasananya masih merayakan Waisak, hari penuh kedamaian. Selamat bagi yang merayakannya.
(Koran Tempo 10 Mei 2009)
Jumat, Mei 08, 2009
Yadnya Tak Harus Mahal
Upacara Pitra Yadnya atau ngaben atau pembakaran jenazah adalah pekerjaan mudah dan murah yang sering dipersulit sendiri, dan dimahal-mahalkan oleh penjual banten. Begitu seorang Pandita Mpu memberikan penataran di hadapan para pemangku. Lalu, beliau bercerita, bagaimana orang memper¬siapkan banten ngaben itu jauh-jauh hari. Pas ketika upacara, semua banten lumutan, janurnya kusut, kue dan sesajinya berjamur, semut merayap penuh di sana-sini. Baunya pun tak sedap lagi. Pandita Mpu pun melanjutkan ceramahnya: “Apa banten seperti itu kita haturkan kepada Tuhan untuk mengantar roh yang akan kita upacarai? Apa Tuhan tidak tersinggung diberikan banten yang sudah bengu (bau busuk)?”
Ini sebenarnya cerita lama, tetapi memang masih terjadi di pedesaan, apalagi kalau di pegunungan. Setiap melakukan dharmawacana ke luar Bali, saya pun sering ditanya soal ini, soal banten yang bau. Maklum, banten dikirim dari Bali, dipaketkan lewat kapal laut, jadi selain karena bau alamiah, juga kemasukan air laut. Jawaban saya adalah, saya tak tahu, apakah Tuhan tersinggung atau tidak. Saya belum pernah mendengar ungkapan Tuhan Maha Tersinggung. Tapi kalau hati kita sudah tidak enak meng¬haturkan banten yang “bengu” begitu, apalagi daging ayamnya sudah dipenuhi lalat, bisa jadi Tuhan memang ter-singgung. Bukan karena banten itu, tetapi karena kita sendiri sudah tidak sreg lagi, jadi Tuhan hanya mengikuti kondisi batin kita. Jelasnya saya katakan, “saya yang tersinggung kalau muput diberi banten bengu, karena itu kalau nanti saya sudah melinggih, jangan saya diminta muput jika bantennya bau. Saya mudah bersin.”
Umat Hindu di Bali, terutama di pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak banyak mendalami kitab-kitab agama, seringkali terjebak pada pola takut salah dalam mengha¬turkan banten. Takut tidak komplit, takut kurang ini atau kurang itu. Kalau salah, nanti Tuhan memberikan kutukan. Ida Bethara dan Bethara Kawitan juga memberikan kutukan atau setidak-tidaknya memberikan “sakit” sebagai sinyal dari adanya kesalahan itu. Istilah di pedesaan seperti “kepongor” atau “kepanesan” adalah suatu kepercayaan bahwa para leluhur kita — bahkan dalam tingkat tertinggi Hyang Widhi — menjatuhkan hukuman kepada umatnya karena melakukan tindakan yang salah atau kurang lengkap dalam melaksanakan upacara. Tuhan dan Bethara lebih sebagai penghukum, bukan sebagai Yang Maha Kasih, Yang Maha Pengampun.
Karena itu, supaya tidak salah, maka upacara ritual pun harus lengkap. Lengkap versi siapa? Lengkap menurut tradisi yang sudah turun-menurun, tanpa peduli lagi apakah tradisi itu benar atau sudah salah dari sononya. Karena itulah tidak sedikit orang yang menga¬dakan upacara ngaben sampai menjual harta warisan, agar pelaksanaan ritualnya disebut lengkap. Pokoknya demi upacara lengkap itu, pendidikan anaknya bisa dikorbankan, tanah produktif untuk kehidupan sehari-hari bisa digadaikan. Uang SPP anak dikorbankan karena harus membuat bebangkit. Padahal tanpa bebangkit pun yadnya bisa jalan.
Upacara Pitra Yadnya yang lengkap itu juga dikaitkan dengan kesenian, baik berupa bunyi-bunyian maupun pementasan tari. Ngaben tanpa bunyi angklung terasa begitu asing, kata orang.di kampung saya Tapi, kenapa tidak membunyikan gamelan angklung dari kaset lewat pengeras suara saja? Ini kan menghemat ratusan ribu.
Belum lagi tradisi gamelan gambang, yang konon satu-satunya gamelan yang bisa mengantarkan “pitara” ke sorga. Tanpa gamelan itu, tak ada jalan menuju sorga. Lalu lesung yang ditumbuk itu (ngeluntang), yang akan menyambut arwah-arwah yang akan diupacarai. Langkanya lesung penumbuk padi akan membuat kelabakan orang untuk mencari di mana ada lesung yang bisa disewa. Di sini saya selalu katakan, tradisi apapun yang ada di Bali selalu mengacu kepada tradisi agraris. Sekarang zaman global, padi tak perlu ditumbuk pakai lesung, ada mesin slip, kenapa ngaben tidak membunyikan mesin slip saja? Kan orang yang diaben belum tentu pula tahu lesung karena sudah hidup di zaman global.
Itu baru di tingkat bunyi-bunyian. Kemudian di tingkat pe¬mentasan, ada kepercayaan harus meminta tirtha dalang wayang kulit dengan lakon tertentu, yang ada kaitannya dengan sorga atau mencari air suci untuk mengantarkan roh ke surga. Lakon yang terkenal dalam kaitan ini adalah Biwa Swarga, Dewa Ruci dan berbagai variasinya yang tentu saja tak dikenal dalam ephos Mahabharata yang asli.
Pernah saya menanyakan kepada seorang dalang, kenapa ia mementaskan cerita yang aneh, yaitu Anoman ke sorga mencari tirtha. Bukan Bima sebagaimana lazimnya. Jawabannya enteng saja: “Saya tak biasa mendalang dengan lakon Mahabharata, saya spesialis Ramayana.” Pentas wayang kulit di Bali di masa lalu memang ada dua kubu: Mahabharata dan Ramayana yang dibedakan oleh gamelan pengiringnya. Nah ini kan lagi-lagi tradisi yang sudah ditinggalkan. Sekarang dalang Cenk-Blong (Wayan Nardayana), mau pentas Mahabharata atau Ramayana tetap saja pakai gamelan semar pegulingan. Tradisi tak harus dipertahankan, tetapi sastra agama harus dipertahankan.
Lalu, apa kaitannya pentas wayang kulit ini dengan upacara Pitra Yadnya? “Sebenarnya tak ada, karena tirtha dalang itu sendiri bisa diminta tanpa harus ada pementasan,” kata sang dalang. Ini benar sekali, bahkan tirtha dari Sang Dalang itu sendiri juga bukan keharusan. Kalau Pandita Mpu masih tergantung pada tirtha dalang untuk muput ngaben, wah, jangan mediksa dululah. Ini yang sering saya katakan.
Kesenian ini hanyalah embel-embel. Di Puri Gianyar kalau ada upacara pitra yadnya, biasanya dipentaskan tari gambuh, suatu hal yang tentu sulit untuk “ditiru” di daerah lain yang tidak mengenal tari klasik itu. Akhirnya kembali kepada masalah “perasaan batin” yang punya upacara, sejauh mana ia merasa sudah melak¬sanakan ritual itu secara lengkap. Kesenian itu sama saja akhirnya dengan banten, apakah kita puas dengan membuat yang sederhana kalau memang mampunya seperti itu? Atau kita memaksakan diri, padahal kita jelas tidak mampu?
Belakangan ini, dalam hal ritual di lingkungan keluarga, saya selalu mengatakan jangan menghambur-hamburkan yang tak perlu. Tetapi juga dipertimbangkan bagaimana kita bermasyarakat. Menyelenggarakan yadnya adalah juga menunjukkan cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau dana ada, kenapa harus memutar kaset yang berisi kidung dan gamelan, kenapa tidak mengundang sekehe shanti. Kenapa tidak mengundang sekehe topeng, sekehe angklung, dan sebagainya. Jangan dengan alasan sederhana, kita melakukan yadnya dengan “sepi ing demit” (sepi karena pelit).
Ada kawan saya dari Kalimantan yang heran melihat yadnya yang tergolong “megah” ketika anak saya potong gigi. “Pak Putu tidak konsisten, selalu menganjurkan yadnya yang sederhana, kok sekarang mewah, ada topeng, ada gamelan gong, ada angklung, ada gender ada banyak penari, undangannya pun banyak.,” katanya. Jawaban saya: “Ini karena Hyang Widhi suweca dengan saya. Saya diizinkan punya gamelan gong, lalu disumbang aklung oleh banjar, topeng punya sendiri, penari anak-anak ashram. Kalau saya beryadnya dengan sepi-sepi, kapan saya bisa menjamu warga desa saya sendiri?”
Lagi pula, saat saya beryadnya itu, saya masih hidup dengan “gaya Jakarta” dengan sobat-sobat yang juga datang dari Jakarta. Menjamu 200-an warga desa biayanya sama dengan makan sepuluh orang di hotel berbintang. Nanggap wayang kulit di Bali jauh lebih murah dari mendatangkan seorang MC kalau membuat acara di Jakarta. Jika ukurannya di bawa ke sini, tak ada alasan untuk berpelit-pelit dengan dalih “upacara agama terlalu mahal”. Justru kita disebut kikir atau pelit, beryadnya sederhana tetapi tiap malam mabuk-mabukan di kafe. Tentu harus tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, jangan membuat yadnya yang mewah saat gagal panen kopi, misalnya,
Begitu sebaliknya, kalau kita hidup serba kekurangan, untuk makan sehari-hari saja masih berjuang keras, untuk apakah kemewahan ritual yang hanya meneruskan tradisi lama itu? Tingkatan yadnya bisa diturunkan, kesenian tak menjadi keharusan, ritual bisa dibuat dengan murah. Jika perlu, ya, gabung saja menyelenggarakan yadnya seperti yang dilakukan oleh Semeton di Sekretariat Pasek ini. Ritual jangan sampai memberatkan.***