Saya punya sahabat orang Aceh. Tapi ini “sahabat internet”, mungkin istilah ini tak cocok. Saya ingin menggambarkan bahwa persahabatan itu sangat kental tetapi kami tak pernah jumpa. Di masa lalu perkawanan ini disebut “sahabat pena”.
Awalnya dia minta dipanggil Dek Gam, sebutan untuk anak lelaki. Kemudian, panggilan itu berubah ketika kami berdiskusi soal Gerakan Aceh Merdeka yang akronimnya GAM. “Ganti saja panggilan saya jadi cilek karena perawakan saya kecil,” katanya. Cilek di Aceh, ya, sama dengan cilik di Jawa.
Namun, dia memanggil saya bapak, padahal saya siapkan pilihan abang, mas, atau bli. Yang terakhir ini khas Bali. Alasannya, nah, ini yang membuat bulu hidung saya berdiri saking bangganya, dia kagum dengan tulisan saya, baik di koran, di blog, maupun di beberapa buku. Ini sesungguhnya tak enak untuk disebutkan, tapi karena saat ini musim kampanye di mana kesombongan diumbar, tak apalah.
Dialog kami yang paling menarik tentu saja masalah sosial dan agama. Latar belakang budaya dan agama yang berbeda, membuat kami makin intim “bagaikan saudara kandung” (istilah saya) atau “bapak jadi orangtua kedua saya” (istilah dia). “Seharusnya orang seperti bapak yang dipinang menjadi calon legislatif oleh partai, bukan artis,” tulisnya suatu ketika, yang membuat saya kaget, kenapa urusan agama tiba-tiba dibawa ke calon legislatif.
Dia mengaku muak dengan ulah para politisi sekarang ini. Apalagi entah sadar atau tidak, istilah agama dipakai untuk urusan korupsi. Misalnya, “korupsi berjamaah”. Ketika Agus Condro menerima duit Rp 500 juta, disebutkan pembagian itu untuk “kloter” pertama. “Kata kloter tak ada dalam kamus, itu kan asalnya dari kelompok terbang, istilah untuk angkutan haji, urusan agama, kok dibawa-bawa ke uang haram?” Cilek marah betul.
“Itu sebabnya saya mohon para ulama, pendeta, apa pun sebutannya lagi, jadilah calon legislatif. Keluarlah sejenak dari pesantren, pesraman, pedukuhan, atau apa pun sebutannya, tolong urus negeri ini. Kenapa harus artis?”
“Jangan sepelekan artis. Saya kenal Miing, saya tahu Tantowi dan Helmy Yahya,” saya mencoba membela. Tapi, cilek, sahabat Aceh ini, tetap ngotot: “Ya, tapi pondasi moral mereka tetap tak kokoh, bangsa ini sudah mengalami kehancuran moral, hanya ulama sejati yang bisa membenahinya.”
Siapa itu ulama sejati? “Pemuka agama yang menebarkan kedamaian. Pemuka agama yang membawa kesejukan dan ketentraman. Pemuka agama yang bisa berdebat sambil tersenyum,” jawabnya.
Nah, di sini persoalannya. Kebanyakan dari mereka itu tidak dikenal secara nasional. Mereka umumnya tokoh lokal karena memang pengabdian mereka itu nyata di masyarakat. “Itu betul Pak, seperti halnya bapak, saya sudah tanya ke teman-teman, apa pernah dengar nama bapak?. Jawabnya, tidak. Yang sering didengar Putu Wijaya. Tapi, bukankah itu harusnya tugas partai yang mengangkat tokoh lokal ke nasional?
Saya menjawab emailnya dengan tertawa, seolah wajahnya ada di komputer. “Di situ persoalannya, meski saya bukan tokoh agama, saya tahu persis pemuka agama tak suka bergaya selebritis, apalagi berulah artis. Mereka pun bukan kader partai.”
Komunikasi kami macet beberapa saat sampai dia menulis lagi: “Pokoknya saya tetap percaya, kini giliran tokoh agama yang harus memperbaiki negeri ini, tapi bagaimana caranya, ya?” Saya belum membalasnya, karena saya juga tak tahu bagaimana caranya. Apa, ya, ada pemuka agama yang mau mengiklankan dirinya untuk kekuasaan, apalagi hanya untuk direkrut menjadi calon legislatif?
(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo edisi Minggu 24 Agustus 2008)
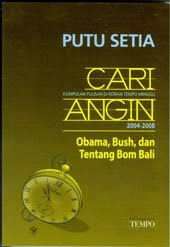


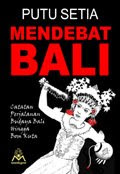

2 komentar:
Sangan Bagus
Tulisanini sangat bagus dan kami senang sekali membacanya karena bisa mewakili apa yang ada dalam benak kami.
Selamat berkarya
sangat menarik... ida bhawati, sempat membuat blog. tentunya akan sangat menghibur dan mendidik membaca tulisan-tulisan di blog ini, semoga semakin sering muncul tulisan ida disela-sela mempersiapkan kehidupan yg lebih baik....
dudik
Posting Komentar