Ketika menonton Muhaimin Iskandar berebutan mengambil nomor urut partai dengan Yenny Wahid, istri saya kembali kambuh kesalnya gara-gara partai yang ia dirikan tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
“Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Maha Besar, itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai ibu akan didukungnya,” kata istri saya nyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai ibu akan laku?”
Saya sudah capek menasehati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istrirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.
“Bersyukurlah Bu, Partai Besar tidak lolos. Sudah ada 34 partai yang lolos, dan itu terlalu banyak. Rakyat sudah antipati pada partai. Mendengar partai yang dibayangkan anggota dewan, lalu mendengar sejumlah kata: korupsi, suap, main perempuan. Citra partai sudah hancur,” kata saya menenangkan.
“Partai-partai baru sulit laku,” kata saya lagi. “Masyarakat telah terpola dengan tiga partai, PDI mewakili kaum nasionalis, Golkar mewakili kekaryaan dan PPP mewakili Islam. Ini karena sejarah yang panjang. Kalau ditambah dua lagi, yaitu PKS dan Partai Demokrat, ya, semestinya sudah cukup lima partai. Partai baru seperti Hanura, Gerinda, dan lainnya, itu kan Golkar dalam bentuk lain. Partai Pelopor, PNI Marhaenis, Banteng Kemerdekaan, dan sejenisnya, itu kan dianggap sempalannya PDI. Begitu pula partai yang berbasis Islam, ada banyak karena sempal-menyempal. Kalau induknya masih ada kenapa harus bergabung ke sempalannya? Coba saja lihat nanti, partai-partai baru itu hanya dapat suara nol koma nol nol persen.”
“Tapi kan tetap dapat suara,” potong istri saya. “Waktu pemilihan Gubernur Bali ada kandidat yang mengumpulkan partai yang perolehan suaranya nol koma nol persen itu, partai kecil dapat uang lumayan karena menjadi penggenap agar jumlah suaranya 15 persen.”
“Itu memalukan. Mestinya partai dengan suara minimum langsung dibubarkan dan pengurusnya tak boleh mendirikan partai apapun lagi. Unsur malu harus jadi etika politik. Negeri ini amburadul kalau rasa malu sudah hilang,” saya memotong. Namun saya sudah tak sabar. “Ya sudah, tapi Ibu jangan menyalahkan KPU. Mungkin anak kita di Jakarta yang terlambat mendaftarkan …” saya mencoba lagi menenangkan.
Istri saya langsung menelepon anaknya. “Komang, apa betul Partai Besar yang ibu dirikan sudah didaftarkan ke KPU? Kok tidak lolos? Kan semua keluarga Ibu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Jawa sepakat membentuk cabang?”
Terdengar suara di handphone. “Lo, lo, ibu mendirikan partai politik?”
“Ya, dong, Partai Besar itu partai politik…”
“Waduh, maaf Bu, saya mendaftarkannya ke Departemen Perdagangan, bukan ke KPU.
Saya pikir Ibu mendirikan toko kelontong, kan toko kelontong di Jakarta umumnya berisi tulisan: menjual eceran, grosir, partai besar dan partai kecil….”
(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo)
“Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Maha Besar, itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai ibu akan didukungnya,” kata istri saya nyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai ibu akan laku?”
Saya sudah capek menasehati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istrirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.
“Bersyukurlah Bu, Partai Besar tidak lolos. Sudah ada 34 partai yang lolos, dan itu terlalu banyak. Rakyat sudah antipati pada partai. Mendengar partai yang dibayangkan anggota dewan, lalu mendengar sejumlah kata: korupsi, suap, main perempuan. Citra partai sudah hancur,” kata saya menenangkan.
“Partai-partai baru sulit laku,” kata saya lagi. “Masyarakat telah terpola dengan tiga partai, PDI mewakili kaum nasionalis, Golkar mewakili kekaryaan dan PPP mewakili Islam. Ini karena sejarah yang panjang. Kalau ditambah dua lagi, yaitu PKS dan Partai Demokrat, ya, semestinya sudah cukup lima partai. Partai baru seperti Hanura, Gerinda, dan lainnya, itu kan Golkar dalam bentuk lain. Partai Pelopor, PNI Marhaenis, Banteng Kemerdekaan, dan sejenisnya, itu kan dianggap sempalannya PDI. Begitu pula partai yang berbasis Islam, ada banyak karena sempal-menyempal. Kalau induknya masih ada kenapa harus bergabung ke sempalannya? Coba saja lihat nanti, partai-partai baru itu hanya dapat suara nol koma nol nol persen.”
“Tapi kan tetap dapat suara,” potong istri saya. “Waktu pemilihan Gubernur Bali ada kandidat yang mengumpulkan partai yang perolehan suaranya nol koma nol persen itu, partai kecil dapat uang lumayan karena menjadi penggenap agar jumlah suaranya 15 persen.”
“Itu memalukan. Mestinya partai dengan suara minimum langsung dibubarkan dan pengurusnya tak boleh mendirikan partai apapun lagi. Unsur malu harus jadi etika politik. Negeri ini amburadul kalau rasa malu sudah hilang,” saya memotong. Namun saya sudah tak sabar. “Ya sudah, tapi Ibu jangan menyalahkan KPU. Mungkin anak kita di Jakarta yang terlambat mendaftarkan …” saya mencoba lagi menenangkan.
Istri saya langsung menelepon anaknya. “Komang, apa betul Partai Besar yang ibu dirikan sudah didaftarkan ke KPU? Kok tidak lolos? Kan semua keluarga Ibu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Jawa sepakat membentuk cabang?”
Terdengar suara di handphone. “Lo, lo, ibu mendirikan partai politik?”
“Ya, dong, Partai Besar itu partai politik…”
“Waduh, maaf Bu, saya mendaftarkannya ke Departemen Perdagangan, bukan ke KPU.
Saya pikir Ibu mendirikan toko kelontong, kan toko kelontong di Jakarta umumnya berisi tulisan: menjual eceran, grosir, partai besar dan partai kecil….”
(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo)
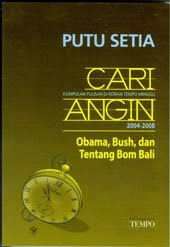


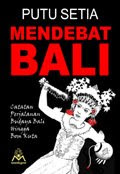

Tidak ada komentar:
Posting Komentar