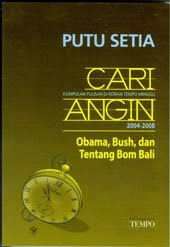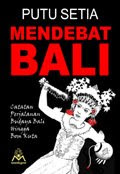Pemilihan presiden saat ini ada kemajuan yang berarti. Calon hanya ada tiga pasang, berkurang dibanding pada lima tahun lalu, dengan lima pasang calon. Namun, berapa pun calonnya, kalau lebih dari dua pasang, sangat besar kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan presiden. Apalagi ketiganya punya kekuatan yang berimbang.
Melihat betapa sibuknya ketiga pasang calon ini memanfaatkan semua celah untuk kampanye, tak akan ada yang menang mutlak-mutlakan. Menang mutlak itu hanya ada di era Soeharto. Ini pun sejatinya bukan menang, karena Soeharto takut ada pemilihan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memilih presiden, dipaksakan memunculkan calon tunggal. Kalau sudah calon tunggal, siapa yang menang atau kalah?
Sekarang, ketika rekayasa menggiring suara rakyat tidak memberi jaminan--meski sudah diberi janji, termasuk uang sekalipun--muncul gerakan yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung satu putaran. Dasar pemikirannya bagus, bisa menghemat beberapa triliun rupiah di tengah krisis ekonomi. Cuma, Gerakan Nasional "Setuju Satu Putaran Saja" itu ketua umumnya Denny J.A. (tak usah ditanya siapa yang memilihnya jadi ketua umum) dan menggiring pemilih untuk mencontreng SBY-Boediono. Artinya, gerakan ini merupakan bagian dari kampanye SBY-Boediono.
Tentu saja tim sukses dua pasangan yang lain jadi berang. Padahal, jika menerapkan kampanye yang damai dan bersahabat, konsep satu putaran itu bisa digulirkan oleh semua pasangan dengan jargon masing-masing. Tim sukses Mega-Prabowo, misalnya, akan menyambut ide itu dengan jargon "Oke, Satu Putaran, Pilih Mega-Prabowo". Kemudian tim sukses JK-Wiranto juga setuju satu putaran dengan menawarkan jargon "Pilih JK-Wiranto, Satu Putaran Lebih Cepat Lebih Baik".
Kampanye akan lebih menghibur. Yang jelas lebih mudah dicerna masyarakat dibanding saling sindir dengan istilah-istilah yang tak membumi. Seperti pada acara deklarasi "Pemilu Damai" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Penonton televisi terhibur oleh orasi Butet Kertaradjasa, yang mengkritik banyak hal, termasuk lembaga survei yang bisa dipesan. Banyak yang tertawa, termasuk menertawakan Butet, yang begitu profesional menerima pesanan dan "membela yang bayar", sampai-sampai orasinya--ini bukan monolog karena tak ada unsur seninya--lebih panjang ketimbang orasi calon wakil presiden. Butet saat itu dibayar Mega-Prabowo.
Dalam kasus ini, dua tim sukses yang lain kecolongan dengan tampilnya Butet. Yang terjadi barangkali adalah "kelemahan intelijen". Kalau terendus Butet akan berorasi di pihak Mega-Prabowo, tim sukses SBY-Boediono tentu bisa membayar Mandra, misalnya. Lalu JK-Wiranto membayar Jarwo Kuat atau Kelik Pelipur Lara, yang sudah biasa memerankan Jusuf Kalla di "negeri mimpi". Jika bagi pelucu itu disiapkan bahan untuk "menyerang lawan", tidak ada yang tak bisa.
Rupanya kampanye sekarang ini perlu lebih banyak memakai akal-akalan atau mencuri momen karena Komisi Pemilihan Umum begitu mudah dikibuli, termasuk pada acara yang dibuatnya sendiri, meskipun ditutup dengan permintaan maaf.
Cuma, semakin banyak akal-akalan--survei dan polling, gerakan terselubung satu putaran, orasi berbalut seni monolog, perjalanan dinas tapi kampanye, dan banyak lagi--semakin terbuka akal masyarakat bahwa semua calon itu sesungguhnya memamerkan kekurangan akalnya dalam merebut suara rakyat. Kesalahan para calon dan tim suksesnya hanya satu: mengira rakyat itu bodoh, sehingga dipakailah cara kampanye yang bodoh.
(Dari Koran Tempo 14 Juni 2009)
Selasa, Juni 16, 2009
Satu Putaran
Kamis, Juni 04, 2009
Kapongor
Suatu hari ada orang yang bertanya pada saya, apakah benar menanam pohon kelapa di depan rumah bisa kapongor. Apa itu kapongor? Tanya saya memancing, “Dimarahi Bethara,” katanya.
Saya katakan, Bethara tak pernah marah, tetapi kapongor itu betul. Nanti kalau kelapanya berbuah lalu jatuh dan menimpa anak-anak yang masih kecil, kan berbahaya.
Di hari yang lain, seseorang bertanya, apa berani menebang pohon kepuh di setra. Pohon itu sudah tua, kalau dahannya rontok berbahaya buat orang yang ada di bawahnya. Lagi pula di setra akan dibangun balai panjang untuk “mesayuban” dari terik matahari atau hujan. Saya jawab: “Potong saja.” Lalu saya ditanya lagi, apa tidak kapongor? Saya katakan; “Tidak”. Dan betul setelah bertahun-tahun tak ada yang berani menebang pohon kepuh yang dibilang keramat itu, sekarang sudah lenyap. Setra jadi asri dan ada bale “mesayuban”.
Ada lagi yang unik. Seseorang yang baru menjadi nenek konsultasi ke saya, dia mau ke balian. Dia ingin bertanya, siapa nama cucunya yang baik agar anak itu tumbuh sehat dan cerdas di masa depan. Saya tanya dulu, apa bapak dan ibunya sudah memberi nama pada anaknya itu? Sudah, katanya. Nama pemberian orang tuanya cukup panjang: Ni Putu Juniwati Putri Dewi. Nenek itu khawatir nama panjang itu akan membuat keluarga itu kepongor, karena nama-nama leluhurnya hanyalah Wayan Sobret, Ketut Manyong, Nengah Keplug dan sebagainya.
Saya katakan kepada nenek itu: “Jangan sekali-sekali menanyakan nama ke balian, nanti nama itu diganti atau dikatakan jelek. Ini nama bagus sekali, anak itu akan cerdas.” Ketika sang nenek diam, saya katakan lagi; “Kalau tanya ke balian paling disebutkan anak itu keberatan nama, lalu sakit-sakitan. Supaya sehat namanya diganti menjadi Putu Lenjog, malah nanti anak itu jadi malu.”
Kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi di pedesaan. malah ada yang sampai bentrok dalam kekeluargaan. Misalnya soal kawitan, dan ini cerita nyata. Sebuah keluarga ada anaknya yang sakit gatal-gatal, lama tak sembuh. Ditanyakan ke balian, eh, ternyata salah kawitan. Selama ini keluarga besarnya itu termasuk soroh Pasek Bendesa. Menurut balian, seharusnya Pasek Kayu Selem. Keluarga itu mantap pindah kawitan, namun keluarganya yang lain tak mau. Alasannya juga sudah menanyakan ke balian yang lain. Apa yang terjadi? Karena takut kapongor terus-menerus -- yang ditandai dengan sakit gatal itu -- keluarga yang anaknya sakit itu pindah kawitan. Ya, akhirnya pecah dadia, pecah panti dan seterusnya.
Saya mengenal keluarga besar itu dan saya tentu tak mau mencampuri urusan soroh berdasarkan omongan balian. Apalagi seumur-umur saya tak pernah bersinggungan dengan balian. Tapi saya siap menolong keluarga itu.
Pertolongan yang pertama saya lakukan, bukan soal kemana mencari soroh yang benar. Tetapi mengajak anak yang sakit gatal itu ke dokter kulit di Denpasar. Ternyata anak itu mengidap penyakit kulit akibat virus yang memang harus diobati secara benar dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya sakitnya sembuh. Setelah anak itu sehat, kepada keluarga besar itu saya minta mempelajari silsilah kawitan berdasarkan babad yang ada. Nah, terserah mereka untuk memilih, mau ke mana. Yang jelas, tak ada urusan kapongor di sini, yang ada urusan virus yang menyerang kulit yang tak bisa disembuhkan oleh obat dari Puskesmas atau loloh dari balian.
Belum lama ini ada keluarga yang juga “minta izin” ke saya, apa baik menanyakan ke balian, apakah kakek dan neneknya yang baru diaben sudah mendapat tempat yang “pas” di sana. Saya tidak heran soal ini, sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Saya tanya alasannya, meski pun saya sudah bisa menebaknya. “Ya, siapa tahu, banten ngabennya kurang ini kurang itu, atau salah runtutan upacaranya,” katanya. Saya katakan, perbuatan menanyakan ke balian itu justru melanggar ajaran agama. Pertama, karena kita menjadi tidak yakin setiap melaksanakan yadnya. Padahal syarat dari yadnya adalah keyakinan. Kedua, kita tidak tulus menyerahkan urusan ritual kepada Sulinggih yang muput, padahal ketulusan ini utama. Jangan pernah ragu dengan Sulinggih begitu kita memilih beliau untuk muput. Ketiga, tak ada urusan Hyang Pitara atau apapun sebutannya setelah diaben menjadi marah atau tak mendapat tempat yang “pas” hanya gara-gara banten. Keempat, siapa balian itu? Kalau balian itu tak pernah mempelajari tingkat pengabenan, omongannya bisa jadi ngawur.
Masyarakat Bali -- meskipun tidak begitu banyak lagi seperti dulu -- masih percaya pada balian jenis ini. Maksudnya balian untuk meluasang, balian baas pipis, balian dasaran, atau sebutan lainnya. Yakni balian yang entah dengan teknik atau ilmu yang beragam, dipercaya bisa menjadi perantara dari roh orang yang sudah tiada. Atau kalau tidak “kemasukan roh” seolah-olah tahu dan bisa menebak segala sumber yang jadi pangkah masalah “pasiennya”. Dari sinilah kemudian muncul istilah kapongor karena berbagai hal. Kapongor salah upacara, kapongor salah banten, kapongor salah memberi nama dan sebagainya.
Anehnya, jarang sekali balian berkata: “Kamu kapongor oleh Hyang Pitara ini karena suka minum arak, suka berjudi, suka metajen, suka selingkuh, suka narkoba, suka memirat.” Kalau ada balian seperti itu, mungkin baik juga, masyarakat Bali bisa lebih sejahtra.
(Editorial Majalah Hindu Raditya, edisi Juni 2009)
Neolib
Di sebuah warung berlabel “mini market” di kawasan Ubud, Bali, saya terkejut menyaksikan adegan ini. Seorang anak muda tergopoh-gopoh menuju rak obat dan bertanya pada pelayan: “Ada neolib?”
Ia tak bergurau mengucapkan kata itu. Pelayan, perempuan yang juga muda, menjawabnya dengan kalem, jauh pula dari nada canda: “Neolib untuk flu, apa neolib untuk nyeri?” Si lelaki menjawab cepat: “Neolib untuk flu.” Pelayan memberikan satu bungkus tablet bergambar kepala orang. Transaksi terjadi, lalu anak muda itu pergi.
Setengah penasaran saya mendekati pelayan. “Kenapa obat yang sudah populer itu disebut neolib?” Barulah pelayan itu tersenyum, manis juga, dan khas pelayan warung di kawasan pariwisata. “Di sini orang sudah terbiasa dengan plesetan yang dipopulerkan televisi. Semua obat dengan awalan neo disebut neolib, makanya saya tanya, neolib untuk flu atau nyeri. Sering pula disebut neolib tablet atau neolib krim,” ujar si pelayan.
Konon, plesetan itu hanya awalnya saja menimbulkan nada canda. Begitu lewat tiga hari apalagi seminggu, plesetan sudah tak ada nada candanya lagi, sudah biasa-biasa saja. Ternyata banyak juga jenis “plesetan politik”, bukan hanya neolib. Kalau ada orang yang tadinya jarang bergaul atau enggan menyapa, lalu tiba-tiba ramah, orang itu dijuluki: “kerakyat-rakyatan”. Misalnya: “Pak Dogler sekarang kerakyat-rakyatan, pasti ada maunya.”
Anehnya, julukan “kerakyat-rakyatan” hampir selalu berkonotasi negatif. Ada temannya yang lain. Ketika seorang pengendara sepeda motor meraung-raungkan mesin motornya saat melintas di depan mini market itu, petugas parkir berteriak: “lanjutkan, lanjutkan, lebih cepat lebih baik mati”. Begitu pula ketika petugas parkir menggoda cewek, pedagang bakso menggoda: “Pak Parkir, lanjutkan, lanjutkan, mumpung istri tak ada…”
Apa tahu arti neolib? Ini pertanyaan yang saya ajukan kepada pelayan warung, pedagang bakso, dan petugas parkir. Pelayan hanya tertawa karena memang tak tahu. Pedagang bakso juga tertawa, lalu dia bilang: “Saya belum gila, tak perlu neolib”. Dan ini jawaban petugas parkir, agak panjang: “Itu kan dagelan bapak-bapak di televisi. Semua bersilat kata. Semua mengaku pintar. Semua mengaku dekat rakyat. Kita nonton senang saja, banyak kata-kata baru untuk bahan becanda.” Saya tanya, kalau diberi kesempatan bicara, mau bilang apa kepada bapak-bapak itu? Tak lama berpikir, petugas parkir berkata: “Berhenti saja deh ngomong membela rakyat, kok nggak tahu malu ya? Kan kelakuannya sudah diketahui rakyat.”
Malam ini, mungkin besok malam pula, kata neolib boleh jadi masih beredar. Pesaing pasangan SBY-Budiono terus menghunjamkan istilah neolib ini untuk menyerang. Budiono jadi sasaran tembak oleh orang-orang yang berada di kubu JK-Win dan Mega-Prabowo. Tembakan yang berhasil, bukan karena penembak yang piawai, tetapi Budiono mau menyediakan diri bersibuk-sibuk membantah. Ia menari dalam irama gendang lawannya.
Jadi, Budiono memang lugu dan “kurang mahir” berakrobat politik. Bukan saja dituduh membawa paham neolib, tapi juga disebut “mbahnya neolib” atau seperti yang dibilang tim suksesnya Mega-Pro, “ayatulahnya neolib”. Sampai kapan Budiono terus menari?
Padahal, isu neolib sudah ditertawakan masyarakat. Bahkan slogan yang diembel-embeli “kerakyatan” juga dicibir. Orang desa yang lugu bertanya: “Para jenderal yang bertarung itu kok bisa kaya sekali, berapa gajinya sebagai tentara? Sekarang ngaku membela rakyat, apa nggak nilep uang rakyat sebelumnya?” Mungkin ini perlu jawaban.
(Dari Koran Tempo Minggu 31 Mei 2009)
Tentara Kita
Kalau tiba-tiba mendengar ada suara bergemuruh, cobalah segera menatap langit. Siapa tahu ada pesawat terbang yang oleng, lalu menabrak rumah Anda. Peringatan ini ditujukan kepada semua penduduk negeri tanpa kecuali, karena kecelakaan pesawat bisa terjadi di mana saja. Namun, warga yang diam di dekat pangkalan militer, tentu lebih waspada.
Terbakarnya pesawat Hercules di Magetan, pekan lalu, sungguh tragedi yang mengenaskan. Ini kecelakaan pesawat yang ke sekian dengan korban yang banyak. Korbannya tentara kita – lebih akrab disebut begitu dibandingkan Tentara Nasional Indonesia. Juga banyak warga sipil, keluarga tentara dan pemilik rumah yang dilabrak.
Dianalisa dari berbagai sudut, diinvestigasi dari berbagai faktor, tetap muncul sangkaan kuat penyebab jatuhnya pesawat karena usianya yang uzur, perawatannya yang minim, dan mungkin saja suku cadangnya “asli tapi palsu”. Kabut boleh dijadikan kambing hitam, tetapi banyak pesawat tentara kita yang memang sudah tua.
Apa pun hasil investigasinya, saya ikut berbela sungkawa kepada para korban. Hanya, saya menyesalkan ada wakil rakyat yang mendadak menjadi pahlawan, muncul di televisi yang meminta semua pejabat terkait mundur. Dari Kepala Staf TNI AU, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan yang tidak disebutkan, Presiden. Kata wakil rakyat itu, pejabat ini sudah tak punya rasa malu dengan berbagai kecelakaan pesawat yang menewaskan perwira-perwira terbaik tentara kita.
Kalau salah yang dicari, yang benar tidak akan didapat. Siapa yang mengkritisi anggaran pertahanan di DPR? Siapa yang dulu -- dan berulang kali dikatakan – bahwa anggaran pertahanan tak perlu mendapat prioritas? Sudah lama tentara kita tidak mendapatkan prioritas dari sisi anggaran. Di zaman global yang menghormati hak asasi manusia ini, kata sejumlah politisi, tak ada negara menyerang negara. Artinya, faktor ancaman dari luar nol koma kosong. Jadi, lebih baik membangun bendungan, pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pabrik pupuk, dibandingkan membeli senjata termasuk pesawat militer. Di masa damai dan tenang ini, begitu diucapkan, membangun puskesmas dan memperbaiki nasib petani jauh lebih penting dari memikirkan tentara.
Akhirnya, Nusantara ribuan pulau ini punya anggaran pertahanan jauh di bawah Singapura, negeri satu pulau. Tentara kita mulai “tak dianggap”, baik oleh orang luar, juga oleh orang dalam. Dulu, perayaan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober senantiasa ditunggu masyarakat karena akan ada akrobatik udara atau aksi memukau di lautan. Masyarakat bangga, anak-anak kecil pun memakai “baju tentara”. Kini, tak ada lagi. Perayaan 5 Oktober diisi perwira cakep dan cantik melakukan gerakan seragam dengan langkah tegap: satu, dua, satu, dua. Memang ada unjuk ketrampilan, tetapi itu sebatas tentara yang menebas balok es dengan tangan kosong. Kurang membanggakan. Bukan saja balok es lebih murah ketimbang pesawat tempur, ketrampilan itu jamak ada di dunia persilatan, bahkan di pesantren. Lihat di Pasar Senen Jakarta, atau di sepanjang Malioboro Yogyakarta, busana anak-anak dengan atribut militer sudah jauh berkurang dibandingkan dulu.
Saat ini, ketiga pasang calon presiden, semuanya ada unsur tentara. Ada dua mantan jenderal kesohor menjadi calon wakil presiden, ada satu mantan jenderal yang lebih kesohor lagi menjadi calon presiden.. Siapa pun yang terpilih, semestinya bisa berjuang kembali membangun tentara kita. Petani memang perlu disejahtrakan, tetapi tentara juga, karena petani dan tentara adalah juga manusia.
(Dari Koran Tempo Minggu 17 Mei 2009)