Ini bukan iklan politik. Juga bukan iklan caleg-calegan. Ini hanya cerita seorang teman yang gemar sekali mengomentari iklan, tetapi sangat terpengaruh oleh iklan. Bayangkan saja, ia sudah demikian sehat lahir batin, masih saja minum suplemen untuk “keperkasaan laki-laki”. Apanya lagi yang perlu diperkasa?
“Kalau saya tak minum obat kuat itu, kasihan kan produsennya pasang iklan mahal-mahal,” katanya. Artinya, teman saya ini setuju, iklan itu perlu untuk menjual produk. Namun, katanya lagi, kalau usahanya itu sudah monopoli, tak ada saingan sama sekali, ya, untuk apa beriklan? Itu buang-buang duit dan rentan korupsi, apalagi jika itu perusahaan negara. “Contohnya Pertamina, ngapain mengiklankan jual premium? Memangnya kalau tak beriklan, pemilik sepeda motor dan mobil akan membeli premium di kantor telepon?”
Teman saya ini mencatat, hampir semua departemen membuat iklan tak bermutu, pesan yang disampaikan tak sebanding dengan biaya yang milyaran rupiah. Menteri Kesehatan buat iklan untuk hidup sehat, Menteri Olahraga buat iklan untuk berolahraga. Masyarakat kok dianggap bodoh. Mending uang itu langsung dibagikan ke rakyat saja. Yang mereka jual itu sesungguhnya bukan “produk”, tetapi “tampang pengiklan”.
“Lihat di Depok, walikota pasang iklan lewat baliho untuk mengajak rakyat makan pakai tangan kanan. Ini dikaitkan dengan jati diri bangsa. La, senorak itu pesan yang disampaikan, membawa-bawa jati diri bangsa. Memangnya tak ada yang lebih penting dari itu?” kata teman saya.
Iklan politik dan “iklan caleg” (ini sudah populer, maksudnya iklan yang dibuat para calon legislatif) juga menyebalkan di mata teman saya ini. Partai besar membuat iklan yang menyalahkan pemerintah. Janjinya begitu, faktanya begini. “Padahal mereka menyembunyikan fakta penting, yakni pemimpin partai itu sudah pernah memimpin bangsa ini, tetapi ditinggalkan rakyat karena memang tidak berhasil,” katanya.
Iseng-iseng saya bertanya, apakah kegemaran beriklan ini berdampak positif atau buruk? “Positif untuk pemilik televisi, pembuat spanduk dan baliho. Pengiklan belum tentu, bisa positif bisa negatif,” jawabnya. “Lihat iklan caleg, semuanya dengan bahasa pengemis: mohon dukungan, mohon doa restu, tolong pilih saya. Atau bahasa klise yang jadi bahan tertawaan: kami berjuang untuk rakyat, tempat rakyat mengadu, dan sejenisnya. Memangnya rakyat buta dengan kelakuan anggota dewan yang penuh skandal itu?”
“Ah, Anda terlalu jauh, skandal itu kan ulah oknum,” kata saya. “Tapi ini yang melekat di hati rakyat sekarang. Pada saat rakyat sudah berkesimpulan anggota dewan itu brengsek, meski tidak semua, seharusnya cara beriklan itu lain. Begitu pula pada saat pejabat tak bisa memberi contoh baik pada rakyat, jangan beriklan sok menggurui. Pilih makanan yang sehat, cuci tangan pakai sabun, itu kan seolah rakyat bodoh. Masalahnya, apa rakyat punya makanan dan bisa membeli sabun? Ini kan pesan-pesan gombal.”
Wah, saya tak berani mendebat lagi, takut kata yang keluar lebih jorok dari gombal. Lama saya tak ketemu dia, sampai saatnya saya perlu banget dan mengontak handphone-nya. Tak ada jawaban. Berkali-kali saya memutar nomor 0818xxx xxx, tak ada jawaban, padahal ini kartu yang jangkauannya paling luas dan tarifnya konon paling murah. Eh, tiba-tiba dia nongol dan langsung saya semprot: “Saya telepon Anda, kok tak dijawab?” Dia tenang saja: “Gara-gara iklan. Kartu yang saya pakai dulu, sekarang dipakai para monyet, ya, saya ganti, memangnya saya juga monyet?”
(Diambil dari Koran Tempo 7 Desember 2008)
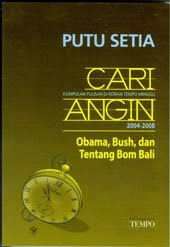


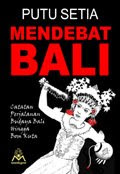

1 komentar:
Lagi jalan-jalan di internet, eh ketemu Pak Putu. Apa kabar Pak? Permisi baca-baca isi blognya ya. Salam dari Pamulang. Mustafa Ismail [ http://jalansetapak.com ]
Posting Komentar