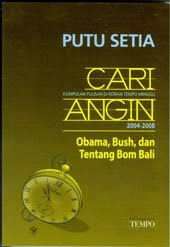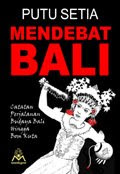Eforia menyambut kemenangan Barack Obama sebagai presiden di Amerika Serikat, tadinya saya pikir hanya milik para eks patriat Amerika yang ada di Bali saja.
Ternyata pendukung Obama ada juga pada supir taksi, pelayan hotel, pedagang kaki lima. Sejumlah siswa di Solo mengibarkan bendera merah putih meneriakkan dukungan pada Obama, bukan kepada Pakubuwono atau Mangkunegoro.
“Saya juga gembira, saya dekat dengan Obama,” kata istri saya. Ah, dari mana dekatnya? “Saya punya teman di Surabaya yang mengirim pesan singkat kemenangan Obama ini. Teman saya itu punya teman yang suaminya berteman dengan orang yang pernah mengenal Obama ketika kecil di Jakarta.”
Weleh-weleh, itu “lelucon Obama” yang melanda dunia. “Orang dungu di Indonesia menyebutnya lelucon. Orang bijak menyebutnya satire, bahwa negeri kita ini tak bisa menampilkan Obama,” kata istri saya, kali ini kok serius banget.
“Obama itu berkulit hitam, bukan bertampang presiden, tetapi bertampang pelatih basket atau peraih medali emas lari seratus meter. Orang Indonesia banyak yang mengira Obama akan kalah telak karena masalah kulit itu. Eh, kok bisa menang? Artinya, asal-usul ras, tak ada masalah di sana.”
Saya masih diam. “Indonesia makin jauh seperti itu. Dulu, orang mengira setelah orde baru runtuh, Indonesia akan mengalami masa emas dalam hal berkebangsaan. Pada masa orde baru masalah Jawa dan non-Jawa jadi polemik. Presiden harus Jawa, wakilnya bolehlah non-Jawa. Apalagi soal agama. Kepala Staf Angkatan Udara sudah diumumkan, eh, bisa dibatalkan gara-gara ketahuan agamanya Hindu. Saat reformasi datang, orang berharap banyak.”
“Ada kemajuan?” saya memberanikan memotong. “Tambah buruk. Malah di era ini muncul peraturan berdasar syariah agama tertentu, muncul kekerasan berwajah agama. Ada Undang-undang Pornografi yang seolah-olah hasrat seksual itu begitu mudahnya bangkit hanya melihat betis, leher, dan rambut wanita. Keindahan ciptaan Tuhan harus ditutup, jika perlu hanya kelihatan mata doang, seperti istri para teroris yang menghabisi puluhan nyawa itu. Masih ingat eksekusi untuk Tibo…?”
“Jangan, jangan teruskan,” kata saya. Istri saya meneruskan: “Lo, saya hanya mengatakan Tibo itu otak perusuh di Poso, lalu dieksekusi tanpa ribut-ribut seperti mengeksekusi ketiga bom Bali….”
“Jangan teruskan!” saya hampir berteriak. “Kamu pasti mengatakan, Tibo dieksekusi dengan lancar karena agamanya itu, ketiga pengebom Bali dieksekusi dengan kehebohan berhari-hari lantaran agamanya ini, dan ketiganya dibela oleh lembaga berlabel agama, menjadi selebritis dan pahlawan, senyumnya terus dipamerkan, gitu kan?”
Saya lalu melunak: “Judul tulisan ini, Obama. Kalau menyerempet Amrozy dan temannya, saya takut, seperti halnya pemerintah yang sangat takut dengan kelompok ini.”
“Ya, kembali ke Obama. Kapan kita punya Obama?” katanya. Saya jawab: “Lo, kita kan sudah berteman secara imajiner dengan Obama. Saya pun dekat dengan Obama, rumah bekas tempat tinggalnya di Menteng sering saya lewati.”
“Ah, capek deh. Kita makin jauh dengan Obama. Made Mangku Pastika memilih jadi Gubernur Bali karena tak mungkin bisa menjadi Kapolri….”
“Lo, jangan mengubah angle, tulisan ini judulnya Obama. Judul Mangku Pastika lain kali, ketika ia ditangkap karena membangkang tidak memberlakukan undang-undang di Bali. Memangnya Bali mau bikin negara sendiri?”
“Kayaknya begitu, diberi peluang, malah didorong ….” Kata istri saya lirih, kata-kata yang masih perlu penjelasan panjang. Ya, angin pancaroba, ke mana engkau bertiup?
(Dikutip dari rubrik Cari Angin Koran Tempo Minggu 9 November 2008)
Selengkapnya