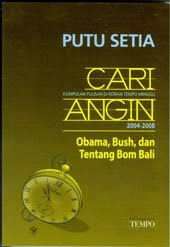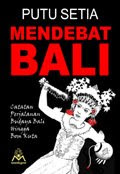Sebuah warung yang menjajakan makanan ringan dan rokok ketengan. Tak ada penunggunya. Pembeli bisa mengambil apa saja, lalu membayar sesuai harga.
Anda pasti menduga ini salah satu dari seribu “Kantin Kejujuran” yang sudah didirikan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Atau Anda mengira ini “Warung Kejujuran” yang ada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah besar. Saya lagi bercerita tentang warung di lereng Gunung Batukaru, Bali, tempat pemukiman para petani kopi yang hidupnya begitu sederhana: miskin tidak, kaya juga belum.
Kenapa warung tidak ditunggui? Alasan yang masuk akal adalah karena warung ini hanya “usaha tambahan” di luar usaha pokok sebagai petani kopi yang sangat disibukkan oleh urusan kecil-kecil. Ada alasan yang “kurang masuk akal” bagi kita yang biasa tinggal di kota. Kalau warung ditunggui, pembelinya malah rikuh berbelanja, tak bebas mengambil jajan ini dan itu, tak bebas makan sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil buang air kecil. Lagi pula, alasan yang lebih tak masuk akal, jika ada penunggu warung, pembeli dan penunggu warung bisa ngobrol lama-lama, tentu akan mengganggu pekerjaan pokok.
Ajaib bin aneh, pemilik warung mengaku tak pernah rugi. Pembeli, yang tak tahu siapa, tak pernah berutang. Uang dimasukkan ke kaleng bekas kotak biskuit. Kata pemilik warung: “Kalau ada orang mengambil jajan di dalam toples dan tidak membayar, kan sama saja dengan kuluk, hina sekali manusia itu.” Apa itu kuluk? Anjing, dalam bahasa setempat.
Bagaimana kalau orang itu mau hina, disamakan dengan anjing, dan menggasak isi warung? “Ada hukum karma, orang itu akan celaka,” kata pemilik warung itu lagi. Kalau dia tak percaya j hukum karma? “Mustahil di sini, di puncak gunung ini ada pura keramat, orang yang curang pasti celaka. Lihat saja, mana ada petani kehilangan buah kopi, padahal kan ditaruh di pinggir jalan tanpa ditunggui,” katanya lagi.
Warung itu salah satu simbul kejujuran komunitas setempat, yang agaknya mereka saling kenal meski jarang kumpul. Kejujuran yang dilandasi suatu keyakinan kuat (atau ketakutan yang kuat), bahwa berbuat curang akan kena kutuk dari “penghuni puncak gunung”. Selain itu, cap manusia hina yang setara dengan kuluk (anjing), sangatlah memalukan. Kalau itu terjadi hanya tersisa dua alternatif: pergi jauh dan tak pernah kembali lagi, atau bunuh diri. Luar biasa.
Manusia perkotaan banyak yang tak merasa hina meski pun korupsi milyaran rupiah. Koruptor, oleh media massa, sering digambarkan sebagai tikus, konon lebih hina dibandingkan anjing. Toh, “manusia tikus” ini masih sulit diberantas, manusia hina ini masih menghuni departemen, lembaga negara, bahkan lembaga wakil rakyat. Di situ tak dikenal hukum karma, juga tak ada “penghuni puncak gunung” yang ditakuti. Kalau pun hukum karma berjalan, itu “lagi apes”, sementara “penghuni puncak gunung” adalah atasannya yang, “ah, tak mungkin pula jujur”.
Warung Kejujuran yang digagas Jaksa Agung tak usah dicela sebagai mengada-ada atau langkah yang “tak ada arti apa-apa”. Gagasan ini tetap bagus sebagai pembelajaran (dan pembiasaan) menegakkan moral jujur. Namun, ini langkah yang sangat kecil untuk menyelamatkan bangsa dari virus korupsi yang kian merajalela. Tetap diperlukan langkah besar. Tetap diperlukan “penghuni puncak gunung” yang tegas menegakkan hukum positif, tak cuma hukum moral seperti hukum karma. Dan koruptor itu, kalau sudah nyata terbukti, mari kita “hinakan” ramai-ramai. Dia tak lagi manusia, tetapi kuluk. Mau? ***
(Diambil dari Koran Tempo edisi 19 Oktober 2008)
Selengkapnya